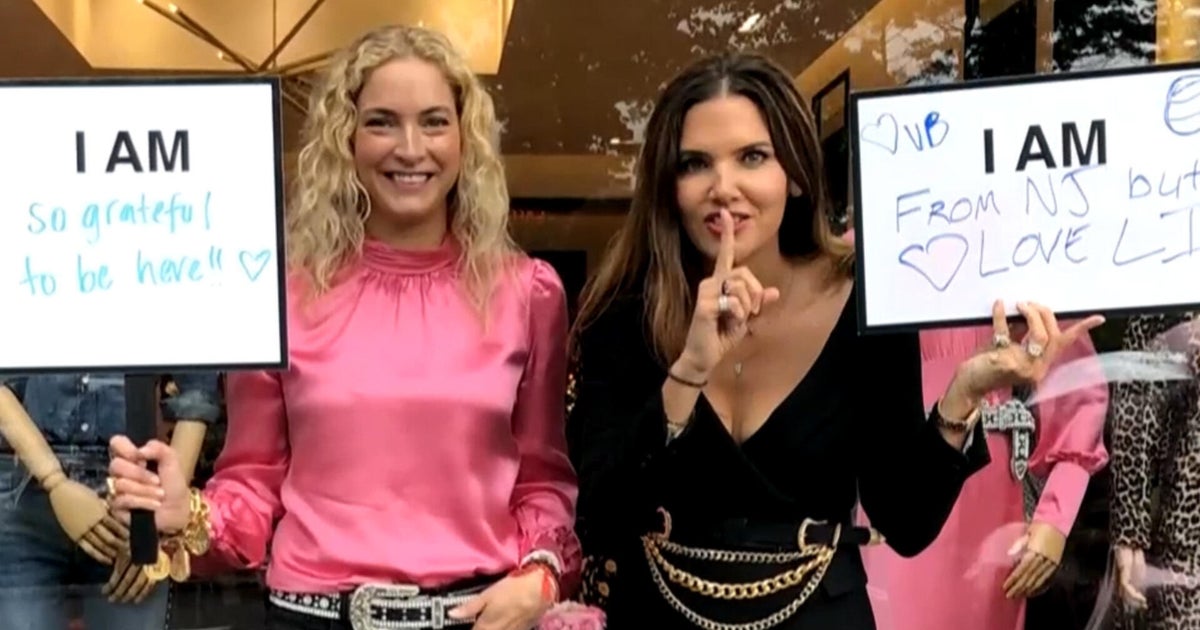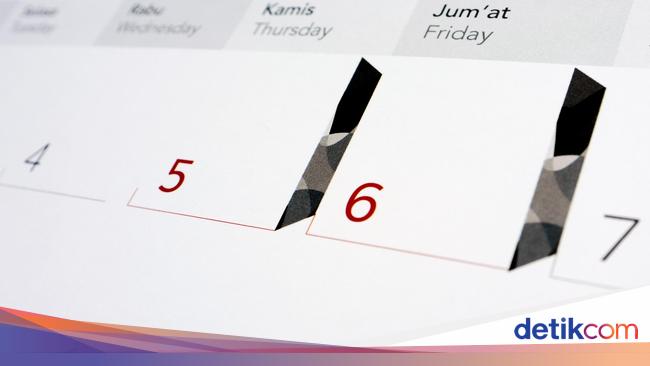Jakarta -
Laporan terbaru Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Monash University Indonesia yang terbit Maret 2025, mengungkapkan bahwa 10,34% dari 479.350 konten politik di media sosial selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mengandung ujaran kebencian (Idris et al., 2025). Angka ini bukan hanya menunjukkan persoalan etika digital, melainkan jejak industri disinformasi yang kian terstruktur.
Ujaran kebencian yang disebarkan melalui media, termasuk media sosial, sering kali dihubungkan dengan disinformasi. Hal ini diperkuat melalui penelitian yang dilakukan Jalli (2024), bahwa melalui narasi yang provokatif, perilaku ini membuka potensi konflik yang lebih besar dan hasutan untuk melakukan kekerasan.
Dari hampir 50 ribu konten ujaran kebencian yang teridentifikasi, sebanyak 15,22% di antaranya menyerang identitas kelompok rentan. Fakta ini tidak bisa dipandang sebagai gangguan sesaat, melainkan sebagai ancaman sistemik terhadap tatanan demokrasi kita.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mekanisme penyebaran disinformasi di Indonesia ternyata mengikuti pola yang telah diidentifikasi oleh laporan yang dibuat Wardle & Derakhshan (2017) untuk Council of Europe. Dalam kerangka konseptualnya, mereka menyampaikan tentang 'information disorder' yang dibedakan dalam tiga bentuk utama, yaitu: misinformasi (informasi salah tanpa niat jahat), disinformasi (informasi salah dengan tujuan manipulasi), dan malinformasi (informasi benar dengan niat merugikan). Ketiganya telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat digital Indonesia.
Disinformasi politik menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, utamanya ketika digunakan sebagai taktik dalam kontestasi politik. Salah satu disinformasi yang muncul adalah sentimen negatif terhadap warga Indonesia keturunan campuran, dengan menyisipkan referensi spesifik ke keturunan Arab dan Tionghoa. Narasi ini berusaha membentuk opini publik dengan menggambarkan imigran sebagai sumber masalah sosial.
Narasi disinformasi tersebut diperparah dengan amplifikasi narasi disinformasi oleh aktor khusus. Masih dari laporan yang dirilish oleh AJI dan Monash University Indonesia, materi disinformasi tersebut disebarluaskan kembali (seperti retweet) oleh jaringan terkoordinasi, termasuk buzzer dan bot. Mereka bahkan merekomendasikan platform media sosial untuk menindak cyber armies yang mengoperasikan akun palsu atau troll yang membuat grup untuk menyebarkan ujaran kebencian dan disinformasi yang menargetkan komunitas rentan. Pola ini menunjukkan evolusi dari sekedar penyebaran hoaks sporadis menuju industri disinformasi yang terstruktur.
Temuan lapangan AJI dan Monash University Indonesia juga memperkuat apa yang disampaikan oleh Lazer et al. (2018), tentang faktor-faktor pendorong penyebaran disinformasi. Desain algoritma platform digital yang memprioritaskan 'engagement' memang terbukti menjadi 'amplifier' alami bagi konten-konten provokatif. Laporan AJI dan Monash University Indonesia mengakui bahwa algoritma dapat berperan dalam diseminasi disinformasi.
Secara spesifik, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa algoritma rekomendasi dapat secara tidak sengaja memperkuat atau mengamplifikasi disinformasi dengan mengelompokkan pengguna berdasarkan minat yang sama dan kemudian mempromosikan konten serupa kepada sesama pengguna, sehingga menciptakan echo chamber dan efek filter bubble. Di sisi penerima, kecenderungan kognitif manusia terhadap bias informasi, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Lazer dkk., membuat informasi yang sesuai dengan prasangka lebih mudah diterima tanpa verifikasi.
Dampak disinformasi ini terhadap tubuh sosial dan politik Indonesia bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan. Tingkat kepercayaan terhadap media arus utama juga dapat merosot, yang selanjutnya menciptakan krisis legitimasi informasi di tengah masyarakat. Ini bisa dilihat dari penelitian AJI tahun 2024 yang menunjukkan, sebanyak 23% masyarakat tidak percaya terhadap media, sedangkan 5,9% lainnya sangat tidak percaya (Akbari et al., 2024).
Yang lebih berbahaya, polarisasi sosial akibat disinformasi ini tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga merambah ke interaksi sosial nyata. Ini terlihat dalam peningkatan ketegangan antar kelompok di berbagai daerah. Misalnya insiden pengeroyokan dan pembacokan pendukung pasangan calon di Pilkada Sampang, pada 2024 lalu (Aziz, 2024).
Penelitian tentang manipulasi media pernah dilakukan oleh Marwick & Lewis (2017). Mereka memperingatkan tentang Teknik "amplification for effect" yang digunakan oleh aktor-aktor disinformasi. Ini juga terlihat pada laporan AJI dan Monash University Indonesia yang menemukan pola terorganisir beberapa akun inti bertindak sebagai penyebar utama, kemudian dibantu puluhan akun lain untuk memperkuat penyebaran. Model jaringan seperti ini membuat konten bermasalah bisa mencapai ribuan orang dalam waktu singkat.
Di tengah tantangan ini, upaya penanganan disinformasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural. UU ITE yang ada saat ini belum mampu menjangkau pelaku intelektual di balik industri disinformasi. Platform media sosial juga belum sepenuhnya transparan dalam kebijakan moderasi konten mereka. Sementara itu, program literasi digital yang ada masih terlalu fokus pada aspek teknis verifikasi fakta, tanpa menyentuh aspek psikologis dan sosiologis yang lebih dalam.
Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang memadukan berbagai elemen. Pertama, penguatan regulasi yang tidak hanya fokus pada konten, tetapi juga pada jaringan penyebaran dan pembiayaan disinformasi. Kedua, peningkatan literasi digital yang tidak hanya mengajarkan cara mengenali hoaks, tetapi juga memahami mekanisme psikologis dan ekonomi politik di balik disinformasi. Ketiga, kolaborasi erat antara pemerintah, platform teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem deteksi dini dan respons cepat.
Pengalaman Pilkada 2024 harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Disinformasi digital telah berevolusi menjadi ancaman nyata yang tidak hanya merusak proses demokratis, tetapi juga merongrong fondasi sosial masyarakat Indonesia. Sebagaimana diingatkan oleh Lazer dkk., pertarungan melawan disinformasi pada hakikatnya adalah upaya mempertahankan integritas ruang publik demokratis. Tanpa upaya serius dan sistematis dari semua pemangku kepentingan, masa depan demokrasi digital Indonesia akan terus berada dalam ancaman.
Dhana Adhipratama, Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia
(sls/Dhana Adhipratama)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini