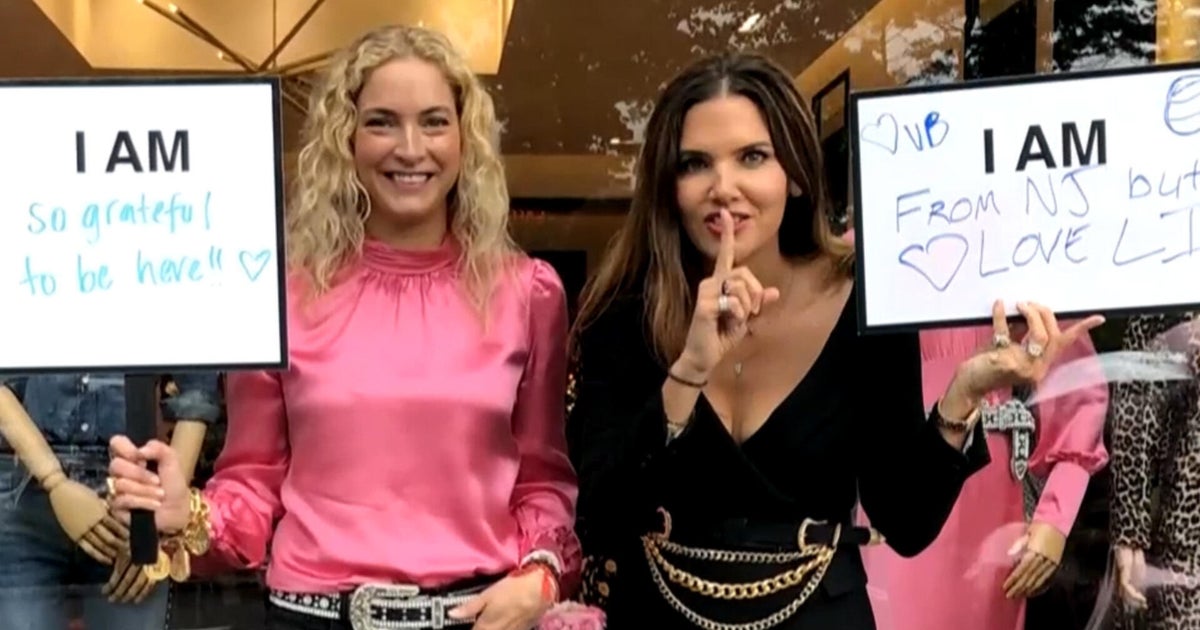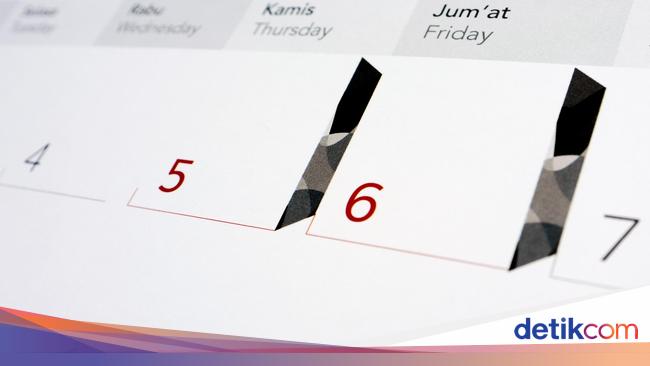Saat pandemi COVID-19 melanda, Novan justru terserang penyakit lain yang tak kalah mengancam: tuberkulosis paru. Ia baru berusia 23 tahun saat tubuhnya mulai menunjukkan gejala yang membuatnya kelimpungan.
"Awalnya kata dokter sih dari lambung. Terus gue tiba-tiba tuh nggak ada demam, nggak ada apa, tenggorokan gue gatal. Terus gue batuk, keluar darah tuh. Kaget," ujar Novan kepada detikX mengenang awal mula penyakitnya.
Meski kaget, ia tidak langsung memeriksakan diri. Sampai akhirnya gejala makin parah. Setiap petang tubuhnya melemah. Dada terasa panas, punggung serasa ditusuk, dan ia mengalami kesulitan bernapas. Ia sempat menduga terinfeksi COVID-19 karena kesamaan gejala. Namun hasil pemeriksaan di berbagai rumah sakit menunjukkan hasil berbeda, mulai dugaan jantung hingga lambung, belum ada yang menyebutkan tuberkulosis.
"Ketemu-ketemunya gue di Puskesmas Kebon Jeruk tuh yang disebut TB. Ada kali tuh tujuh rumah sakit gue datengin dulu tuh sebelum ke puskesmas," tuturnya.
Sebelumnya, ia ditolak saat berobat ke Puskesmas Kembangan karena menyebutkan gejala batuk darah dan sesak napas. Dua gejala yang saat itu langsung diwaspadai sebagai COVID-19.
"Udah deh, nggak boleh masuk gue, langsung disuruh ke rumah sakit," ucapnya.
Perjalanan diagnosis yang berliku ini bukan hanya menguras fisik dan mental, tapi juga finansial. Sebelum beralih ke layanan BPJS Kesehatan, Novan membayar pengobatan dari kantong pribadi.
"Abis-abisan itu gue, Bang. Sekitar Rp 15 (juta)-lah. Sampai gue gadein kamera, handphone dua, buat pengobatan," ungkapnya.
Ia mengaku sempat takut menggunakan BPJS karena mengira pelayanannya tidak maksimal. Namun, ketika dana menipis, ia akhirnya mencobanya dan ternyata bisa menjalani pengobatan dengan rutin.
Selama enam bulan pengobatan, ia mengonsumsi berbagai jenis obat yang terus berganti dosis. Sampai akhirnya dinyatakan sembuh.
"Dari (obat) yang gede ke kecil tuh, itu selama 6 bulan," ungkapnya.
Novan tak sendiri. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan, sepanjang 2024 hingga Maret 2025, sebanyak 23.858 pasien meninggal dunia karena TBC. Jumlah keterjangkitan TBC mencapai 1.016.475 kasus (855.420 pada 2024 dan 161.055 hingga 17 Maret 2025). Secara umum, tren penemuan kasus TBC meningkat tajam sejak 2017, dari 446.732 kasus menjadi lebih dari dua kali lipat dalam tujuh tahun.
Lonjakan ini dapat mencerminkan dua kemungkinan: pertama, beban penyakit TBC di masyarakat memang besar; kedua, kemampuan sistem kesehatan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus telah meningkat pesat. Namun tidak tertutup kemungkinan kedua faktor tersebut terjadi bersamaan, yaitu peningkatan kasus nyata di lapangan sekaligus kemampuan deteksi yang membaik.
Pemerintah sebenarnya memperkirakan, pada 2024 terdapat lebih dari 1,09 juta orang terinfeksi penyakit menular ini. Namun, dari jumlah itu, tak sampai 900 ribu kasus yang bisa ditemukan dan dilaporkan ke sistem kesehatan. Artinya, sekitar 22 persen kasus masih luput dari pencatatan, entah karena pasien belum terdeteksi atau tak pernah sampai ke layanan kesehatan.
Tantangan tak berhenti di sana. Dari kasus yang ditemukan, lebih dari 12 ribu pasien terkonfirmasi menderita TB resisten obat. Bentuk TB yang lebih sulit dan mahal untuk diobati karena pengidap terindikasi resisten beberapa jenis obat. Sayangnya, dari jumlah itu, hanya sekitar 9.500 pasien yang bisa diikutkan dalam program pengobatan khusus TB RR/MDR.
Menurut Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia dr Henry Diatmo, kasus TBC di Indonesia diperkirakan menyebabkan 134 ribu kematian dalam satu tahun.
“Angkanya (kematian) yang sekarang 134 ribu dalam setahun, angka kasusnya (TB) 1.090.000. Sangat tinggi. Kalau hitungan jamnya, itu 17 kematian setiap jam," ungkapnya kepada detikX saat dihubungi via telepon, Jumat pekan lalu.
Henry menyebut Indonesia kini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam jumlah kasus TBC, setelah India. “Dulu kita pernah di posisi 5. Sekarang kita di posisi kedua, karena ternyata negara-negara yang lain itu berhasil mengupayakannya (penurunan kasus),” jelasnya.
Tingginya angka penularan TBC di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh karakteristik penyakit yang menular lewat udara, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap TBC juga dinilai rendah. Penyakit ini sering kali dianggap remeh karena sudah lama dikenal.
“Kalau ngomongin TBC, dianggap hal biasa. Padahal ini bukan hal yang biasa. Kalau dianggap hal yang biasa, kenapa angkanya naik terus?” ujarnya.
Ia menegaskan, walaupun pengobatan tersedia dan TBC bisa disembuhkan, banyak penderita yang tidak menjalani pengobatan hingga tuntas, sehingga menimbulkan resistensi dan menjadi sumber penularan. Pandangan bahwa TBC hanya menyerang kelompok ekonomi menengah ke bawah juga keliru.
Indonesia bersama komunitas global sebetulnya telah menetapkan target eliminasi TBC pada 2030. Namun, dengan sisa waktu lima tahun menuju target tersebut, tantangan masih sangat besar. Salah satu harapan terbesar kini datang dari pengembangan vaksin TBC. “Itu yang diharapkan saat ini karena vaksin itu cenderung membuat pencegahan awal ya. Artinya, supaya nanti gak jadi sakit,” jelas dr. Henry.
Sementara itu, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Ina Agustina Isturini menegaskan Indonesia masih berada dalam situasi darurat tuberkulosis (TBC). Menurut estimasi global tahun 2023, terdapat 10,8 juta orang sakit TBC di seluruh dunia, dan Indonesia memiliki kontribusi 10,1 persen dari total kasus.
Ia menjelaskan penemuan kasus TBC di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, tetapi masih jauh dari harapan. Pada 2024, penemuan kasus mencapai 78 persen atau sekitar 856 ribu kasus. Angka ini meningkat dari 77 persen pada 2023, dan jauh lebih tinggi dibanding masa pandemi COVID-19, ketika penemuan kasus hanya 46–48 persen. Meski begitu, angka ini masih di bawah target minimal 90 persen.
“Dari kasus yang ditemukan, ditargetkan paling tidak 95 persen harus diobati. Tahun ini kita baru mencapai 92 persen. Tahun lalu hanya 88 persen, jadi memang ada peningkatan, tapi belum sesuai harapan,” kata Agustina kepada detikX pekan lalu.
Keberhasilan pengobatan juga menjadi indikator penting. Untuk TBC sensitif obat, target keberhasilan pengobatan adalah 90 persen. Namun, pada 2024, capaian nasional hanya 85 persen. Sementara itu, untuk TBC resisten obat (TBC-RO), target keberhasilan adalah 80 persen, tapi realisasi hanya 59 persen. Pencegahan penularan TBC melalui terapi pencegahan bagi kontak erat juga masih belum optimal. Cakupan hanya 19,4 persen dari target 50 persen.
“Penularan masih berlangsung, sehingga kami banyak mengupayakan kegiatan inovatif dan akselerasi agar penemuan kasus dan pengobatan bisa optimal,” ujarnya.
Secara khusus Ina mengatakan TBC-RO merupakan tantangan besar dengan rata-rata kontribusi sekitar 1,4-1,5 persen dari seluruh kasus TBC. Pada 2024, tercatat 12.400 kasus TBC-RO dari 856 ribu kasus TBC. Indonesia termasuk lima besar negara dengan masalah TBC-RO. "Obatnya lebih kompleks, mahal, dan butuh waktu lebih lama, serta memiliki risiko kematian yang lebih tinggi," katanya.
Menurutnya, tingginya penularan TBC di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kepadatan penduduk dan persepsi masyarakat. “Masih banyak yang menganggap TBC itu penyakit keturunan, tidak bisa disembuhkan, mahal, atau bahkan penyakit guna-guna,” jelasnya.
Upaya pemerintah Indonesia dalam mengendalikan TBC pada 2024 menunjukkan capaian yang belum merata di seluruh provinsi. Berdasarkan data final yang dirilis Kementerian Kesehatan, cakupan penemuan kasus TBC secara nasional baru mencapai 78 persen, masih berada di bawah target 90 persen.
Cakupan penemuan kasus TBC mengukur seberapa banyak penderita TBC yang bisa ditemukan dan didiagnosis oleh layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita sebenarnya di suatu daerah. Misalnya, jika di suatu provinsi diperkirakan ada 10 ribu orang yang menderita TBC dan layanan kesehatan berhasil menemukan dan mencatat 9.000 kasus, jadi cakupannya adalah 90 persen.
Semakin tinggi cakupan ini, semakin besar peluang penderita mendapat pengobatan dan mencegah penularan ke orang lain. Pemerintah menargetkan cakupan penemuan kasus sebesar 90 persen pada tahun ini.
Beberapa provinsi mencatat keberhasilan tinggi dalam penemuan kasus, seperti Nusa Tenggara Barat (116%), Jambi (107%), dan DKI Jakarta (100%). Namun Papua Pegunungan (27%), Bengkulu (33%), dan Kepulauan Riau (52%) menunjukkan performa yang sangat rendah.
Tak hanya dalam penemuan kasus, masalah juga terlihat pada keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat (TB SO). Capaian nasional hanya mencapai 86 persen, di bawah target 90 persen. NTB kembali menjadi provinsi dengan capaian tertinggi (95%), sementara Papua Pegunungan dan Papua menjadi yang terendah dengan tingkat keberhasilan masing-masing hanya 21 persen dan 44 persen.
Situasi lebih mengkhawatirkan terjadi pada penanganan TBC resisten obat (TBC RO). Tingkat enrollment rate pasien TBC RO secara nasional hanya 79 persen, jauh dari target 95 persen. Provinsi seperti NTT dan Sumatera Barat berhasil melampaui target, tetapi Papua Barat Daya dan Papua kembali mencatat capaian terendah, masing-masing 52 persen dan 58 persen.
Capaian keberhasilan pengobatan TBC RO juga masih memprihatinkan. Secara nasional hanya 59 persen pasien yang dinyatakan sembuh atau berhasil menyelesaikan pengobatan, dari target 80 persen. Beberapa provinsi, seperti Bengkulu (77%) dan NTT (72%), mencatat hasil baik, tapi Papua Pegunungan (33%), Papua Barat Daya (38%), dan Papua (39%) mencatat hasil paling rendah secara nasional.
Sistem kesehatan pun, kata Agustina, menghadapi kendala. Seperti pencatatan kasus yang belum terintegrasi, keterlibatan fasilitas kesehatan swasta yang belum optimal, dan tantangan geografis yang menyulitkan distribusi pengobatan jangka panjang.
“Kita juga masih menghadapi masalah kualitas pelayanan, sistem rujukan, dan tenaga kesehatan,” jelasnya.