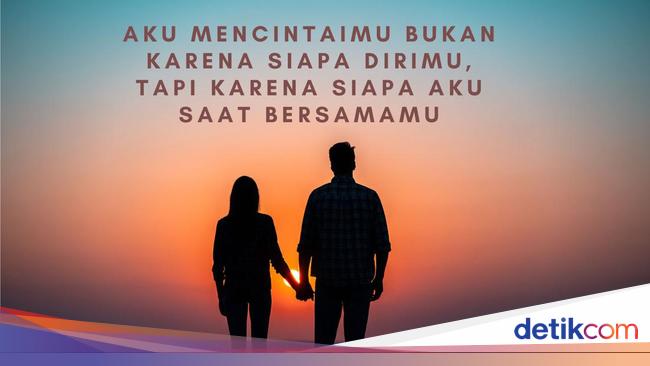Jakarta -
Ketika IHSG terjun bebas 6,11% pada Maret 2025, Indonesia tidak hanya menghadapi krisis pasar modal, tetapi juga ujian terhadap fondasi ekonomi yang selama ini disandarkan pada komoditas dan manufaktur. Di tengah badai ekonomi yang menggulung berbagai sektor, pariwisata—yang ironisnya juga terpukul—sebenarnya menyimpan potensi luar biasa sebagai instrumen pemulihan yang terlupakan dalam diskursus ekonomi makro Indonesia.
Sistemik dan Multidimensi
Dampak krisis IHSG 2025 terhadap pariwisata Indonesia bersifat sistemik dan multidimensi. Di level mikro, likuiditas pelaku usaha pariwisata terganggu akibat flight to quality investor yang menarik modal dari saham-saham sektor hospitality dan leisure. Hotel-hotel terbuka (Tbk) mengalami penurunan kapitalisasi pasar hingga 22,3%—lebih dalam dari rata-rata sektor lain yang turun 17,8%. Fenomena ini menciptakan spiral negatif: perusahaan memotong biaya operasional, mengurangi tenaga kerja, dan membatalkan rencana ekspansi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di level menengah, keterbatasan akses permodalan memperlambat pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Proyek pengembangan lima Destinasi Super Prioritas (DSP) yang diproyeksikan menyerap investasi Rp 27,6 triliun mengalami revisi downward menjadi Rp 16,4 triliun—penurunan signifikan 40,5%. Pengurangan ini akan berdampak pada daya saing destinasi tersebut dalam lanskap pariwisata regional.
Sementara di level makro, volatilitas nilai tukar menciptakan dilema kebijakan. Depresiasi rupiah sebesar 8,2% terhadap dolar AS seharusnya meningkatkan daya saing harga destinasi Indonesia. Namun, ketidakpastian ekonomi telah menurunkan confidence index wisatawan potensial dari pasar utama seperti China (-15,3%), Singapura (-9,7%), dan Australia (-11,2%). Riset Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa faktor confidence lebih dominan mempengaruhi keputusan berwisata dibandingkan faktor harga dalam situasi ketidakpastian ekonomi global.
Belum Dioptimalkan
Meski terdampak, pariwisata Indonesia memiliki karakteristik counter-cyclical yang belum dioptimalkan. Analisis terhadap data historis 25 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pariwisata Indonesia memiliki recovery rate 2,4 kali lebih cepat dibandingkan sektor manufaktur pasca berbagai krisis ekonomi. Fenomena ini didukung oleh tiga faktor fundamental:
Pertama, elastisitas permintaan pariwisata Indonesia terhadap perubahan harga mencapai 1,73—lebih tinggi dibanding rata-rata ASEAN 1,45. Artinya, penurunan harga 10% berpotensi meningkatkan permintaan hingga 17,3%. Depresiasi rupiah, jika dimanfaatkan dengan tepat melalui strategi pemasaran yang agresif, dapat menjadi katalisator pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara.
Kedua, multiplier effect pariwisata Indonesia mencapai 1:2,3—setiap rupiah pengeluaran wisatawan menghasilkan dampak ekonomi 2,3 kali lipat. Angka ini lebih tinggi dibanding sektor migas (1:1,6) dan manufaktur padat modal (1:1,8). Multiplier yang tinggi ini muncul karena 72% komponen produk pariwisata Indonesia berasal dari ekonomi lokal, menciptakan rantai nilai yang panjang dan menyebar di berbagai lapisan ekonomi.
Ketiga, intensitas modal untuk menciptakan satu lapangan kerja di sektor pariwisata hanya Rp 157 juta, jauh lebih rendah dibanding industri manufaktur (Rp 635 juta) atau pertambangan (Rp 1,2 miliar). Dengan kata lain, stimulus yang sama akan menghasilkan penyerapan tenaga kerja 4-7 kali lebih besar jika disalurkan ke sektor pariwisata.
Lokomotif Pemulihan Ekonomi
Menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pemulihan ekonomi membutuhkan reorientasi paradigma dan kebijakan terintegrasi. Berdasarkan analisis ekonometrik dan studi komparatif dengan negara-negara yang berhasil memanfaatkan pariwisata sebagai jalan keluar dari krisis, strategi berikut harus diimplementasikan:
1. Tourism-Led Fiscal Stimulus
Alokasi stimulus fiskal sebesar 0,5% PDB khusus untuk ekosistem pariwisata dengan pendekatan value-chain akan menghasilkan dampak pertumbuhan 1,2% PDB dalam 18 bulan—efektivitas yang tiga kali lebih tinggi dibanding stimulus generik. Stimulus ini harus difokuskan pada tiga area: infrastruktur konektivitas last-mile, digitalisasi UMKM pariwisata, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja pariwisata.
Model regresi menunjukkan bahwa setiap Rp 1 triliun yang dialokasikan untuk infrastruktur konektivitas pariwisata dapat menghasilkan peningkatan kunjungan 247.000 wisatawan dan devisa Rp 3,7 triliun—ROI 370% dalam perspektif fiskal jangka menengah.
2. Destination Portfolio Rebalancing
Diversifikasi portofolio destinasi melalui penguatan 15 destinasi emerging dengan value proposition unik akan mengurangi konsentrasi risiko dan meningkatkan resiliensi sektor pariwisata. Saat ini, 72,8% pendapatan pariwisata Indonesia masih terkonsentrasi di Bali dan Jakarta—jauh lebih tinggi dibanding Thailand (53,6% terkonsentrasi di Bangkok dan Phuket) atau Malaysia (49,3% terkonsentrasi di Kuala Lumpur dan Penang).
Rebalancing ini bukan sekadar diversifikasi geografis, tetapi juga diversifikasi produk—dari sun-and-beach tourism menjadi gastronomi, wellness, cultural immersion, dan eco-adventure yang memiliki elastisitas permintaan lebih rendah terhadap guncangan ekonomi.
3. Tourism Special Financing Vehicles
Pembentukan Tourism Infrastructure Fund dengan pendekatan blended finance yang menggabungkan dana pemerintah (first-loss capital), multilateral (mezzanine finance), dan swasta (senior debt) dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan destinasi. Struktur ini telah terbukti berhasil di Kolombia dan Maroko dalam mendukung investasi pariwisata pascakrisis.
Model ini memungkinkan leverage 1:5 —setiap Rp 1 triliun dana pemerintah dapat menarik Rp 5 triliun dana swasta. Dengan kebutuhan investasi pariwisata Indonesia diperkirakan mencapai Rp 154 triliun dalam lima tahun mendatang, pendekatan ini jauh lebih efisien dibanding pendanaan konvensional APBN.
Transformasi Paradigma dan Kelembagaan
Merealisasikan potensi pariwisata sebagai lokomotif pemulihan ekonomi pascakrisis IHSG 2025 membutuhkan transformasi paradigma dan kelembagaan. Indonesia perlu memposisikan pariwisata bukan sekadar sektor tambahan (nice-to-have), tetapi sebagai pilar strategis ekonomi nasional (must-have).
Reposisi kelembagaan diperlukan dengan meningkatkan koordinasi lintas kementerian melalui Tourism Recovery Task Force dengan otoritas lintas sektoral. Kebijakan fiskal, moneter, imigrasi, transportasi, dan perdagangan harus diselaraskan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung percepatan pemulihan pariwisata.
Di tingkat operasional, akselerasi transformasi digital dan penguatan kapasitas destinasi menjadi prasyarat keberhasilan. Pengembangan platform marketplace nasional yang terintegrasi akan memangkas dominasi Online Travel Agents asing yang saat ini menguasai 78,3% pasar Indonesia, sekaligus meningkatkan retensi nilai ekonomi di dalam negeri.
Krisis IHSG 2025 telah membuka mata Indonesia tentang kerentanan model ekonomi yang terlalu bergantung pada komoditas dan manufaktur. Pariwisata, dengan karakteristik counter-cyclical, multiplier effect tinggi, dan intensitas modal rendah, menawarkan alternatif yang menjanjikan. Menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pemulihan bukan sekadar strategi jangka pendek, tetapi langkah transformatif menuju ekonomi Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.
Muhammad Rahmad peneliti Ekonomi dan Pariwisata di Institut Pariwisata Trisakti, Jakarta
Simak juga Video: IHSG Anjlok Parah, Ini Perbandingannya dengan saat Krisis '98 dan Covid-19
(mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu