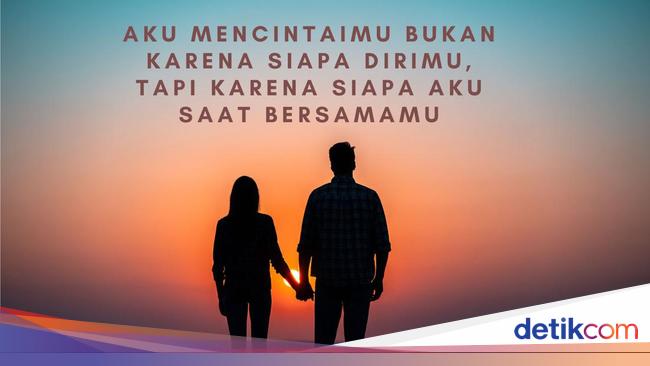Jakarta -
Isu mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke permukaan. Sekilas, perdebatan ini tampak seperti bagian dari dinamika politik yang wajar dalam demokrasi. Namun jika dicermati lebih dalam, tuduhan tersebut sesungguhnya mengandung kekeliruan logika yang serius dan berbahaya: ia tidak hanya menyesatkan akal sehat publik, tetapi juga mengikis dasar kepercayaan sosial yang menjadi perekat kohesi bangsa.
Dalam ranah logika, tuduhan palsunya ijazah Presiden Jokowi tanpa bukti valid merupakan bentuk dari logical fallacy atau kesesatan berpikir. Tepatnya, ini termasuk dalam jenis argumentum ad ignorantiam, yaitu menganggap sesuatu itu salah atau benar karena belum dibuktikan sebaliknya.
Di balik tuduhan ini, tersembunyi asumsi keliru: "karena saya belum melihat ijazah asli Jokowi, maka itu palsu." Padahal, dalam hukum, filsafat ilmu, maupun kaidah epistemologis, beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh. Tanpa bukti tandingan yang sahih, tuduhan tersebut secara otomatis gugur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fakta Tak Bisa Dilangkahi oleh Praduga
Untuk mengingatkan, ijazah Jokowi telah diverifikasi secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), almamater Jokowi. Pihak fakultas, dosen pengajar, serta rekan seangkatan telah membenarkan bahwa Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980.
Data tersebut tercatat dalam sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bahkan dalam berbagai dokumen resmi kenegaraan, seperti lembar biodata capres-cawapres di KPU, ijazah tersebut digunakan dan tidak pernah dibatalkan secara hukum.
Dalam dunia akademik maupun peradilan, sebuah fakta hanya bisa diragukan apabila muncul fakta baru yang memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat. Sebuah ijazah tidak bisa dianggap palsu hanya karena muncul video YouTube atau opini sepihak.
Jika ada pihak yang meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, maka yang harus dilakukan adalah menghadirkan dokumen pembanding – ijazah lain atas nama Joko Widodo yang berbeda, atau bukti otentik bahwa Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Hingga kini, tidak ada satu pun bukti alternatif seperti itu yang muncul.
Sebaliknya, berbagai klarifikasi dan konfirmasi telah dikeluarkan oleh institusi resmi. Bukan hanya baru-baru ini, bahwa pada 2022, pihak UGM sudah menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni mereka. Rektor UGM, Panut Mulyono, menyampaikan, "Bapak Joko Widodo adalah benar lulusan kami. Kami punya semua catatannya, termasuk tugas akhir beliau." Pernyataan ini konsisten dengan data administrasi kampus dan testimoni dosen pembimbingnya, Prof. Yanto Santosa.
Bahayanya bagi Kohesi Sosial
Isu pemalsuan ijazah terhadap tokoh publik bukan barang baru. Di luar negeri, beberapa pejabat mundur karena ketahuan benar-benar memalsukan gelar akademik, seperti Karl-Theodor zu Guttenberg, Menteri Pertahanan Jerman pada 2011, yang mengundurkan diri karena terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasi doktornya.
Tapi yang perlu dicatat: dalam kasus-kasus tersebut, ada bukti akademik konkret berupa plagiarisme yang diverifikasi oleh otoritas kampus.
Bandingkan dengan situasi Jokowi. Tidak ada lembaga resmi mana pun – baik universitas, Kementerian Pendidikan, KPU, atau MA – yang menyatakan ijazah tersebut bermasalah. Bahkan, Mahkamah Agung telah menolak gugatan perdata terkait ijazah Jokowi karena tidak berdasar dan tidak memiliki cukup bukti (Putusan MA No. 225 K/Pdt/2023).
Maka, berulang-ulangnya isu ini dimunculkan hanyalah bentuk character assassination yang merusak iklim demokrasi. Lebih berbahaya lagi, ini menjadi celah untuk merusak trust atau kepercayaan publik terhadap institusi.
Francis Fukuyama dalam bukunya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995) menyatakan bahwa negara yang masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap institusi akan lebih stabil, inovatif, dan maju secara ekonomi. Ketika masyarakat dicekoki teori konspirasi dan praduga tanpa dasar, trust publik terhadap pemerintah dan institusi akan hancur.
Dampak Polarisasi Terhadap Kepercayaan Sosial
Persoalannya, bukti empiris menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap tokoh publik berkorelasi dengan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga negara.
Survei Edelman Trust Barometer 2024 menunjukkan bahwa 61% masyarakat di negara-negara berkembang mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi akibat derasnya penyebaran disinformasi. Indonesia masuk dalam kategori negara dengan trust index menengah, tetapi dengan kerentanan tinggi terhadap hoaks, khususnya menjelang pemilu.
Sementara itu, survei LSI Denny JA pada akhir 2023 mencatat bahwa 41% responden ragu terhadap berita di media sosial yang menyerang pejabat publik, tetapi 31% mengaku mempercayai narasi tersebut jika disebarkan oleh tokoh publik atau influencer yang mereka ikuti. Ini menunjukkan bahwa hoaks memiliki daya rusak serius terhadap kepercayaan sosial dan pemahaman rasional publik.
Ironisnya, isu seperti ini mengaburkan debat publik yang lebih substansial. Alih-alih membahas isu-isu strategis seperti transisi energi, ketahanan pangan, atau reformasi hukum, ruang publik justru diramaikan dengan debat tak produktif soal validitas ijazah yang telah diverifikasi. Inilah bentuk nyata dari anti-intellectualism dalam demokrasi: ketika debat rasional dikalahkan oleh sensasi.
Situasi ini juga berbahaya karena mendorong pembentukan echo chamber di media sosial. Pengguna hanya terpapar informasi yang memperkuat keyakinannya, tanpa sempat menguji validitasnya secara kritis. Akibatnya, ruang publik tidak lagi menjadi tempat tukar gagasan, tetapi ladang fitnah dan prasangka.
Mengembalikan Rasionalitas dalam Wacana Publik
Sebagai gambaran, lebih dari 85 juta suara diraih Joko Widodo dalam Pilpres 2019 – sebuah capaian demokratis yang bukan hanya mencerminkan besarnya dukungan rakyat, tetapi juga menggambarkan berjalannya proses verifikasi administratif yang sangat ketat dan berlapis.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu, memverifikasi semua berkas pencalonan, termasuk keabsahan ijazah, melalui koordinasi dengan institusi pendidikan, instansi pemerintahan, dan lembaga negara lainnya.
Artinya, kemenangan Jokowi tidak mungkin lahir tanpa melalui sistem pengawasan formal yang sahih. Meragukan keabsahan dasar administratif seperti ijazah tanpa bukti valid bukan hanya keliru, tetapi juga merupakan bentuk disinformasi yang membahayakan nalar publik dan menyesatkan persepsi demokratis.
Kita bisa menarik pelajaran dari pengalaman global. Di Amerika Serikat, selama dua periode kepresidenan Barack Obama, muncul teori konspirasi yang menuduh bahwa ia bukan warga negara Amerika, dan karena itu tidak sah menjadi presiden.
Tuduhan ini tidak pernah terbukti, namun terus dipelihara oleh kelompok politik tertentu untuk merusak legitimasi Obama dan memperkuat polarisasi masyarakat. Kampanye "birtherism" ini kemudian diakui sebagai salah satu bentuk disinformasi politik paling destruktif di era modern.
Tuduhan terhadap keaslian ijazah Jokowi menempati spektrum yang serupa – menciptakan keraguan terhadap legitimasi dengan cara menyebarkan narasi palsu. Kedua kasus di atas, menunjukkan bagaimana teori konspirasi yang tidak berbasis bukti bisa merusak kepercayaan publik, menumpulkan akal sehat kolektif, dan mengganggu ketertiban demokrasi.
Pada akhirnya, tuduhan pemalsuan ijazah tanpa bukti tidak boleh lagi diberi ruang dalam demokrasi yang sehat. Demokrasi dibangun di atas fondasi nalar, bukan prasangka. Setiap tuduhan harus diuji secara hukum dan disertai bukti yang otentik.
Jika logika publik terus dikotori oleh narasi tanpa dasar yang kokoh, kita bukan hanya sedang menurunkan standar berpikir bangsa, tetapi juga mengubah demokrasi dari arena pertukaran gagasan menjadi pasar rumor. Ini adalah kemunduran yang serius dan berpotensi merusak ketahanan sosial-politik bangsa.
Kita harus mulai menata ulang cara kita berinteraksi dengan informasi. Literasi digital dan pendidikan publik harus diperkuat untuk membangun daya tangkal masyarakat terhadap hoaks dan narasi menyesatkan.
Media pun perlu mengambil posisi lebih tegas. Tidak semua isu layak diberitakan, apalagi jika tidak berbasis fakta. Memberi ruang pada disinformasi dalam nama "keseimbangan berita" hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis.
Kritik terhadap pemimpin negara adalah hak demokratis, tapi harus dibedakan dari fitnah. Kita boleh dan harus mengkritik kebijakan, integritas, bahkan gaya kepemimpinan, selama hal itu dilakukan dengan nalar jernih dan data yang valid. Menyeret kembali isu ijazah tanpa bukti autentik bukanlah kritik – itu adalah serangan terhadap akal sehat publik dan bentuk degradasi dalam diskursus kebangsaan.
Sebagai masyarakat yang ingin maju, kita harus belajar membedakan kritik yang membangun dari tuduhan yang menyesatkan. Kita butuh nalar, bukan prasangka; butuh bukti, bukan sensasi.
Wim Tohari Daniealdi dosen UNIKOM Bandung
(mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini