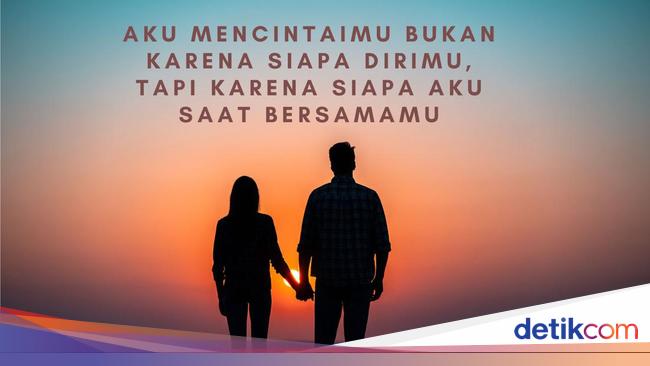Jakarta -
Suatu pagi, di antara riuh unggahan liburan dan kopi senja di Instastory, saya melihat foto papan boarding gate. Wajah itu saya kenal. Teman lama, dulu bercita-cita kuliah sambil kerja di Jerman. Saya tanya, "Jadi ke Jerman?" Jawabnya, "Nggak, Mas. Tapi ke Republik Ceko." Dalam rangka apa? Balasannya singkat: #KaburAjaDulu.
Tagar itu menempel kuat di kepala saya. Ia bukan sekadar lelucon atau selingan media sosial belaka. Di balik dua kata itu, tersimpan rasa yang lebih dalam-tentang harapan yang mengecil, ketidakpastian yang membesar, dan mungkin juga kekecewaan terhadap rumah sendiri.
Ada yang mulai merasa Indonesia bukan lagi tempat terbaik untuk tumbuh. Bertahan berarti stagnan, sedangkan pergi mulai dianggap sebagai solusi. Kabur bukan lagi sekadar perpindahan fisik, melainkan simbol perlawanan terhadap keadaan. Sebuah bentuk protes sunyi dari generasi muda, yang barangkali jauh lebih mencintai negeri ini daripada yang kita kira.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pesan Protes
Mobilitas anak muda ke luar negeri memang bukan hal baru. Sejak lama, generasi muda Indonesia pergi mencari ilmu, pekerjaan, atau sekadar mengadu nasib di negeri orang. Namun, dalam konteks tagar KaburAjaDulu, pergerakan ini memiliki nuansa berbeda. Ia lahir sebagai respons simbolik atas ketidakpuasan terhadap situasi sosial dan politik di dalam negeri.
Perasaan buntu menghadapi kondisi ekonomi, terbatasnya lapangan kerja, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak kepada rakyat menjadi pemicunya. Salah satunya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak luas. Misalnya, pemangkasan anggaran membuat perusahaan melakukan PHK besar-besaran-meskipun keputusan PHK itu dievaluasi ulang. Anak-anak muda melihat ini dengan getir: yang sudah bekerja saja diberhentikan, apalagi mereka yang baru mencari kerja-masa depan seolah semakin kabur.
Di sisi lain, efisiensi anggaran juga berdampak pada pemangkasan beasiswa pendidikan dalam negeri juga menjadi pukulan telak, meskipun segera dianulir oleh pemerintah. Bagi mereka yang bermimpi melanjutkan pendidikan, studi ke luar negeri menjadi pilihan rasional. Tidak hanya untuk menuntut ilmu, melainkan juga membuka peluang hidup yang lebih baik di sana.
Meski perpindahan ini belum mencapai level eksodus, pemerintah seharusnya memandang fenomena ini sebagai alarm peringatan. Ini bukan sekadar urusan individu, melainkan isyarat kegelisahan kolektif. Ada gerakan kekecewaan yang merayap pelan di kalangan anak muda, yang jika dibiarkan, bisa berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan politik ke depan.
Nasionalisme yang Bergeser
Sayangnya, sebagian elite politik justru menanggapi fenomena ini secara sinis. Ada yang mempertanyakan kecintaan anak muda terhadap tanah air, atau ada pernyataan yang terkesan meremehkan keresahan generasi muda, menunjukkan adanya jarak emosional antara penguasa dan rakyat.
Menganggap anak muda yang pergi ke luar negeri sebagai tidak nasionalis adalah simplifikasi yang keliru. Jika mau bicara soal nasionalisme, bisa saja anak muda yang pergi itu lebih nasionalis daripada para pejabat yang selama ini hanya menjadikan nasionalisme sebagai jargon politik.
Anak-anak muda yang bekerja di luar negeri justru mengalirkan sumber kehidupan bagi keluarganya di tanah air. Kiriman uang (remittance) mereka menopang kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan adik, bahkan memperbaiki rumah orang tua. Dengan begitu, mereka justru meringankan beban negara. Ini mengingatkan kita pada konsep nasionalisme fungsional, yakni bentuk keterikatan pada negara yang tidak lagi sekadar ditunjukkan dengan kehadiran fisik, melainkan dengan kontribusi nyata kepada keluarga dan masyarakat.
Teori ini sejalan dengan pemikiran John Urry (2000) tentang nasionalisme fleksibel. Dalam era globalisasi, seseorang bisa tetap nasionalis meskipun tinggal jauh dari tanah air. Kontribusi ekonomi, pengembangan jaringan, dan transfer pengetahuan justru menjadi wujud baru nasionalisme.
Lebih jauh, hal ini juga berkaitan dengan gagasan diaspora nasionalisme yang dikemukakan Benedict Anderson (1991) dalam bukunya Imagined Communities. Anderson menegaskan bahwa bangsa bukan hanya dibayangkan oleh mereka yang tinggal di dalam negeri, tetapi juga oleh warga negara yang berada di luar negeri. Diaspora tetap merasa bagian dari bangsa karena ikatan emosional, budaya, dan kontribusi ekonomi.
Dengan kata lain, nasionalisme hari ini memang bergeser bentuknya. Jika dulu nasionalisme diukur dari bertahan dan berjuang di tanah air, sekarang kontribusi bisa diberikan dari mana saja. Mereka yang menjadi bagian dari warga dunia (global citizen) tetap membawa "Indonesia" dalam dirinya. Nasionalisme tak lagi statis, melainkan dinamis dan lintas batas.
Kontrasnya, nasionalisme elite politik di dalam negeri justru patut dipertanyakan. Mereka mengklaim cinta tanah air, namun tak jarang menguras sumber daya negara demi kepentingan pribadi dan kelompok. Korupsi merajalela, sementara anak muda yang berusaha mandiri justru dicap tidak nasionalis. Bukankah ini sebuah ironi?
Apa yang dilakukan anak muda yang bekerja di luar negeri lebih nyata dampaknya bagi keluarga dan komunitas, dibanding nasionalisme para elite yang hanya menjadi slogan kosong. Seperti kata Ernest Gellner (1983) dalam Nations and Nationalism, nasionalisme seharusnya selaras dengan pembangunan sosial-ekonomi. Jika negara gagal menyediakan ruang untuk berkembang, nasionalisme pun bisa memudar atau bertransformasi.
Pemerintah Harus Peka
Fenomena KaburAjaDulu adalah isyarat keras yang seharusnya membuat pemerintah bercermin. Anak-anak muda tidak meminta banyak, hanya ruang untuk tumbuh dan berkembang di tanah sendiri. Jika ruang itu sempit, mereka akan mencarinya di tempat lain.
Tugas pemerintah bukan menghakimi atau mencap mereka tidak cinta Indonesia, melainkan menciptakan ekosistem yang membuat mereka ingin bertahan. Lapangan kerja, pendidikan terjangkau, dan jaminan sosial yang layak adalah bentuk nyata nasionalisme negara kepada rakyatnya.
Nasionalisme sejati bukan soal berdiri tegak menyanyikan lagu kebangsaan, melainkan memastikan setiap anak bangsa memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik di tanah airnya sendiri.
Dan kalau pun mereka memilih pergi, jangan buru-buru menghakimi. Bisa jadi, langkah kaki mereka keluar negeri adalah cara lain mencintai Indonesia-dengan cara yang belum mampu dipahami oleh sebagian elite negeri ini.
Nurul Fatta. Konsultan politik di Politika Research and Consulting (PRC).
(rdp/rdp)

Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu