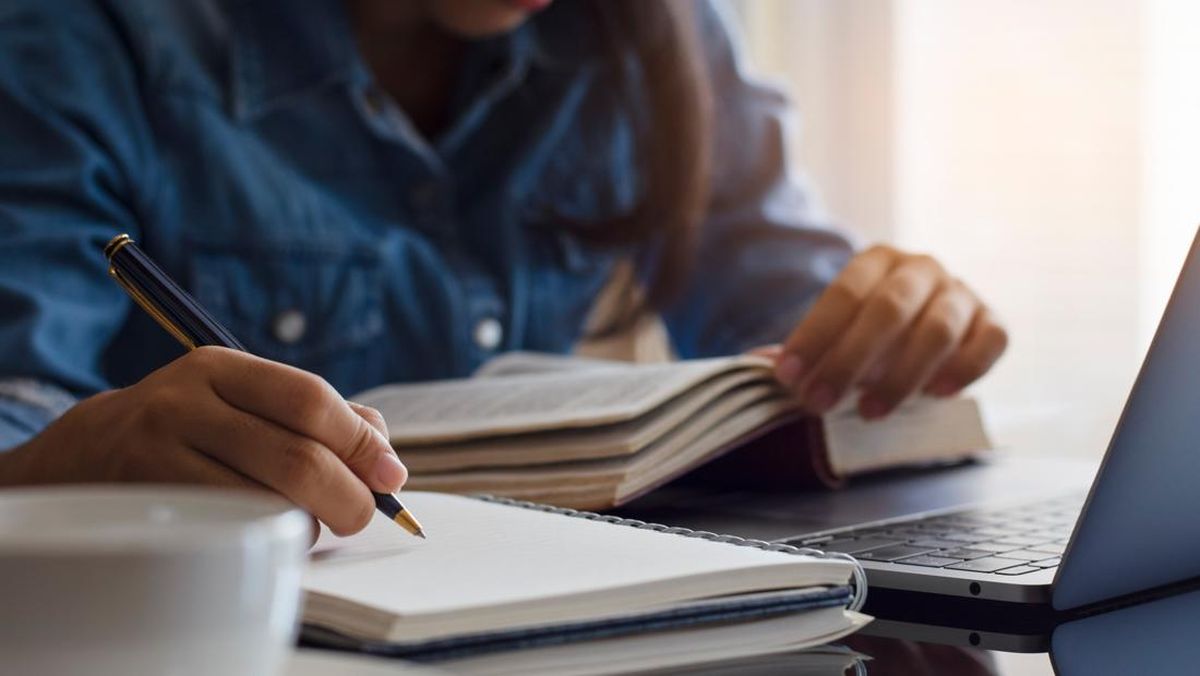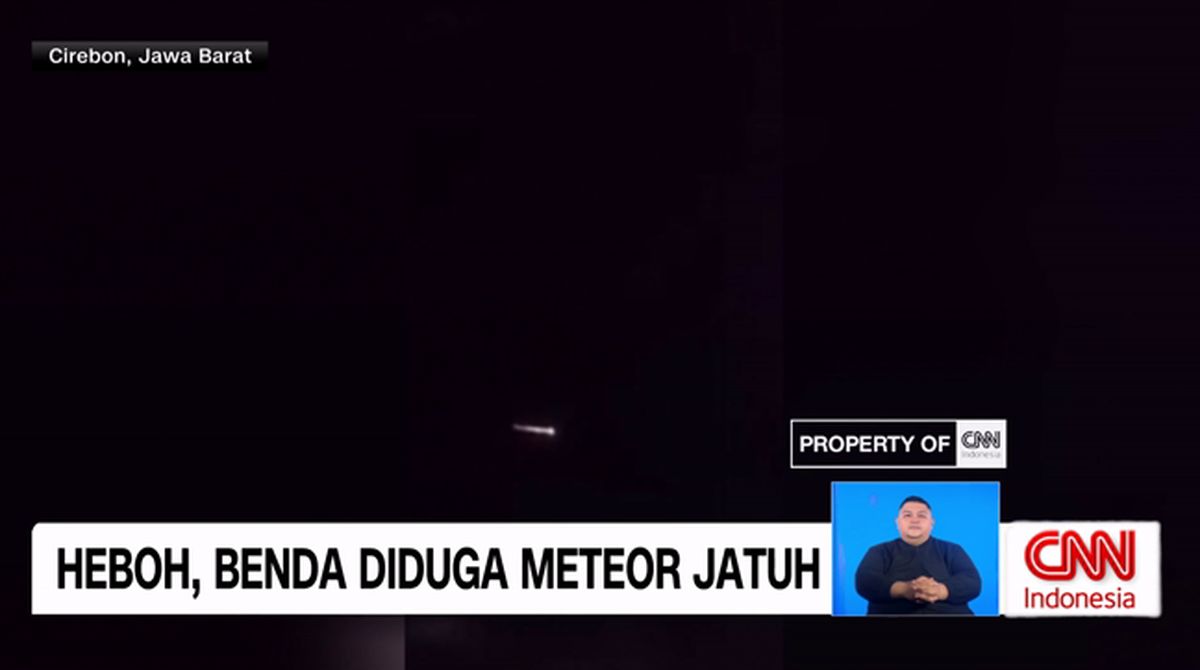Jakarta -
Pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan nikel di Raja Ampat menjadi tanda kemenangan penting bagi gerakan civil society dalam melawan dominasi oligarki atas sumber daya alam. Keputusan ini merupakan hasil dari konsistensi perjuangan masyarakat sipil, aktivis lingkungan dan komunitas adat yang bersuara lantang atas kerusakan ekologis serta ketimpangan kekuasaan.
Di tengah derasnya arus kepentingan ekonomi yang seringkali menyingkirkan hak-hak ekologis, kemenangan ini menunjukkan bahwa suara yang terorganisir dan konsisten, mampu meruntuhkan hegemoni kuasa atas tanah dan alam yang semestinya dijaga bersama.
Namun, yang perlu digarisbawahi adalah kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baik untuk melanjutkan kesadaran perlindungan lingkungan masyarakat dan merajutnya melalui tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh semua orang, bahkan dalam tindakan yang paling kecil, yakni dengan tidak membuang-buang makanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sisa Makanan dan Masalah Lingkungan
Mungkin saja apa yang kita buang hari ini dari meja makan tampak sepele saja. Sepotong ayam yang tak tersentuh, nasi yang tersisa, sayur yang dibiarkan dingin dan kemudian masuk ke tempat sampah dan air minum diambil secara berlebihan sehingga tak diminum. Namun, siapa sangka bahwa sisa-sisa kecil ini, jika dikumpulkan secara global, dapat menjadi bagian dari bencana ekologi yang sistemik.
Food waste atau pemborosan pangan kini bukan hanya soal etika dan kepedulian sosial, tapi juga menjadi isu lingkungan yang mendesak.
Dalam laporan Food Waste Index Report 2024 yang dirilis oleh United Nations Environment Programme (UNEP), dunia dihadapkan pada kenyataan yang memprihatinkan: sebanyak 1,05 miliar ton makanan terbuang pada tahun 2022 hanya dari tiga sektor konsumsi akhir, yakni rumah tangga, jasa makanan, dan ritel.
Angka ini mencerminkan bahwa hampir seperlima (19%) dari total makanan yang tersedia bagi konsumen dibuang sia-sia, bukan karena rusak di ladang, tetapi karena tidak dimakan setelah diproduksi dan disediakan. Jika dirinci, sektor rumah tangga menyumbang limbah terbanyak, yaitu 631 juta ton, yang setara dengan 79 kilogram per orang per tahun.
Artinya, tanpa kita sadari, sebagian besar pemborosan makanan justru terjadi di dalam dapur dan meja makan kita sendiri. Sektor jasa makanan seperti restoran dan katering menyumbang 290 juta ton, sedangkan sektor ritel seperti supermarket dan toko bahan makanan menyumbang 131 juta ton.
Lebih mencengangkan lagi, data ini belum termasuk 13% tambahan makanan yang hilang dalam proses produksi, distribusi, dan penyimpanan sebelum sampai ke konsumen, seperti yang dicatat oleh Food and Agriculture Organization of the United Nation.
Jika kedua angka ini digabungkan, dunia sebenarnya kehilangan lebih dari sepertiga dari seluruh pangan yang dihasilkan setiap tahunnya.
Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada air yang disedot dari tanah, energi yang digunakan untuk menanam dan mendistribusikan bahan makanan, bahan bakar fosil yang terbakar dalam transportasi, serta lahan yang dialihfungsikan untuk pertanian-semuanya berujung sia-sia saat makanan dibuang.
Lebih parahnya lagi, ketika makanan membusuk di tempat pembuangan akhir, ia menghasilkan metana-gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dari karbon dioksida. Dengan demikian, sisa makanan bukan sekadar 'sampah' dalam pengertian konvensional, melainkan representasi konkret dari kontribusi manusia terhadap percepatan perubahan iklim. Sayangnya, kesadaran akan dimensi ekologis dari limbah makanan ini masih sangat minim, termasuk di Indonesia.
Hal ini juga tampak dari laporan yang sama yang menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki sistem pengukuran nasional yang komprehensif terkait limbah makanan rumah tangga. Ketiadaan sistem pengukuran nasional berimbas pada ketiadaan data yang representatif ini mencerminkan rendahnya atensi struktural maupun sosial terhadap isu food waste.
Tak heran, Indonesia masuk menjadi negara peringkat tiga sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi.
Padahal, tanpa kesadaran dan pengukuran yang memadai, akan sangat sulit membangun kebijakan pengelolaan limbah pangan yang adil secara ekologis dan berkelanjutan secara sosial. Ini adalah persoalan yang menyentuh langsung jantung dari prinsip keadilan lingkungan.
Tanggung Jawab Lingkungan Setiap Orang
Dalam pendekatan hukum lingkungan, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan, termasuk dalam cara kita memproduksi dan mengonsumsi makanan. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip pencegahan kerusakan lingkungan menuntut kita untuk berpikir jauh ke depan terhadap dampak dari tindakan sehari-hari. Ini mencakup perilaku konsumsi.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus wajib menjaga keberlanjutannya. Artinya, aktivitas konsumsi pribadi yang menghasilkan limbah berlebihan, termasuk food waste, dapat dilihat sebagai bagian dari pelanggaran terhadap tanggung jawab ekologis warga negara.
Sayangnya, regulasi khusus mengenai limbah makanan di Indonesia masih tergolong lemah. Pengaturan yang ada lebih banyak berfokus pada limbah industri atau B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sementara limbah organik dari rumah tangga-termasuk sisa makanan-sering terabaikan. Namun, jika kita mengacu pada prinsip-prinsip global dalam environmental governance, maka food waste seharusnya sudah masuk dalam radar kebijakan lingkungan.
Aksi dari Dapur
Sebelum bicara soal regulasi dan kebijakan publik, ada hal mendasar yang perlu kita bangun bersama: kesadaran. Revolusi ekologis tidak selalu datang dari ruang sidang pengadilan atau peraturan menteri, tetapi bisa dimulai dari meja makan di rumah. Ya, dari atas piring.
Masyarakat bisa memulai dengan hal-hal kecil, seperti mengatur porsi makanan secukupnya, menyimpan sisa makanan dengan benar, membiasakan diri tidak membeli berlebihan, dan kreatif mengolah bahan pangan yang tersedia. Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah ini dielaborasikan dengan penggunaan teknologi melalui penggunaan aplikasi donasi makanan atau mendukung komunitas yang bergerak dalam redistribusi pangan.
Di sisi lain, lembaga pendidikan dan komunitas lingkungan dapat mengintegrasikan isu food waste ke dalam kurikulum, kampanye publik, dan praktik nyata. Bayangkan jika kampus, sekolah, dan tempat ibadah memiliki sistem pengelolaan limbah makanan yang terstruktur. Dampaknya tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial-mengurangi kelaparan dan meningkatkan solidaritas.
Kita juga perlu membangun budaya baru, budaya menghargai makanan sebagai hasil kerja keras petani, air, tanah, dan energi. Dalam perspektif spiritual dan etika lingkungan, membuang makanan sejatinya adalah bentuk ketidakadilan terhadap bumi dan sesama makhluk hidup.
Food waste bukan hanya tentang kebiasaan makan. Ia adalah cerminan cara seseorang memandang dunia dan menempatkan diri dalam tatanan ekologis yang saling terhubung. Ketika masyarakat mulai sadar bahwa setiap nasi yang tersisa punya jejak karbon, bahwa tiap makanan yang dibuang menyumbang pada krisis iklim, maka di situlah kesadaran hukum lingkungan tumbuh.
Sebagai elemen dasar dari sebuah negara, masyarakat tidak harus menunggu kebijakan nasional untuk bergerak. Keselamatan bumi bisa dimulai dari dapur. Dari keputusan sederhana: "Cukup ambil yang bisa dimakan." Karena pada akhirnya, menyelamatkan lingkungan bisa sesederhana membersihkan piring dan tidak membiarkan satu sendok pun terbuang sia-sia.
Eko Prasetyo. Dosen Fakultas Hukum dan Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia.
(imk/imk)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini