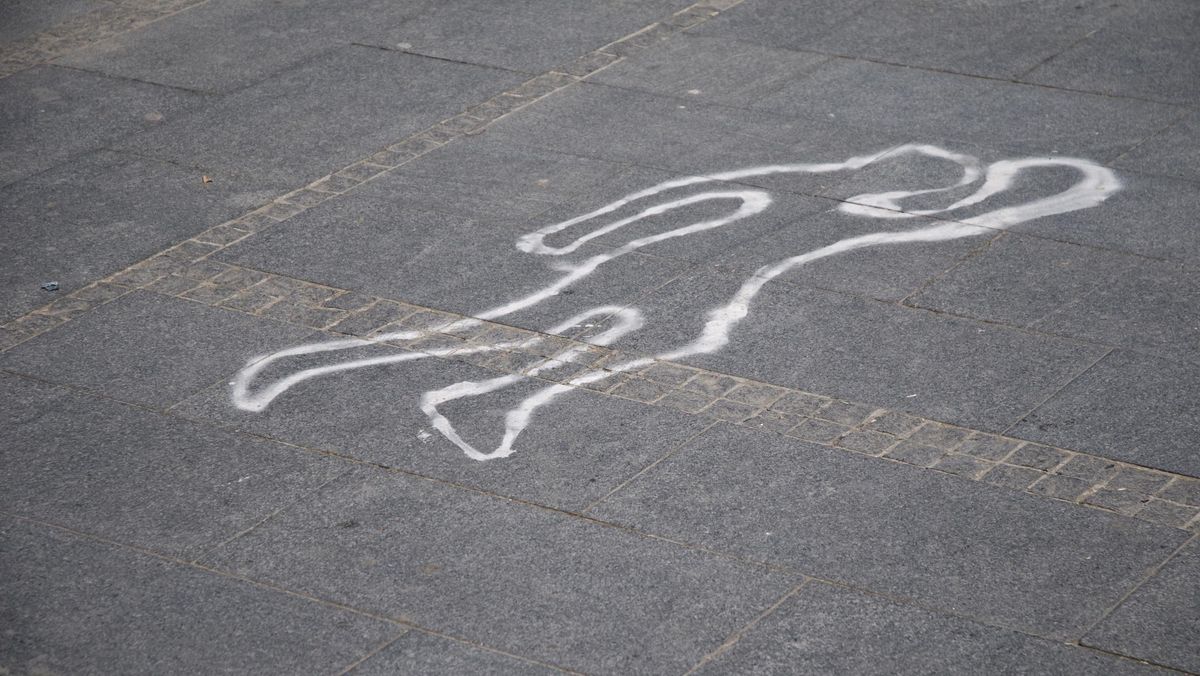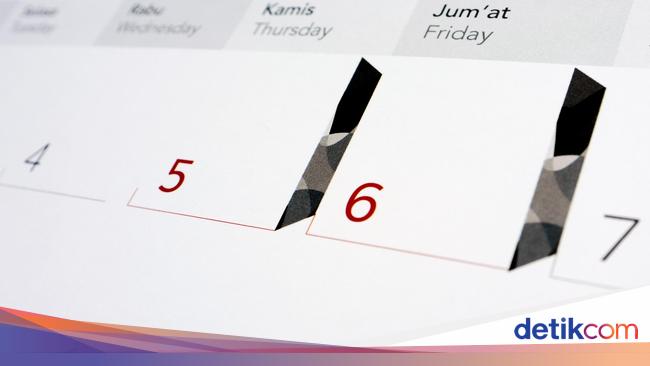Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo telah mempolarisasi bangsa ini ke ke jurang perdebatan yang tak kunjung usai. Ada dua kubu yang berseteru, tidak lagi di media sosial, malah sudah ke ranah hukum. Yakni, mereka yang "mengimani" Jokowi melakukan manipulasi ijazah dan mereka yang menolaknya.
Di tengah perseteruan dua kutub itu, terus berseliweran kabar, potongan video menggiring pandangan negatif kepada Presiden Indonesia ke 7 tersebut. Bahkan di tengah berbagai limpahan konten tersebut, lahir para "pakar dadakan" yang menjajakan asumsi sebagai bukti kebohongan Jokowi. Sayangnya, kegaduhan ini tak lahir dari kemampuan literasi.
Mudah Ditelusuri
Budaya literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga mencakup kemampuan memahami informasi, mengkritisinya, serta mencari kebenaran melalui sumber-sumber yang sahih. Banyak yang lebih senang menyebar keraguan dibanding mencari kepastian. Budaya literasi bangsa ini sangat rendah sehingga mudah terprovokasi oleh provokator.
Padahal informasi mengenai riwayat akademik Jokowi mudah dilacak dan dibuktikan kebenarannya. Ini bukan sesuatu yang sulit karena arsip dan jejak seputar akademiknya masih banyak tersebar dan tersimpan, khususnya di tempatnya kuliah. Misalnya, tahun masuk beliau ke Fakultas Kehutanan UGM pada 1980. Informasi ini bisa ditelusuri melalui koran-koran lama yang tersimpan rapi di Perpustakaan Daerah Yogyakarta, tepat di jantung Malioboro. Cukup cari arsip Kedaulatan Rakyat edisi Juni 1980. Di sana tercantum nama-nama peserta yang lulus Sipenmaru tahun itu. Jika benar Jokowi lulus, maka namanya pasti tertera sebagai mahasiswa baru di Fakultas Kehutanan UGM. Album lulusan Fakultas Kehutanan UGM pun masih tersimpan di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Demikian juga, skripsi, dokumentasi akademik, hingga arsip kegiatan mahasiswa bisa diakses publik.
Literasi bukan hanya soal bisa membaca, tapi tentang mampu menelaah dan memverifikasi. Dan pada titik inilah hoaks dan fitnah kemudian menjadi "keimanan" baru. Ada anekdot yang relevan dengan kondisi ini: dua orang berselisih soal bentuk bumi. Yang satu berkata, "Aku akan mencarinya di YouTube." Yang lain menjawab, "Aku akan mencarinya di perpustakaan." Kita tahu siapa yang akan menemukan jawaban, dan siapa yang hanya akan menemukan gema dari pikirannya sendiri.
Budaya literasi bangsa Indonesia masih rendah. Bahkan, UNESCO menempatkan Indonesia di peringkat 62 dari 70 negara dalam indeks literasi dunia. Sementara PISA 2018 menempatkan pelajar Indonesia pada peringkat 62 dari 77 negara dalam kemampuan membaca.
Dr. Jari Lavonen, pakar pendidikan dari University of Helsinki, mengatakan, "Literacy is the foundation of democracy. Without it, truth becomes vulnerable to loudness." Dan hari ini, kita menyaksikan bagaimana kebenaran digerus oleh kebisingan, dan bangsa dikoyak oleh ilusi yang viral.
Yang menyedihkan, semua ini terjadi di tengah krisis ekonomi. Ketika utang negara menembus Rp8.200 triliun, harga kebutuhan pokok melambung, dan lapangan kerja semakin sempit, energi bangsa justru dihabiskan untuk memperdebatkan sesuatu yang dapat diverifikasi dalam waktu sehari—jika saja kita mau membuka lembaran-lembaran sumber primer tentu tak habis energi bangsa ini.
Jalan ke Depan
Masalah utama dari kisruh ijazah palsu ini bukan terletak pada ada-tidaknya data, tapi pada budaya masyarakat yang malas membaca dan cepat percaya tanpa memverifikasi. Masyarakat yang tidak terbiasa menelusuri informasi ke sumber pertama, yang justru merasa cukup dengan potongan video dan narasi bias dari media sosial. Kebodohan hari ini bukan karena ketiadaan informasi, tapi karena keengganan mengakses dan memahaminya. Karena itu, solusi yang diperlukan bukan sekadar kampanye literasi dangkal, melainkan revolusi kognitif—perubahan cara berpikir masyarakat terhadap kebenaran dan informasi.
Pertama, negara harus berhenti menjadikan literasi sebagai jargon tahunan. Literasi informasi harus dijadikan kebijakan nasional lintas sektor. Artinya, setiap kementerian—dari pendidikan, komunikasi, sampai hukum—harus menjadikan kemampuan menelusuri data, memahami konteks, dan memverifikasi kebenaran sebagai bagian dari pelatihan publik dan sistem pendidikan formal. Belajar membaca tak cukup; kita perlu belajar mencurigai, menguji, dan membuktikan.
Kedua, pemerintah wajib menyediakan akses arsip yang terbuka dan terverifikasi. Tidak masuk akal jika data akademik pejabat publik seperti presiden harus dicari dengan susah payah. Pemerintah butuh portal nasional yang terintegrasi, tempat masyarakat bisa menelusuri dokumen resmi, berita masa lalu, dan rekam jejak akademik atau publik tokoh bangsa. Hoaks tumbuh subur di ruang gelap—dan tugas negara adalah menyalakan lampu.
Ketiga, hoaks tidak akan pernah punah selama penyebarnya merasa aman. Maka penegakan hukum harus cepat, transparan, dan memberikan efek jera. Tapi lebih dari itu, proses hukum harus dijadikan panggung edukasi: tunjukkan bagaimana informasi yang salah dibangun, bagaimana ia tersebar, dan bagaimana ia merusak nalar publik. Publik bukan hanya perlu tahu bahwa si penyebar salah, tapi mengerti mengapa mereka mudah tertipu.
Kita hidup di masa ketika kebohongan bisa diviralkan, dan kebenaran dikubur oleh algoritma. Jangan salahkan rakyat jika akhirnya menjadikan kesalahan sebagai kebenaran. Negara gagal menyediakan rakyat mencari tempat sumber informasi yang valid. Jika hari ini satu ijazah bisa memecah bangsa, jangan bayangkan apa yang bisa terjadi jika yang dipertaruhkan adalah konstitusi, pemilu, atau perang informasi antarnegara. Perbaikan harus dimulai hari ini, dimulai dari hal yang paling sederhana: membaca, memverifikasi, lalu berpikir.
Bangsa besar tidak dibangun oleh semangat curiga, tetapi oleh semangat mencari kebenaran. Jika bangsa terus abai terhadap budaya literasi, maka rakyat mudah diadu, dijauhkan dari substansi, dan dipermainkan oleh mereka yang lebih dulu menguasai narasi. Sudah saatnya kita bangkit bukan dengan teriak, tapi dengan membaca. Seperti kata filsuf Prancis, Voltaire, "Mereka yang dapat membuatmu percaya pada absurditas, dapat membuatmu melakukan kekejian."
Penulis, Ketua Komite Akademik Politeknik Negeri Medan
Simak juga Video Dampak Positif AI di Dunia Pendidikan: Skill Literasi Siswa Meningkat