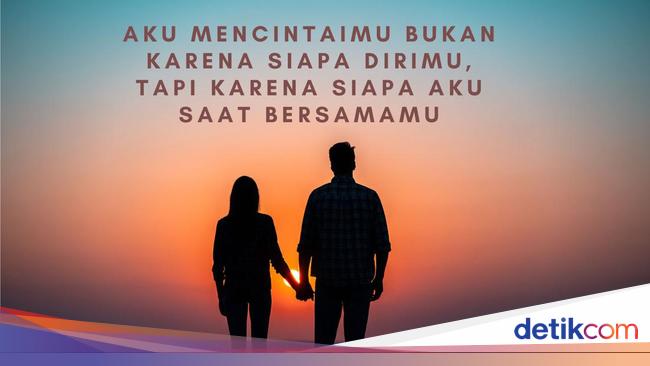Jakarta -
Industri fesyen adalah salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. United Nations Environmental Programme (2018) mengungkapkan bahwa industri fesyen menjadi salah satu penyumbang terbesar limbah tekstil global dengan produksi sekitar 92 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya, yang berdampak signifikan pada polusi global. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappennas) menyatakan bahwa timbunan limbah tekstil di Indonesia diperkirakan mencapai hingga 2,3 juta ton per tahun; jumlah ini akan terus meningkat sebesar 70% apabila tidak dilakukan intervensi.
Di tengah kesadaran akan dampak lingkungan dari fast fashion, praktik belanja pakaian bekas yang kerap disebut thrifting, hadir sebagai solusi yang dianggap lebih ramah lingkungan. Di Indonesia, thrifting tumbuh dan berkembang di Bandung sekitar 1990 - 2000 dengan pakaian yang identik akan skateboard dan streetwear. Pakaian-pakaian ini kerap dipasarkan di Pasar Baru, Cibadak, Kebon Kelapa, Tegallega hingga berakhir di Pasar Gedebage.
Awalnya, thrifting hadir sebagai praktik berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi limbah tekstil, memberikan pakaian-pakaian kehidupan kedua dan mendukung ekonomi sirkular. Jika merujuk pada teori Buyerarchy of Needs, thrifting dimaknai sebagai pembelian pakaian bekas dengan tujuan mengurangi limbah fesyen.
Menurut Sarah Lazarovic, sang pencetus, terdapat enam langkah dan petunjuk untuk mempraktikkan fesyen berkelanjutan. Yakni, use what you have, borrow, swap, thrifting, make, dan buy. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan thrifting justru kerap dimaknai sebagai ajang konsumtif. Fenomena seperti thrifting haul di media sosial menjadi contoh nyata bagaimana pakaian bekas bukan lagi sebuah persoalan keberlanjutan, melainkan gaya hidup dan ajang flexing.
Merugikan UMKM
Fenomena thrifting tentu akan berimplikasi pada sektor ekonomi. Menurut artikel yang ditulis oleh Andrew Books di The Guardian, ketika sebuah negara dengan kondisi ekonomi yang rapuh mulai menerima barang-barang impor, terutama pakaian bekas, hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pertumbuhan industri lokal. Hal ini tampak pada kenyataan di Indonesia bahwa praktik impor pakaian bekas dalam skala besar seringkali merugikan para pelaku UMKM lokal.
Produk dijual dengan harga jauh lebih murah hingga kerap mematikan daya saing produk lokal. Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan bahwa pakaian bekas impor mempengaruhi penurunan pendapatan insustri tekstil lokal hingga 30% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini semakin diperburuk dengan kurangnya kesadaran konsumen terkait asal-usul produk yang mereka beli.
Regulasi mengenai impor pakaian bekas sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, yang melarang impor barang bekas dengan tujuan melindungi industri dalam negeri dan kesehatan masyarakat. Namun, implementasi aturan ini di lapangan masih jauh dari optimal.
Perubahan Pola Pikir
Pergeseran makna thrifting dari solusi berkelanjutan menjadi tren konsumtif adalah cerminan dari pola pikir masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami konsep keberlanjutan. Konsumen, pemerintah, dan pelaku industri harus bekerja sama untuk mengembalikan thrifting ke jalur yang benar. Regulasi yang kuat, konsumen yang sadar, dan industri yang bertanggung jawab adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.
Di sisi konsumen, perubahan pola pikir sangat diperlukan. Mindful consumption atau konsumsi yang bijaksana harus menjadi prinsip dasar dalam praktik thrifting. Artinya, konsumen tidak hanya membeli karena tren atau harga murah, tetapi benar-benar memahami kebutuhan mereka dan mempertimbangkan dampak dari setiap pembelian. Kesadaran ini bisa dimulai dengan mengurangi perilaku impulsif saat berbelanja dan lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas.
Praktik thrifting hanya akan berdampak positif jika dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Pemerintah, pelaku bisnis, dan konsumen harus berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem fesyen yang benar-benar berkelanjutan. Tentu kita tak ingin gerakan yang seharusnya menjadi solusi malah berubah menjadi bagian dari masalah baru, bukan?
Mengubah Pola Konsumsi
Fesyen berkelanjutan lebih dari sekadar mengurangi limbah atau membeli pakaian bekas. Realisasi terhadap fesyen berkelanjutan mencakup perubahan sistemik di seluruh industri, mulai dari cara pakaian diproduksi, dipasarkan, hingga dipakai. Di sini, thrifting memegang peranan penting dalam mengubah pola konsumsi. Misalnya, dengan membeli pakaian hasil thrifting, konsumen tidak hanya menghemat uang, tetapi juga mendukung ekonomi sirkular yang mengedepankan penggunaan kembali barang.
Hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar fesyen berkelanjutan yang mengutamakan pengurangan dampak lingkungan tanpa mengorbankan kualitas atau gaya. Namun, agar konsep fesyen berkelanjutan bisa terealisasi secara maksimal, perlu adanya perubahan dalam cara berpikir konsumen. Tidak hanya mengandalkan faktor harga atau merek, tetapi lebih kepada kualitas dan daya tahan barang yang akan dipilih. Oleh karena itu, pendidikan mengenai konsumsi bijak dan keberlanjutan sangat penting untuk disosialisasikan, baik melalui media sosial, komunitas, atau kebijakan pemerintah.
Najlaa Aura pemerhati fesyen
(mmu/mmu)