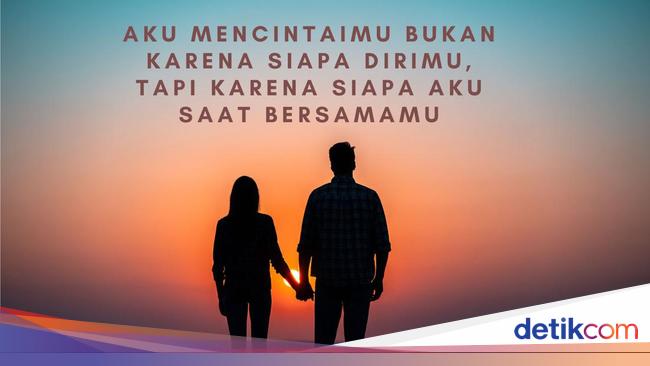Jakarta -
Ketika kecil, saya pernah mendengar kisah tentang bagaimana secara heroik Jepang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat kekalahan Perang Dunia II dari Sekutu. Saat dua bom atom meluluhlantakkan Hirosima dan Nagasaki, Jepang tidak memiliki pilihan selain menyerah kepada sekutu. Kaisar Jepang, Hirohito, lantas mengumpulkan seluruh guru yang tersisa saat itu. Yang dikumpulkan oleh kaisar saat itu bukanlah tentara, bukan polisi, tetapi guru. Kemudian protes pun mengalir kepada kaisar dari para serdadu Jepang yang tersisa dan mempertanyakan mengapa bukan tentara yang dikumpulkan. Padahal saat itu Jepang sedang berperang fisik dengan sekutu.
Kaisar bersikukuh, jika yang dikumpulkan tentara, mungkin Jepang akan tetap terus dapat berperang, hingga titik darah penghabisan. Risikonya, jika kalah, mungkin tidak akan ada Jepang yang kita kenal saat ini. Kaisar berpandangan bahwa setelah Perang Dunia II ini selesai cara terbaik untuk "membalas" kekalahan tersebut adalah melalui pendidikan. Jepang harus melawan dan membalikkan keadaan melalui pendidikan. Jepang boleh dikatakan "menyerah" saat itu secara militer tetapi denyut perlawanan tetap harus mengalir melalui pendidikan. Di tengah kondisi negara yang dapat dikatakan dalam kondisi kalah perang, pendidikan harus menjadi pemandu.
Kebangkitan Jepang
Kurang lebih 40 tahun setelah deklarasi kekalahan Jepang terhadap tentara Sekutu, yaitu sekitar era 80-an, kita menjadi saksi mata bahwa Jepang telah menjadi bangsa utama di dalam penguasaan teknologi. Perjuangan memajukan pendidikan telah menunjukkan hasil dalam bentuk ekspor teknologi ke seluruh dunia, termasuk ke Amerika sebagai pemimpin sekutu pada Perang Dunia II di front Pasifik.
Teknologi Jepang yang diekspor meliputi kendaraan bermotor hingga ke peralatan elektronik rumah tangga. Bahkan, apabila agak sedikit melebih-lebihkan, barangkali tidak ada satu rumah pun di Republik Indonesia ini yang tidak ada merk dari teknologi Jepang saat ini. Sejak tahun 80-an, Jepang telah menjadi pemain utama teknologi hingga saat ini. Visi kaisar Jepang Hirohito adalah kunci untuk menyelamatkan negaranya dari kemusnahan dan membalikkan keadaan saat itu.
Pemotongan Anggaran Pendidikan
Mengamati kondisi negara kita saat ini, memori saya kembali ke cerita masa kecil saya tersebut. Padahal cerita tersebut sudah saya dengar 20-30 tahun lalu. Pada 2025 ini, cerita tersebut masih relevan ketika terjadi kondisi darurat di mana negara kita harus berhemat.
Refocusing atau memfokuskan ulang anggaran belanja negara untuk memperbaiki efektivitas anggaran dan efisiensi merupakan hal yang baik dan perlu didukung oleh masyarakat. Istilah refocusing menegaskan bahwa selama ini ada yang tidak fokus atau tidak menimbulkan dampak yang diharapkan dari anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintah. Refocusing ini adalah pemotongan anggaran melalui mekanisme blokir anggaran pemerintah. Anggaran yang diblokir diarahkan untuk alokasi lain di antaranya untuk mendukung beberapa program yang menjadi prioritas bagi pemerintah.
Refocusing ini dipicu oleh berbagai hal, di antaranya target pendapatan yang meleset atau utang negara yang jatuh tempo. Pemotongan anggaran ini menyasar ke hampir semua sektor termasuk sektor pendidikan seperti yang dialami oleh pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. Pemotongan anggaran pendidikan kemudian menimbulkan pro dan kontra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akibat pemotongan ini menimbulkan kekhawatiran dari pelbagai pihak termasuk dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hingga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sendiri. Kekhawatiran tersebut di antaranya adalah menyangkut potensi kenaikan biaya kuliah (Uang Kuliah Tunggal/UKT). Kekhawatiran ini tentunya beralasan. Ekonomi masyarakat yang saat ini tengah mengalami gonjang-ganjing akibat pola belanja pemerintah yang berubah.
Belum lagi dampak pemangkasan anggaran infrastruktur akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja massal yang tentunya berdampak kepada kemampuan membayar orangtua mahasiswa. Hal ini akan semakin menambah beban masyarakat.
Berbicara terkait UKT perguruan tinggi, kita tidak dapat melepaskan dari pembahasan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau yang dikenal BOPTN. Setiap perguruan tinggi Negeri memiliki biaya operasional per mahasiswa per semester yang dikenal dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT). BKT ditutup dari dua sumber, dari subsidi pemerintah melalui BOPTN dan kontribusi mahasiswa yang disebut UKT. Ada pula BKT yang dibayarkan melalui beasiswa misalnya seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Per 2024, setahun sebelum isu pemangkasan anggaran, BOPTN yang dianggarkan hanya memberikan kontribusi kurang lebih 3 juta per tahun per mahasiswa. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, ketika menanggapi kenaikan UKT 2024 lalu. Pernyataan ini dikutip di beberapa media. Masih menurut Pahala Nainggolan, idealnya BKT perguruan tinggi adalah sebesar 10 juta per semester. Selisih antara BOPTN dan biaya operasional tersebut harus ditanggung oleh mahasiswa dan perguruan tinggi.
Sementara itu, di sisi lain, anggaran pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian lembaga (Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga/PTKL) bantuan operasionalnya per siswa mencapai rata-rata 67 juta per tahun sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek Kiki Yuliati pada 2024 silam. Data ini mencuat di berbagai media pada 2024 lalu ketika banyak perguruan tinggi menaikkan UKT secara serentak.
Di detik-detik akhir, yaitu pada 14 Februari 2025, akhirnya Kementerian Keuangan mengeluarkan pernyataan bahwa beasiswa dan BOPTN tidak akan terkena pemotongan sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Padahal, masih segar di dalam benak kita, isu keberpihakan kepada pendidikan sempat menjadi sorotan masyarakat beberapa minggu lalu. Sebelum isu pemangkasan anggaran pendidikan ini mengemuka. Isu terkait tunjangan kinerja (tukin) dosen yang selama periode 2020-2024 tidak pernah terbayarkan terangkat ke publik. Padahal dosen-dosen perguruan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil.
Dosen-dosen menjadi garda terdepan di dalam menjalankan darma pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tuntutan tridarma tersebut tidak hanya tingkat nasional tetapi harus mampu bersaing pada tingkat global. Dosen-dosen perguruan tinggi dituntut melakukan publikasi di jurnal internasional di tengah beban pengajaran yang tinggi. Beban pengajaran yang tinggi saat ini karena Indonesia tengah mengalami bonus demografi. Ironi lainnya, dosen PTKL telah mendapatkan tukin dan jumlah mahasiswa tidak sebanyak yang ada di perguruan tinggi di bawah naungan Kemendiktisaintek.
Pengingat
Cerita Kaisar Hirohito sebelumnya kemudian menjadi semakin relate kembali ketika pada awalnya, beberapa sektor tidak mengalami pemotongan seperti, misalnya, anggaran pertahanan dan keamanan saat pembahasan awal refocusing berlangsung. Masyarakat dan pengamat kemudian mempertanyakan dasar mempertahankan anggaran pertahanan dan keamanan di tengah pemotongan besar-besar anggaran di sektor lain, termasuk pendidikan. Walaupun pada akhirnya, sektor pertahanan dan keamanan ikut terkena refocusing.
Sepenggal cerita tentang kebangkitan negara Jepang pasca Perang Dunia II di atas adalah untuk pengingat kita bersama. Bahwa untuk melakukan lompatan dari masalah-masalah kita saat ini harus didasari kepada komitmen memajukan pendidikan. Pendidikan adalah bentuk investasi jangka panjang yang hasilnya belum tentu dirasakan oleh kita saat ini. Tetapi investasi ini terbukti telah mengubah nasib banyak negara, termasuk dari cerita Jepang di atas.
Tentu kita ingin melihat negara kita bangkit dan menjadi negara maju pada 2045. Cita-cita menjadi Generasi Emas 2045 tidak dapat dicapai tanpa sumber daya manusia yang mumpuni. Tulisan ini bukan untuk mendramatisasi kondisi bangsa Indonesia yang seolah disamakan dengan bangsa yang "kalah" atau menyalahkan pihak tertentu. Tulisan ini adalah sekadar refleksi dari memori masa kecil. Doktrin ini yang selalu terngiang di dalam alam bawah sadar saya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib suatu bangsa. Tentunya kondisi bangsa kita saat ini jauh lebih baik dalam banyak hal. Tetapi kita tidak boleh melupakan sektor pendidikan.
Isu refocusing atau pemangkasan anggaran pemerintah hanya satu dari sekian tantangan atau turbulensi jangka pendek yang harus dilalui bangsa ini. Untuk menjadi bangsa yang kuat, dinamika seperti ini adalah hal biasa untuk menguji ketangguhan kita sebagai bangsa dalam melalui berbagai rintangan secara kolektif.
M. Bobby Rahman pengamat kebijakan anggaran, dosen Institut Teknologi Sumatera (Itera)
(mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu