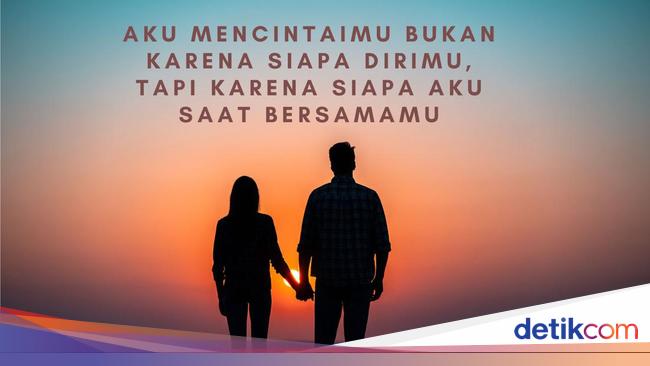Jakarta -
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran secara resmi telah dibahas dalam perencanaan anggaran 2025 dengan menetapkan besaran anggaran pada tahap pertama sebesar Rp 71 triliun, yang akan difokuskan pada pelajar SD-SMP-SMA kategori kuintil 1 dan 2 di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia.
Berdasarkan dokumen Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, rencana implementasi program MBG ini sebagai berikut: (1) Target penerima MBG mencakup 82 juta orang, terdiri dari 44 juta anak usia sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita, dan 4 juta ibu hamil, (2) Sebanyak 44 juta anak usia sekolah yang bersekolah di 439.000 sekolah, yang perlu dilayani oleh 48.000 dapur/unit pelayanan, dan (3) MBG membutuhkan karbohidrat setara 1,9 juta ton beras, protein setara 5,6 juta ton daging serta telur ayam, 3,3 juta ton buah, dan 1,8 juta ton sayuran per tahun.
Ada empat hal penting yang mesti disiapkan pemerintah dalam konteks capaian target itu. Pertama, mengoptimalkan peran aktif pemerintah lokal dalam perspektif optimalisasi fungsi desentralisasi untuk ketersediaan pangan sebagai aspek utama program MBG. Kedua, optimalisasi peran sekolah, kelembagaan, dan kemitraan. Ketiga, perlunya kolaborasi trans-disiplin di tingkat lokal-nasional. Keempat, keterlibatan perguruan tinggi lokal melalui implementasi iptek.
Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
Dalam konteks optimalisasi fungsi desentralisasi, pemerintah daerah semestinya wajib mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal dan sumber daya manusia untuk membangun ketersediaan pangan lokal yang memadai dan berkualitas secara sistematis, paling minimal dapat memenuhi kebutuhan lokal untuk mendukung program MBG. Inisiasi ini bukan saja secara makro bisa menciptakan ketahanan pangan melainkan berefek ganda pada sistem sirkulasi ekonomi yang positif di tingkat lokal.
Dalam konteks itu, beberapa yang harus dilakukan pemerintah lokal; (1) Meningkatkan produktivitas pangan melalui pelatihan dan penyuluhan, akses mudah pada penyediaan peralatan dan sumberdaya, serta diversifikasi pertanian, (2) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam lokal yang ada di daerah, (3) Peningkatan infrastruktur dan sistem distribusi pangan; irigasi, jalan, dan lain sebagainya, (4) Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan, (5) Pemantauan dan pengawasan pangan, (6) Pemanfaatan teknologi dan inovasi, (7) Membangun sistem kemitraan antardaerah dan swasta, dan (8) Edukasi dan kampanye ketahanan pangan.
Kedelapan poin tersebut pada dasarnya telah dilakukan pemerintah namun tidak serius dan terkesan asal-asalan sehingga pengembangan pertanian lokal justru berjalan ditempat dan sebaliknya tidak produktif. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2022, terdapat 74 kabupaten/kota dengan rincian 70 kabupaten (16,83%) dari 416 kabupaten, 4 kota (4%) dari 98 kota masuk dalam kategori IKP rendah. Sementara IKP Provinsi menunjukkan terdapat dua provinsi (5,88%) yaitu Papua dan Papua Barat masuk dalam IKP rendah, masing-masing sebesar 37,80 dan 45,92, di mana Wilayah Indonesia bagian timur secara umum memiliki nilai IKP lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia bagian barat.
Penyebab rendahnya nilai IKP antara lain produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang), prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan tingginya persentase penduduk hidup miskin. Data ini menunjukkan bahwa sesungguhnya daerah belum cukup mampu menyediakan sumber pangan untuk mendukung program MBG.
Terkait optimalisasi peran sekolah, kelembagaan dan kemitraan, barangkali aspek penting harus dipikirkan dipikirkan Prabowo-Gibran dalam mendesain kebijakan program MBG di institusi pendidikan lokal yang ada di daerah (SD, SMP, SMA, pesantren); (1) Program MBG ini tidak terintegrasi sebagai bagian dari kurikulum yang ada di sekolah, (2) Jaminan ketersediaan dan kebutuhan nutrisi makanan/pangan mesti memenuhi kualitas gizi dengan standar kesehatan, (3) Variasi makanan ketersediaan pangan yang berbeda-beda, dan (4) Pengadaan dan distribusi pangan dengan karakteristik budaya dan aksesibilitas yang berbeda.
Merujuk pada empat poin itu maka tidak mungkin sekolah dan/atau institusi pendidikan lokal di daerah mampu mendesain program MBG secara mandiri sehingga dibutuhkan satu sistem kelembagaan dan kemitraan yang kuat yang harus dibangun, misalnya dengan bekerja sama memaksimalkan peran lembaga-lembaga lokal seperti BUMDes, UMKM, atau LSM yang fokus kepada isu terkait.
Prabowo-Gibran barangkali bisa belajar dari India sebagai case study yang positif. Di India, Program makan bergizi di sekolah dikenal sebagai program Mid-Day Meal (MDM), dilatarbelakangi oleh kekurangan gizi pada jenjang anak sekolah. Pemerintah India kemudian meluncurkan program makan siang gratis pada 1995 untuk meningkatkan kehadiran sekolah dan bertujuan mengurangi kelaparan, di mana program ini mencakup 125 juta anak di sekolah negeri serta sekolah bantuan pemerintah.
Program ini memakan biaya sekitar US$ 2,8 miliar di mana studi WFP PBB menunjukkan bahwa dari setiap US$ 1 yang digunakan untuk program makan siang di sekolah Makan Siang dapat mendongkrak dampak ekonomi sebesar US$ 9. Anggaran US$ 1 ini digunakan untuk pengadaan bahan baku makanan, jalur logistik dan penyimpanan, serta penguatan komoditas makanan. Terkait pendanaan, program ini diatur oleh Undang-Undang Ketahanan Pangan dengan skema pembiayaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian dengan rasio 60:40.
Program di India itu melibatkan kerja sama antar kementerian dan lembaga swadaya masyarakat diantaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertanian. LSM berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan meningkatkan efektivitas distribusi makanan. Sebanyak 30 persen pengadaan makanan harus disuplai dari kelompok tani lokal guna mendukung ekonomi lokal dan memastikan keberagaman gizi. Setiap LSM memiliki tugas dan fungsinya masing-masing guna mengimplementasikan program yang lebih efektif dan menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh negeri.
Dalam konteks implementasi penyaluran, India menyalurkan Program Mid-Day Meal Scheme melalui beberapa langkah terstruktur, yaitu: (1) Makanan disiapkan di dapur umum atau dapur sekolah yang ditunjuk berdasarkan pemfokusannya pada penggunaan bahan lokal, (2) Setelah makanan dimasak, makanan tersebut diangkut ke sekolah menggunakan kendaraan yang sesuai guna memastikan makanan tetap dalam kondisi baik hingga sampai ke siswa, dan (3) Di setiap sekolah, guru dan staf bertanggung jawab untuk menyajikan makanan kepada siswa agar memastikan semua anak menerima porsi yang cukup.
Selanjutnya dalam konteks kolaborasi trans-disiplin di tingkat lokal-nasional, dibutuhkan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai multi-aspek yang mempengaruhi program MBG dalam konteks mikro dan makro. Di India misalnya, Program Mid-Day Meal Scheme melibatkan ahli gizi dalam perencanaan menu untuk memastikan bahwa makanan tidak hanya aman tetapi juga bergizi dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi anak-anak. Untuk memudahkan kerja-kerja kolaborasi trans-disiplin perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dari tingkat nasional-lokal, yang masing-masing bertanggung jawab pada satuan wilayah kerja masing-masing.
Dalam perspektif optimalisasi fungsi desentralisasi, wilayah kabupaten berdasarkan potensi dan karakteristiknya mestinya diberi kewenangan khusus dan seluas-luasnya menyusun strategi penguatan program MBG melalui Pokja Kabupaten di bawah tanggung jawab bupati di mana pokja ini harus berjenjang sampai pada tingkat kecamatan/desa. Dalam konteks itu, maka pemerintah juga mesti menyediakan dana khusus dan/atau anggaran untuk operasional kerja-kerja pokja. Tentunya mereka yang terlibat dalam kerja-kerja pokja ini adalah mereka yang mengarusutamakan jiwa patriotik, ikhlas, dan sukarela.
Sementara optimalisasi peran perguruan tinggi lokal dalam mendukung program MBG dilakukan melalui implementasi iptek, dengan pendekatan Tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ini bukan saja terkait upaya penyediaan pangan dalam hal kuantitas dan kualitas melainkan pentingnya penerapan inovasi teknologi untuk memajukan pembangunan dan pengembangan pertanian lokal yang berkelanjutan.
Peran penting dan strategis perguruan tinggi dalam pengembangan pertanian lokal melalui lintas ilmu pengetahuan di antaranya terkait dengan: (1) Riset komoditas unggulan lokal untuk pengembangan, (2) Manajemen pertanian terpadu berbasis komoditas lokal; pengenalan pertanian terpadu dalam proses perencanaan, pengelolaan dan penggunaan lahan, (3) Manajemen pengelolaan potensi limbah lokal; pengelolaan limbah menjadi pupuk organik untuk pertanian berkelanjutan, (4) Pengendalian hama terpadu; pengendalian hama dan penyakit pada tanaman dalam menjaga produktivitas pertanian, dan (5) Manajemen panen dan pasca panen; manajemen pengelolaan panen dan pascapanen, mulai dari pemetikan, pembersihan, sortir, dan grading.
Dalam konteks program MBG, perguruan tinggi lokal mesti dituntut untuk berkiprah mendukung pembangunan pertanian khususnya kemandirian pangan dan energi berbasis pangan, dengan segala tantangan dan permasalahan yang dihadapinya. Paling minimal ada 3 hal yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan politik pangan yang berbasis pada kedaulatan dan kemandirian, yaitu; (1) Mengembangkan aspek kesiapan manusia melalui pendidikan formal, (2) Mengembangkan iptek dan konsep alternatif kebijakan pembangunan melalui aktivitas penelitian, (3) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui diseminasi inovasi, pendidikan non formal dan bentuk pengabdian pada masyarakat.
Perguruan tinggi wajib terlibat karena urgensi program MBG bukan saja bagian dari pencegahan stunting melainkan membangun kembali kedaulatan pangan paling menimal adalah mewujudkan swasembada pangan yang digalakkan oleh Prabowo-Gibran pada 2025.
Rekomendasi
Tantangan program MBG bukan saja terkait dengan jaminan ketersediaan pangan melainkan distribusi logistik untuk membagikan makanan kepada 82 juta anak di berbagai daerah Indonesia dengan aksesibilitas dan kondisi topografi yang berbeda. Dalam konteks itu, hal terpenting mesti dilakukan adalah membangun kekuatan pangan berbasis lokal melalui optimalisasi fungsi desentralisasi. Pemerintah provinsi dan khususnya kabupaten harus diberi peran aktif untuk menciptakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, sehingga ketersediaan pangan bukan saja mampu menjawab permintaan dan kemudahan distribusi untuk kebutuhan program MBG melainkan secara simultan mendukung upaya swasembada pangan nasional.
Sejauh ini peran daerah tidak kelihatan, bahkan seolah mereka tidak peduli atas program ini. Dengan memberikan keleluasaan, tanggung jawab, dan peran aktif pada mereka, tidak saja memudahkan capaian tujuan melainkan akan memberi manfaat ekonomi berganda pada masyarakat lokal termasuk menghidupkan UMKM lokal, BUMDes, dan organisasi terkait yang bisa dilibatkan.
Beberapa rekomendasi penting yang diusulkan; pertama, perlu kiranya diberikan kewenangan penuh pada pemerintah lokal melalui pendekatan optimalisasi fungsi desentralisasi. Pemerintah provinsi/kabupaten perlu mendesain program MBG secara bersama untuk membangun ketersediaan dan ketahanan pangan lokal secara optimal dan berkelanjutan, yang secara simultan mendukung penciptaan ketahanan pangan nasional. India telah memberikan contoh nyata bahwa program makan bergizi yang dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintah lokal berdampak pada peningkatan produksi pangan lokal, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan petani.
Kedua, kolaborasi dan kerja sama kemitraan antarlembaga lintas sektoral lokal-nasional perlu dilakukan secara serius. Di India, peran-peran LSM seperti Akshaya Patra Foundation, Nandi Organization, dan Annamrita memberi kontribusi positif dalam mengimplementasikan program makan gratis yang lebih efektif dan efisien yang menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh negeri.
Ketiga, kolaborasi diskusi trans-disiplin mesti dilakukan untuk memudahkan implementasi program MBG. Para ilmuwan, profesor/guru besar/akademisi (perguruan tinggi), swasta, pelaku usaha dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman harus dilibatkan dalam pokja-pokja nasional, regional, dan lokal untuk memberi rekomendasi terkait implementasi program MBG yang optimal dan berkelanjutan.
Keempat, dalam memberdayakan potensi lokal, pemerintah mesti membuat payung hukum yang jelas dan terukur sebagai alat operasional lembaga-lembaga lokal termasuk pemerintah daerah yang terlibat dan berkontribusi pada program ini. Dengan demikian masing-masing institusi bergerak berdasar pada hukum dan berpegang teguh pada prinsip good governance.
La Ode Muhammad Rabiali mahasiswa Program Doktor di IPB University, pendiri Yayasan KARST Indonesia; aktif dalam bidang kehutanan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat desa
(mmu/mmu)