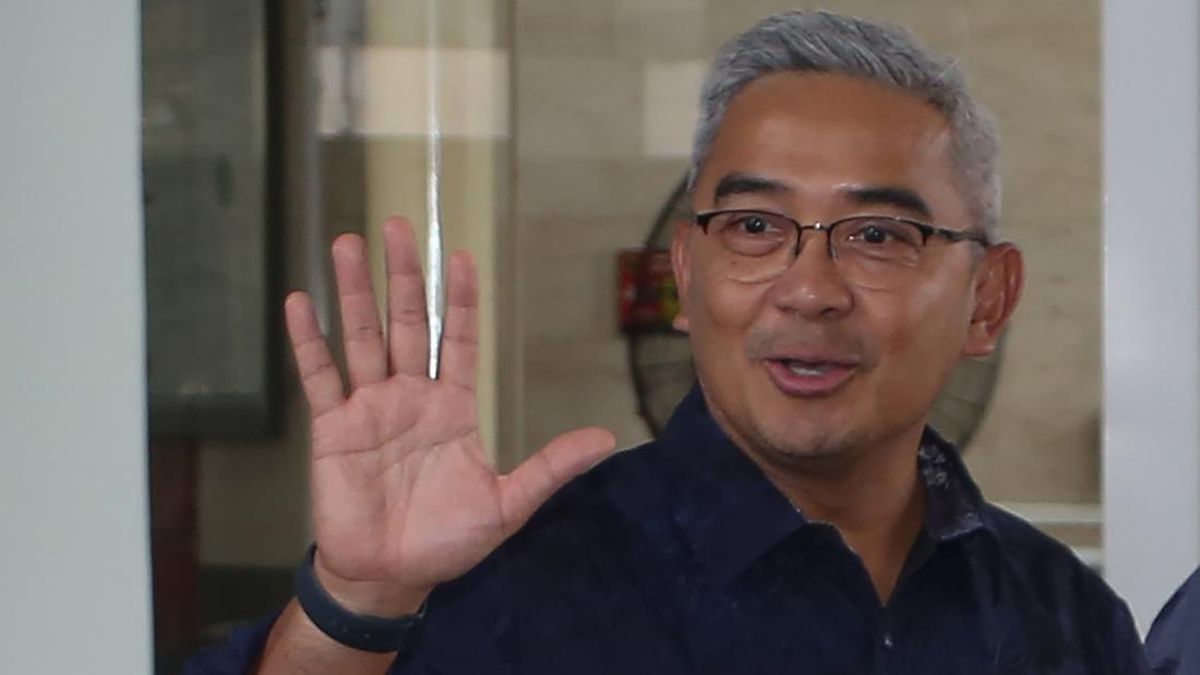Antonius (51) baru-baru ini mengaku kepada istrinya, Atik (50), bahwa gigi gerahamnya patah lagi. Atik menyuruh Antonius membuka mulut. “Masih ada akarnya itu, takutnya infeksi atau kenapa-kenapa. Ayo periksa!” ajak perempuan itu.
Atik memang lebih tinggi kesadarannya untuk periksa gigi. “Meskipun saya juga baru tahu periksa gigi seharusnya enam bulan sekali itu pas sudah akhir 30-an atau 40-an awal lah. Pada waktu itu, saya baru punya BPJS Kesehatan, akhirnya periksa gigi untuk pertama kalinya dan dikasih tahu dokter soal periksa gigi rutin. Kalau nggak ada BPJS, kan, dokter gigi mahal,” jelasnya.
Pasangan itu tinggal di sebuah desa di kawasan pantura, Jawa Tengah dan sama-sama bekerja, punya dua anak dan si bungsu masih kuliah. Penghasilan keduanya jika ditotal Rp 3,5-6 juta per bulan. Tentu saja sekali kunjungan ke dokter gigi untuk konsultasi, merogoh kocek sekitar Rp 100 ribu, dirasa mahal, belum nanti kalau giginya bermasalah dan butuh tindakan beberapa kali.
Makanya, sejak punya asuransi BPJS Kesehatan, Atik memanfaatkannya untuk rutin cek gigi dan mata. Meskipun, ada halangan lain untuknya seperti harus meluangkan waktu di hari kerja, ditambah banyaknya antrean di dokter gigi. Kata Atik, puskesmas atau klinik BPJS umumnya memiliki dua atau lebih dokter umum, tetapi hanya satu dokter gigi, sehingga pasien gigi yang dilayani terbatas, biasanya cuma sepuluh per hari. Tak heran mengingat jumlah dokter gigi sekitar 47 ribu, melayani 280 juta penduduk.
Belum lagi, faktor lupa karena kesibukan, alhasil tidak selalu bisa disiplin enam bulan sekali. “Lupa lagi, lupa lagi. Karena banyak urusan lain yang dilakukan dan dipikirkan toh, tapi paling lama setahun sekali lah. Nggak lebih dari setahun kalau saya. Kalau (suamiku) ini, nih, suka males. Nggak pernah dia. Terakhir kapan ya, Pak, yang waktu itu sakit dan disarankan operasi?” Atik bertanya kepada suaminya.
“Wah, udah lama sekali. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu,” jawab Antonius. Atik menggeleng-gelengkan kepala.
“Ya, habisnya, sembuh sendiri. Maksudnya nggak nyeri lagi. Setelah itu, ya, ada sih beberapa kali saya mengalami nyeri gigi, tapi selalu gitu, dibiarin nyatanya sembuh sendiri. Lalu gigi belakang saya yang copot ini, sebenarnya sudah yang keempat. Awalnya oglak-aglik (goyang), eh, lepas sendiri. Ya sudah, saya pikir kalau seiring bertambahnya usia, seperti mbah-mbah itu kan, giginya memang pada copot, kan?” ujar Antonius kepada detikX yang mewawancara mereka berdua.
Ia tidak tahu bahwa masa pakai gigi manusia sebetulnya seumur hidup, alias bisa tetap utuh sampai meninggal, asalkan dirawat dengan baik sepanjang hidup. Perawatan yang dimaksud yaitu menjaga kebersihan mulut dengan gosok gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol dan gula berlebihan, tidak memiliki kebiasaan menggertakkan gigi, dan rutin periksa untuk mendeteksi permasalahan gigi dan penyakit gusi, agar dapat ditangani lebih awal.
Beberapa orang juga lebih rentan terhadap masalah gigi dan gusi karena faktor genetik. Oleh karena itu, periksa gigi enam bulan sekali sangat dianjurkan, sebab, sakit gigi dan biaya perawatan gigi yang sakit prinsipnya sama, makin dibiarkan atau ditunda perawatan giginya, makin bengkak.
Sayangnya, banyak masyarakat tidak memiliki kesadaran bahwa merawat gigi sepenting itu. Akibatnya, prevalensi karies gigi mencapai 88,8 persen (Riskesdas 2018), dan per 2023, 56,9 persen penduduk Indonesia berumur 3 tahun ke atas punya masalah gigi dan mulut. Bahkan, pada 2019, Indonesia negara peringkat kedua di Asia Tenggara dengan pengeluaran terbesar untuk pengobatan gigi (US$ 216 juta), yang juga kehilangan produktivitas akibat penyakit oral sebesar US$ 3,2 miliar, menurut laporan Oral Health Country Profile WHO.
Ironisnya, menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kementerian Kesehatan, dari sekian banyak penduduk yang mengalami masalah gigi dan mulut, hanya 11,2 persen yang berobat ke dokter gigi atau tenaga medis untuk mengatasi masalahnya. Beberapa alasan mengapa masyarakat tidak segera mencari pengobatan ke dokter gigi, kata survei itu, karena waktu tunggu yang lama (80,2 persen), mengobati sendiri (79,3 persen), berobat ke tukang gigi (77,5 persen), tidak ada biaya berobat (76,7 persen), dan seperti pengalaman Antonius, tidak merasa sakit gigi (70,2 persen).
Atik menceritakan pengalaman orang-orang di sekitarnya. Almarhum ibunya dulu sering sakit gigi, tapi tidak pernah periksa gigi. Yang dilakukan justru mengoleskan minyak angin atau ragi. Selain tindakan itu tidak ada dasar ilmiahnya, ragi bahkan tidak direkomendasikan untuk mengobati sakit gigi karena mengandung bakteri dan jamur, sehingga dapat meningkatkan jumlah bakteri dan jamur di mulut, yang bisa menyebabkan peradangan atau memperburuk infeksi.
Selain itu, Atik juga mendapati rekan kerjanya, keponakannya, dan tetangganya pergi ke tukang gigi. Ada di antaranya yang melakukan pemasangan kawat behel. Padahal, Pasal 6 Permenkes 34/2014 mengatur tukang gigi hanya boleh membuat dan memasang gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan heat curing acrylic sesuai persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. Realitanya, banyak tukang gigi bertindak di luar kewenangan, malpraktik, dan ujung-ujungnya menambah kasus gigi bermasalah.
Di luar hal-hal yang telah disebutkan, Atik menilai rendahnya kunjungan masyarakat ke dokter gigi juga karena perasaan takut. Anak laki-lakinya, dulu saat masih SD, sempat tidak mau ke dokter gigi lagi setelah satu pengalaman ke dokter gigi. “Waktu itu, gigi susunya tidak kunjung lepas meski kondisinya bagus. Dokternya saat itu bilang di depan anakku, ‘Wah, ini harus dicabut semuanya.” Batinku, waduh, trauma ini anakku. Oon dokternya, masa ngomong seperti itu di depan anak?” kisahnya.
Stigma seputar pengalaman periksa gigi dirasa masih kuat, diamini pula oleh seorang dokter gigi di Jakarta Selatan, drg. Adianti. Adianti berkisah, seorang pasien ibu yang rutin mengantar anaknya ke dokter gigi setiap bulan pun, masih menunda pengobatan giginya lantaran takut sakit. Padahal, makin ditunda, saat tindakan dilakukan bisa jadi lebih sakit karena kondisi gigi sudah bertambah parah, alhasil mengkonfirmasi atau makin menguatkan rasa takutnya.
Ada pula kasus yang pernah ia tangani, seorang anak usia 10 tahun gigi gerahamnya sudah pecah. Padahal, gigi tersebut baru tumbuh di usia 6, otomatis baru digunakan selama empat tahun. Usut punya usut, faktor penyebabnya malas menggosok gigi. Meski sudah datang ke dokter gigi dengan koyo di pipi, si anak takut giginya dicabut. Ia baru kembali lagi untuk penanganan dua tahun kemudian. Tidak hanya giginya makin rusak, tapi jumlah gigi yang rusak bertambah hingga empat.
“Padahal, sama saja seperti kalau anak malas sekolah, ya dipaksa sekolah karena pendidikan penting, kan? Ini pun begitu, paksa saja anak gosok gigi. Tentu dengan cara-cara yang baik, ya. Artinya, ini menggambarkan bahwa kesehatan gigi dan mulut tidak dianggap penting atau prioritas,” ujarnya.
Adianti prihatin karena kejadian tersebut bahkan terjadi di ibukota dan bukan di area pinggiran. Bahkan, pasien yang tidak memprioritaskan kesehatan gigi juga datang dari kelas menengah. Misalnya, yang menolak rontgen gigi karena dirasa mahal, sambil di lehernya tergantung dua buah pods (rokok elektrik).
Kata Adianti, ini jadi PR seluruh pihak untuk membetulkan bahkan dari hal mendasar seperti periksa gigi rutin dan kebiasaan gosok gigi. Banyak juga orang yang tidak tahu cara menggosok gigi yang baik dan benar, yaitu gunakan sikat gigi berbulu lembut (supaya aman untuk gusi dan tidak merusak enamel gigi) serta berukuran kecil (agar bisa menjangkau ke seluruh permukaan gigi), pegang sikat dengan sudut 45 derajat ke arah gusi, lalu sikat dengan gerakan memutar kecil dan lembut alih-alih menyikat keras dengan gerakan kanan-kiri. Lama menyikat minimal 2 menit. Terakhir, lengkapi dengan flossing, atau membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi.