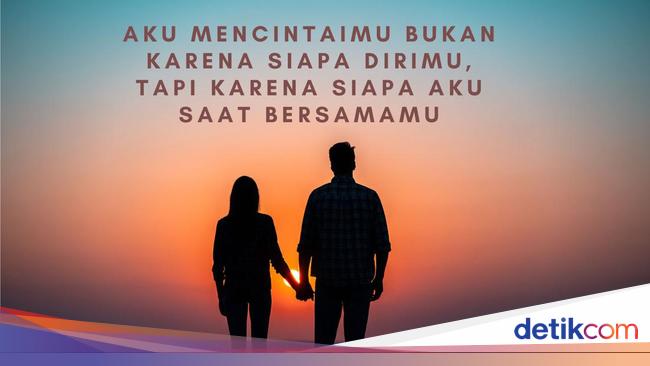Jakarta - Pemerintah Swedia baru-baru ini mengejutkan dunia dengan kebijakan yang bertolak belakang dari tren global: meninggalkan pendidikan digital dan kembali ke metode berbasis teks. Keputusan ini diumumkan pada Januari 2025, dengan pemerintah mengalokasikan anggaran setara Rp 1,7 triliun untuk mendukung transisi tersebut. Langkah ini bukan sekadar eksperimen pendidikan, tetapi juga peringatan keras bagi dunia terhadap dampak digitalisasi yang semakin masif.
Era digital yang awalnya dijanjikan sebagai solusi bagi akses informasi dan peningkatan intelektualitas justru berbalik menjadi ancaman serius terhadap pemikiran kritis dan komunikasi sosial. Apakah kita terlalu cepat mempercayai kemudahan teknologi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya?
Ancaman Nyata
Tidak hanya Swedia, Kanada dan Prancis juga telah mengambil langkah serupa dalam membatasi penggunaan perangkat digital di sekolah. Prancis melarang smartphone di ruang kelas untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan interaksi nyata. Sementara, beberapa provinsi di Kanada mengurangi penggunaan perangkat digital dalam proses pembelajaran setelah menyaksikan dampak negatifnya terhadap prestasi akademik siswa.
Langkah tersebut membuktikan bahwa meskipun teknologi memiliki manfaat, dampak negatifnya terlalu besar untuk diabaikan. Seorang jurnalis dan penulis asal Amerika, Nicholas Carr, dalam bukunya yang bertajuk The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains mengungkapkan bahwa konsumsi informasi serba cepat melalui layar digital menyebabkan otak kehilangan kemampuan berpikir mendalam.
Kebiasaan membaca sekilas dan budaya scrolling telah mengubah cara kita memproses informasi, menjadikannya serba dangkal dan instan. Otak manusia tidak lagi terbiasa menganalisis konsep yang kompleks, melainkan sekadar mengonsumsi informasi dalam bentuk potongan-potongan pendek tanpa refleksi mendalam. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi mendatang yang akan kesulitan membangun argumen logis dan kritis dalam berbagai aspek kehidupan.
Digitalisasi di Indonesia
Mestikah Indonesia mengambil kebijakan serupa? Hemat saya, jika kebijakan serupa diterapkan di Indonesia, tantangannya jauh lebih besar. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara belajar, tetapi juga membentuk pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat. Sayangnya, regulasi yang mengatur dampak digitalisasi terhadap masyarakat Indonesia masih sangat lemah. Literasi digital yang rendah telah menyebabkan maraknya penyebaran hoaks, polarisasi politik, serta budaya debat tanpa substansi yang mencerminkan rendahnya daya kritis masyarakat.
Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait literasi digital dan penggunaan teknologi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengatur tata kelola informasi digital, tetapi implementasinya masih banyak menuai kritik. Alih-alih meningkatkan literasi digital, pada kenyataannya UU ITE justru lebih banyak digunakan untuk menjerat individu yang dianggap melanggar norma tertentu, sementara upaya edukasi terhadap masyarakat luas masih minim.
Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum Merdeka Belajar. Namun, sejauh ini pengajaran literasi digital masih lebih banyak berfokus pada pengenalan teknologi dibandingkan membangun pola pikir kritis dalam menyikapi informasi yang beredar. Akibatnya, banyak masyarakat yang tetap rentan terhadap informasi sesat dan propaganda digital.
Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menginisiasi berbagai program edukasi keamanan digital, tetapi cakupannya masih sangat terbatas. Tanpa upaya masif dari pemerintah dalam membangun kesadaran digital secara menyeluruh, masyarakat akan terus menjadi korban manipulasi informasi yang beredar luas di internet.
Di sisi lain, kesenjangan digital di Indonesia juga menjadi tantangan besar. Sementara masyarakat perkotaan semakin bergantung pada teknologi, banyak daerah pedesaan yang masih sulit mengakses internet dan perangkat digital. Jika digitalisasi dibatasi secara ekstrem tanpa persiapan yang matang, justru akan semakin memperlebar kesenjangan pendidikan dan akses informasi. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan bukanlah penghapusan digitalisasi, tetapi penerapan strategi yang memastikan bahwa teknologi benar-benar digunakan sebagai alat untuk memperkuat daya pikir dan bukan sekadar sebagai hiburan semata.
Regulasi dan Pendidikan
Membatasi digitalisasi secara ekstrem tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang tepat dan sistem pendidikan yang mengajarkan bagaimana teknologi harus digunakan secara bijak. Pemerintah Indonesia harus mulai memperkuat kurikulum literasi digital yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun pola pikir kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di dunia maya.
Sebagai contoh, fenomena maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian selama Pemilu 2019 menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat yang belum memiliki kesadaran digital yang baik dapat dengan mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Saat itu, media sosial menjadi arena pertarungan opini yang sering kali tidak berbasis fakta, melainkan dipenuhi oleh propaganda dan disinformasi. Jika literasi digital masyarakat lebih baik, mereka tidak akan mudah terprovokasi dan mampu memilah informasi yang benar sebelum menyebarkannya.
Fenomena lainnya adalah ketergantungan terhadap aplikasi TikTok dan YouTube di kalangan anak-anak dan remaja yang mengarah pada menurunnya minat membaca buku. Studi dari Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak lebih tertarik mengonsumsi konten video singkat yang bersifat menghibur daripada membaca berita atau buku yang memerlukan konsentrasi dan pemahaman mendalam. Akibatnya, kemampuan berpikir analitis dan daya tahan membaca mereka semakin menurun.
Oleh karena itu, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga krusial dalam membentuk kebiasaan konsumsi informasi yang sehat. Orangtua dan pendidik harus lebih aktif dalam mengarahkan anak-anak agar tidak terjebak dalam pola konsumsi digital yang dangkal. Membiasakan kembali membaca buku fisik, berdiskusi secara langsung, dan menulis secara mendalam bisa menjadi salah satu cara untuk melawan efek negatif dari budaya instan yang dibawa oleh era digital.
Digitalisasi bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus dikendalikan dengan bijak. Langkah Swedia, Kanada, dan Prancis merupakan alarm peringatan bagi kita semua bahwa teknologi, jika tidak digunakan dengan tepat, bisa menjadi ancaman terhadap kualitas berpikir manusia. Indonesia harus belajar dari kebijakan negara-negara ini, tetapi dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang berbeda.
Alih-alih menghilangkan teknologi, kita harus memastikan bahwa penggunaannya benar-benar memperkuat intelektualitas, bukan malah melemahkannya. Pemerintah perlu lebih serius dalam merancang kebijakan yang tidak hanya fokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga menanamkan kesadaran digital yang sehat bagi masyarakat. Jika tidak ada upaya untuk menyeimbangkan teknologi dengan budaya berpikir kritis, kita hanya akan menghasilkan generasi yang sekadar terampil dalam mengakses informasi, tetapi gagal dalam memahami dan mengolahnya secara mendalam. Dan, itu lebih berbahaya daripada sekadar kehilangan akses terhadap teknologi itu sendiri.Turangga Anom mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Insan Cita Indonesia (mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu