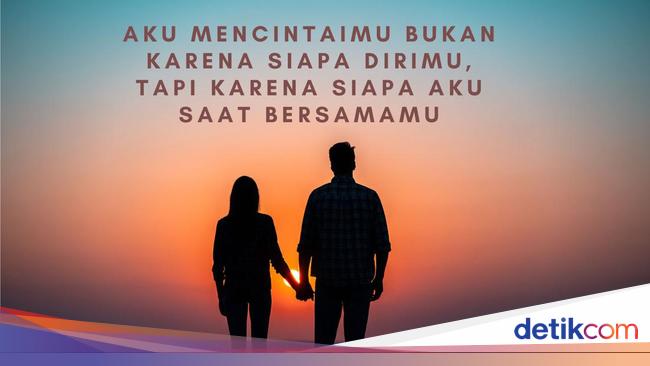Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyampaikan optimisme besar atas lembaga baru yang ia pimpin. Namun narasi tentang peran BP Taskin kerap bersinggungan dengan fungsi kementerian dan lembaga lain. Keberadaan lembaga seperti Kementerian Sosial, Bappenas, dan BRIN, yang juga berperan dalam riset dan rekomendasi kebijakan pengentasan masyarakat miskin, membuat kehadiran BP Taskin dipertanyakan.
Walaupun demikian, Budiman menegaskan BP Taskin hadir bukan untuk mengambil alih peran lembaga lain, seperti Bappenas. Namun menjadikannya partner yang memastikan pengarusutamaan program pemberantasan kemiskinan di tiap lembaga.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam upaya pengentasan masyarakat miskin adalah ego sektoral antarkementerian atau lembaga. Budiman menyadari hal ini dan BP Taskin mengeklaim akan berupaya menjadi jembatan koordinasi.
“Kita coba terapkan model pengentasan kemiskinan yang multisektoral yang tidak ada ego sektoral,” kata Budiman kepada detikX, pada Rabu, 19 Februari 2024.
Salah satu kekhawatiran publik adalah soal implementasi rekomendasi BP Taskin yang menguap begitu saja tanpa ditindaklanjuti. Terlebih diakui banyak rekomendasi kebijakan maupun aturan terkait pemberantasan kemiskinan yang tumpang tindih. Namun Budiman mengeklaim lembaganya memiliki kekuatan hukum melalui perpres untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.
“Kami berhak memberikan laporan mana yang tumpang tindih, mana yang kurang tepat sasaran, mana yang pemborosan,” tegasnya.
Budiman mengatakan rekomendasi dari BP Taskin akan diserahkan kepada kementerian terkait dan Presiden Prabowo Subianto. Presiden disebut akan memantau secara langsung jalannya rekomendasi tersebut. Hal itu diklaim menjadi jaminan rekomendasi BP Taskin tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan demi mencapai tujuan pemberantasan kemiskinan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, diakui Budiman, tumpang tindih ini bukan hanya soal fungsi, tetapi juga data. Hingga kini, data kemiskinan Indonesia sering kali berbeda antara satu lembaga dan yang lain.
“Selama ini kan kayak bansos itu basis datanya beda-beda. Nah, itu bakal kami susun,” ujar Budiman.
Namun menyatukan data dari berbagai kementerian yang memiliki metodologi sendiri bukan perkara mudah. Persoalan semakin rumit jika dibandingkan dengan negara lain yang berhasil melakukan pemberantasan kemiskinan dengan birokrasi yang lebih ramping. Brasil, misalnya, dengan program Bolsa Familia, berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui mekanisme bantuan tunai bersyarat yang dikelola terpusat. Di Indonesia, tumpang tindih fungsi justru sering memperlambat pelaksanaan program.
Di tengah kompleksitas itu, BP Taskin juga menghadapi tantangan dalam mendefinisikan standar kemiskinan.
“Angka kemiskinan menurun, tapi parameternya juga turun. Kita tahu kenyataannya, teman-teman miskin kita jumlahnya mungkin sudah jutaan,” kata Budiman. Pernyataan ini menunjukkan betapa rumitnya memotret kondisi riil kemiskinan di Indonesia.
Apakah BP Taskin benar-benar dibutuhkan? Ataukah justru memperpanjang rantai birokrasi yang seharusnya disederhanakan?
Pembentukan BP Taskin, yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko, menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai badan ini tidak mendesak dan berpotensi menjadi lembaga yang tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada.
“Kenapa mesti pakai badan baru, bentuk badan baru? Kan namanya TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) itu sudah ada dan punya fungsi strategis untuk menanggulangi kemiskinan. Tim ini juga sudah bekerja bertahun-tahun,” ucap Esther saat diwawancarai detikX.
Menurut Ester, meski hasil kerja TNP2K belum terlihat signifikan karena tingkat kemiskinan hanya turun 2 persen dalam sepuluh tahun terakhir, keberadaan tim tersebut seharusnya bisa dilanjutkan. Ia justru mempertanyakan alasan pembentukan badan baru yang dikhawatirkan hanya menjadi tempat penampungan orang-orang dekat Presiden.
“Saya takut dengan adanya BP Taskin ini juga sebenarnya sama saja. Yang pertama hanya untuk menampung orang-orang koalisi besar. Kenapa harus bentuk badan baru? Toh, kalau tinggal meneruskan tugas TNP2K, kan lebih enak, nggak mulai dari nol,” ujarnya.
Dari sudut pandang ekonomi, Ester menegaskan pembentukan BP Taskin tidak terlalu penting karena fungsi yang diembannya sudah bisa dilakukan oleh lembaga yang ada, seperti Bappenas, BPS, dan kementerian-kementerian terkait.
“Saya tuh yang menurut saya tidak urgen ya untuk membentuk badan ini. Fungsi itu tuh sudah bisa dilakukan oleh Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenkop, Kemen UMKM. Pemerintahan ini kebanyakan kementerian dan lembaga. Sudah tahu problemnya, tinggal dilaksanakan,” jelasnya.
Selain itu, tujuan BP Taskin untuk menyatukan data kemiskinan juga dinilai bukan hal baru. Menurut Ester, integrasi data antarkementerian seharusnya bisa dilakukan melalui BPS tanpa perlu membentuk badan baru.
“Kan cuma tinggal minta antarlembaga diintegrasikan, kan bisa di BPS. Apa fungsinya BPS kalau bukan untuk menyatukan data? Yang benar adalah mengintegrasikan data antarkementerian, sehingga subsidi itu tepat sasaran. Selama ini memang tidak ada integrasi data karena masing-masing punya wilayah sendiri-sendiri,” kata Ester.
Setidaknya terdapat 9,1 juta penduduk miskin Indonesia yang hilang dari catatan resmi pemerintah atau tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini dianggap paradoks di tengah kehadiran BP Taskin yang dianggap sebagai solusi baru.
Menurut Bank Dunia, pada 2021 Indonesia sudah memiliki 15 lembaga yang mengurusi isu kemiskinan. Namun Bank Dunia mencatat 30 persen anggaran kemiskinan terbuang sia-sia karena tumpang tindih program. Di Papua, misalnya, 40 persen dana kemiskinan justru tersedot untuk biaya administrasi lembaga, bukan langsung ke masyarakat (Bappenas, 2023).
Salah satu akar masalahnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan 9,4 persen pada Maret 2023, tetapi kriteria yang digunakan jauh dari realitas. Garis kemiskinan BPS sebesar Rp 535.547 per kapita per bulan hanya memenuhi kebutuhan makanan dasar (2.100 kkal/hari), sementara biaya kesehatan, transportasi, dan pendidikan diabaikan. Jika menggunakan standar Bank Dunia (USD 2,15 per hari), angka kemiskinan Indonesia melonjak menjadi 14,6 persen—setara dengan 40 juta orang.
Ketidakakuratan data ini dianggap seperti racun yang merusak kebijakan. Studi The SMERU Research Institute pada 2022 bertajuk ‘Ketimpangan Akses Bansos dan Dampaknya pada Kemiskinan Multidimensi’ mengungkap 40 persen rumah tangga miskin di pedesaan Jawa tidak terdata dalam DTKS karena metode pendataan yang mengandalkan kriteria fisik usang, seperti lantai tanah atau kepemilikan ternak, sementara indikator modern, seperti akses air bersih dan stunting, diabaikan.
TNP2K—lembaga koordinator kemiskinan yang ada sebelum BP Taskin—berdasarkan kajian SMERU tersebut, dianggap kehilangan taring karena tak punya kewenangan memaksa kementerian patuh. Alih-alih menyelesaikan masalah, ego sektoral antarlembaga, seperti Kementerian Sosial, Kemendes PDTT, dan Bappenas, menciptakan kebijakan yang bertubrukan. Program Rastra dan BPNT, misalnya, menargetkan kelompok sama, tetapi 35 persen penerimanya tumpang tindih.
Di Jawa Tengah, 34 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata tidak miskin, ini berdasarkan studi SMERU pada 2021 bertajuk ‘Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Masa Pandemi’. Sebaliknya, 22 persen keluarga miskin ekstrem di NTT justru tak kebagian bantuan. Basis data utama bansos, DTKS, 25 persennya belum diperbarui sejak 2015—data usang ini masih menjadi acuan, membuat program bansos ibarat ‘obat kedaluwarsa’ untuk penyakit akut.
Kegagalan tidak berhenti di data. Evaluasi SMERU terhadap PKH menemukan dua masalah utama: 34 persen penerima bansos tidak memenuhi kriteria miskin (inclusion error), sementara 22 persen keluarga miskin ekstrem justru terabaikan (exclusion error). Penyebabnya? Verifikasi data oleh kepala desa yang rentan manipulasi dan ketiadaan mekanisme pemutakhiran atau real time.
Pemerintah Indonesia dinilai terlalu fokus pada pencapaian angka statistik (misalnya: menekan persentase kemiskinan) ketimbang menyelesaikan masalah mendasar, seperti ketimpangan, kualitas SDM, dan tata kelola data. Jika tidak ada perubahan sistemik, program pemberantasan kemiskinan hanya akan menjadi alat politik temporer, bukan solusi berkelanjutan. Seperti laporan Bank Dunia pada 2021, pemberantasan kemiskinan bukan tentang menciptakan lembaga baru, tapi memperbaiki sistem yang rusak. BP Taskin bisa menjadi awal reformasi—atau sekadar babak baru dalam drama birokrasi yang tak berujung.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti menyoroti sejumlah permasalahan mendasar dalam pembentukan badan ini, mulai urgensinya, potensi tumpang tindih kewenangan, hingga persoalan akuntabilitas.
Menurut Susi, pembentukan BP Taskin harus dilihat dalam konteks tujuan bernegara yang dijalankan melalui fungsi-fungsi negara, khususnya oleh cabang kekuasaan eksekutif. Fungsi eksekutif ini, salah satunya, adalah mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, termasuk pemberantasan kemiskinan. Namun ia mempertanyakan berapa banyak jabatan yang akan dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut, mengingat kewenangan terkait pemberantasan kemiskinan sudah tersebar di berbagai kementerian.
“Ketika cabang kekuasaan eksekutif, fungsi-fungsi itu antara lain untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat, dan di situ kan percepatan pengentasan kemiskinan, maka pertanyaannya adalah, satu, ada berapa jabatan yang akan dibentuk untuk menjalankan fungsi itu? Kita mengetahui di dalam cabang kekuasaan eksekutif itu ada jabatan-jabatan kementerian dan jabatan-jabatan kementerian itu salah satunya kan akan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, dan itu kan tersebar di dalam berbagai Kementerian,” kata Susi kepada detikX.
BP Taskin merupakan peningkatan status dari tim percepatan pengentasan kemiskinan yang sebelumnya sudah ada. Meski disebut sebagai jabatan nonstruktural, badan ini berada langsung di bawah Presiden Prabowo, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala badan.
Penggunaan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, kata Susi, sebagai dasar hukum pembentukan badan ini bisa menimbulkan persoalan bila tidak dibatasi dengan jelas.
“Kalau ini tidak dibatasi dengan beberapa limitasi, kekuasaan ini bisa sangat besar. Itu bisa menjadi eksesif, seakan-akan Presiden bisa membentuk jabatan apa pun yang dia inginkan. Nah, ini kan nggak boleh seperti itu, setiap kekuasaan itu harus ada batasannya,” tegasnya.
Selain itu, Susi menyoroti posisi kepala BP Taskin yang setingkat menteri, meskipun dalam tata kelola pemerintahan, kementerian memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan badan nonstruktural.
“Kita tidak pernah tahu ketika Presiden membentuk berbagai badan itu, rakyat tidak mengetahui bagaimana kajian-kajian akademiknya, bagaimana kajian-kajian ilmiahnya, di mana di situ memperlihatkan urgensi pembentukan jabatan-jabatan baru tersebut,” terangnya.
Lebih jauh, Susi juga mempertanyakan kapasitas BP Taskin dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program-program pemberantasan kemiskinan yang dijalankan oleh kementerian. Menurutnya, setiap kementerian sudah memiliki mekanisme evaluasi dan pengawasan masing-masing.
Persoalan akuntabilitas BP Taskin juga menjadi sorotan, terutama karena badan ini belum memiliki mitra kerja di DPR untuk fungsi pengawasan. BP Taskin seharusnya memiliki mitra kerja di DPR agar dapat diawasi dengan baik. Terutama dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN.
“Jadi begini, di dalam penyelenggaraan suatu negara, tidak ada satu jabatan pun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban itu kan dalam berbagai macam bentuk. Agar dia akuntabel, antara lain mekanismenya adalah mekanisme checks and balances, mekanisme pengawasan,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti terkait penandatanganan memorandum of understanding (MoU) BP Taskin dengan pemerintah daerah, seperti yang terjadi dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Ia mempertanyakan dasar hukum dan bentuk pelaksanaan MoU tersebut.
“Mengapa harus dibuat MoU? MoU itu kan memorandum of understanding, dan ini kelihatannya menjadi tren baru di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Buat apa dibikin MoU yang itu bentuk hukumnya apa, dasar hukumnya apa?” katanya.