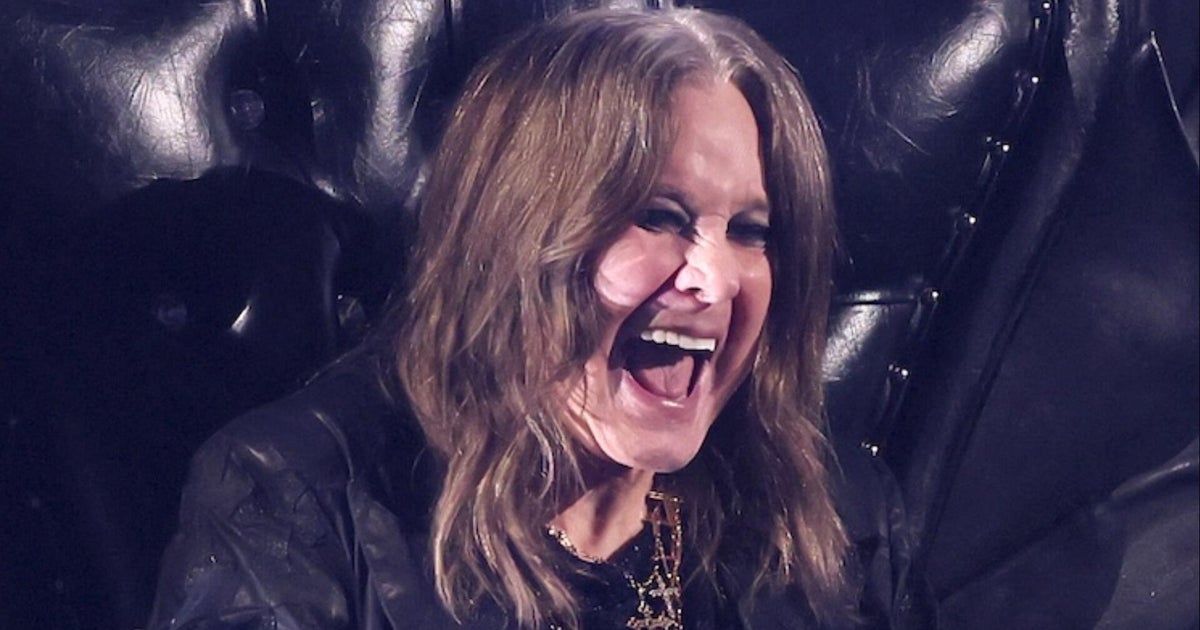Jakarta - Kebangkrutan Sritex dan sejumlah perusahaan di Jawa Barat mempertegas gejala deindustrialisasi di Indonesia. Ironisnya, pemerintah dan para politisi semakin mempertontonkan dramaturgi politisasi aktivitas ekonomi secara masif. Nuansa politisasi ekonomi terasa kental manakala lembaga negara strategis diisi oleh politisi. Alih-alih menuntaskan masalah, kebijakan yang diterbitkan justru mengacaukan ekosistem industri lokal.
Pendirian Danantara yang dimodali uang hasil efisiensi memancing sentimen negatif pasar. Nyaris tidak ada pembicaraan serius ihwal pemanfaatan dana hasil efisiensi untuk mengobati gejala deindustrialisasi. Di sisi lain, kebijakan ekonomi semakin tidak berpihak pada pelaku usaha lokal dan akrobat politik Indonesia dalam perdagangan global malah menumbangkan industri lokal. Sambutan dingin pasar modal dan merebaknya narasi berkonotasi negatif adalah manifestasi ketidakpercayaan publik pada agenda ini.
Politisasi Ekonomi
Kay (1980) mendefinisikan politisasi sebagai pengambilan keputusan dalam kompetensi fungsional lembaga atau program yang bersifat politis tanpa mempertimbangkan faktor teknis dan ilmiah. Dalam konteks ekonomi, politisasi ekonomi dapat dimaknai sebagai pengelolaan ekonomi dengan pendekatan politis yang dominan dan mengabaikan prinsip dan kompetensi ekonomi. Pintu gerbang dari politisasi ekonomi adalah penempatan kepemimpinan politisi pada ruang aktivitas ekonomi.
Implikasi politisasi ekonomi adalah maraknya keputusan politis terkait urusan ekonomi tanpa pertimbangan teknis dan ilmiah. Hal ini berpotensi memicu fenomena rent-seeking (berburu rente), di mana aktor tertentu mempengaruhi kebijakan demi keuntungan pribadi, bukan kepentingan publik, melalui lobi, monopoli, atau korupsi. Tentu saja, muara dari kekacauan ini adalah melemahnya kepercayaan pasar terhadap negara dan berimplikasi pada deindustrialisasi.
Politisasi ekonomi telah menjadi penghambat utama daya saing industri Indonesia. Kebijakan ekonomi lebih berorientasi pada kepentingan politik daripada kepentingan ekonomi nasional memperlemah dunia industri. Proteksi berlebihan melalui regulasi atau subsidi yang diberikan karena kedekatan dengan elite politik membuat industri tidak kompetitif.
Keberpihakan negara dipertanyakan ketika membuka keran impor yang akhirnya memukul industri lokal. Pemerintah yang harusnya menggunakan power politik untuk menciptakan kondusivitas iklim usaha justru abai dan bekerja setengah hati. Pemerintah nampak serius dalam menata perizinan melalui revisi PP 5/2021 terkait Perizinan Berbasis Risiko, namun lupa untuk menata masalah lain dunia usaha yang jauh lebih krusial.
Organisasi Kemasyarakatan yang notabene vote gater dalam kontestasi politik dibiarkan mengganggu dunia usaha, bahkan yang terkecil. Pemerintah yang seharusnya menjamin keamanan justru gelagapan menghadapi gangguan keamanan. Malah, beberapa pejabat publik tercatat dalam struktur kepengurusan dari kelompok tersebut. Lagi-lagi urusan politik mengalahkan kepentingan ekonomi sehingga berdampak pada melemahnya trust pasar.
Bicara soal vote gater, industri dan para buruh justru dijadikan komoditas panas dalam pesta demokrasi. Selaksa janji manis seperti kenaikan upah dan penyelamatan PHK dilontarkan dengan "enteng". Saat terjadi hal buruk dan janji itu ditagih, selaksa jawaban dilontarkan untuk lari dari janji dan tanggung jawab yang terlanjur diucapkan. Industri justru dipolitisasi untuk urusan pemenangan pemilu daripada diperkuat dengan kebijakan politik yang pro ekonomi.
Deindustrialisasi Dini
Deindustrialisasi dini di Indonesia adalah karma atas kegagalan pemerintah dalam mengelola aktivitas perekonomian dan melindungi industri lokal dalam perdagangan global. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun setiap tahunnya. Ini adalah deindustrialisasi dini, di mana dengan realitas bahwa negara kita adalah negara berkembang dan penyerapan tenaga kerja masih bergantung pada sektor industri, namun kita sudah tumbang duluan.
Pada 2008, kontribusi sektor manufaktur non-migas terhadap PDB mampu mencapai 27,8 persen dan semakin menurun di mana kontribusinya hanya sebesar 18,67 persen pada 2023. Penurunan ekstrem ini dipicu oleh lemahnya daya saing industri kita menghadapi gempuran produk impor dari luar negeri yang murah dan mudah diperoleh. Nyaris tidak ada kebijakan proteksi terhadap industri kita, buktinya adalah semakin maraknya industri yang tumbang.
Masalah lainnya, industri asing yang beroperasi di Indonesia turut angkat kaki dan berkontribusi atas ekstremnya deindustrialisasi. Terlepas dari alasan strategi bisnis perusahaan, semestinya kita merefleksikan kembali, apakah kita sudah menjadi tuan rumah yang nyaman atau sebaliknya? Persoalan regulasi dan politik yang tidak stabil hingga ketidakpastian hubungan industrial mendeterminasi persoalan ini.
Kebijakan perdagangan global kita yang mendorong kompetisi tanpa memperkuat pondasi industri kita berujung pada babak belurnya industri lokal. Tumbangnya Sritex dan industri lainnya memberikan efek sistemik yang besar secara perekonomian. Dalam kasus Sritex, penutupan perusahaan ini turut mematikan usaha lokal seperti warung makan hingga tempat penitipan motor. Bayangkan jika hal ini terjadi secara lebih masif di Indonesia, tentu akan menjadi kiamat ekonomi yang menyedihkan.
Isu lain yang patut untuk menjadi atensi adalah terkait regulasi yang kian tidak berpihak pada industri. Misalnya, regulasi terkait PP 28/2024 yang salah satunya membahas terkait pertembakauan menuai resistensi dari industri rokok dan industri lainnya seperti reklame. Pengaturan yang terlampau berlebihan berpotensi mematikan ekonomi nasional. Negara mungkin mendulang pendapatan besar dari cukai, namun produksi dan penjualan yang menurun berdampak sistemik pada stakeholder di hulu-hilir industri ini.
Ketergantungan pemerintah daerah terhadap keberadaan industri tak bisa dipungkiri, sebab aktivitas industri berhasil menciptakan multiplier effect yang menguntungkan pemda dan masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa daerah yang bergantung pada sektor primer cenderung mengalami stagnasi secara ekonomi. Semestinya, pemerintah pusat melihat ini sebagai ekosistem yang berkaitan sehingga kebijakan perindustrian kita berorientasi pada spirit Indonesia First: mengutamakan kepentingan dan penguatan lokal.
Deindustrialisasi dini adalah imbas dari kegagalan kita menghadapi globalisasi dan borderless economy yang semakin nyata. Keberpihakan pemerintah semestinya konkret dan komit terhadap penguatan industri, khususnya skala kecil dan menengah. Kepastian dan kemudahan berusaha dalam bentuk penyederhanaan perizinan perlu diimbangi dengan komitmen memberantas pungutan liar dan penerbitan regulasi yang tak mudah berubah. Jika tidak ada perubahan, deindustrialisasi akan jadi batu sandungan menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% Prabowo-Gibran.
Eduardo Edwin Ramda analis kebijakan di Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
(mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini