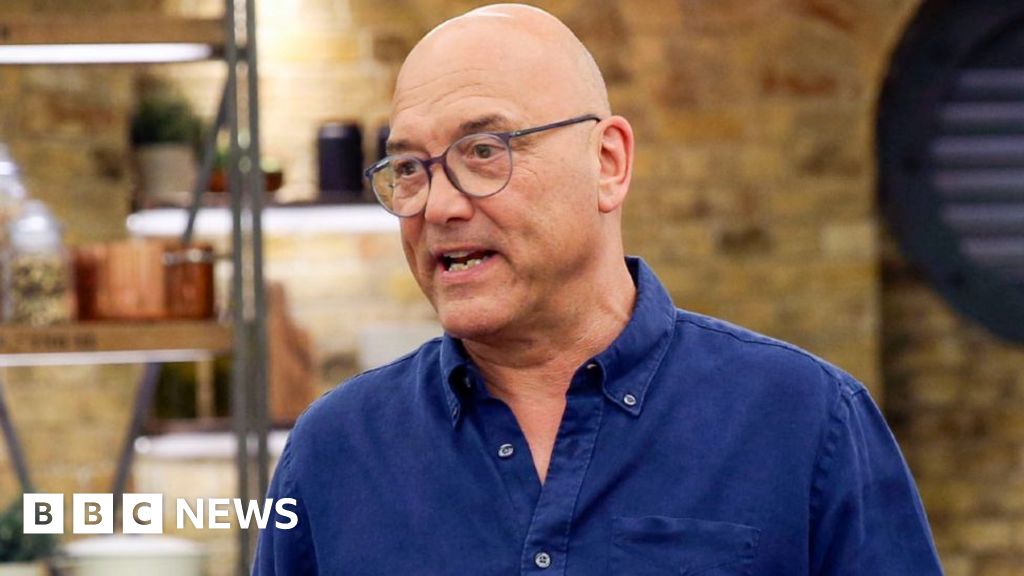Jakarta - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya di Hambalang menjadi momen penting yang mencerminkan dinamika baru dalam hubungan antara politisi dan media di Indonesia. Dalam suasana yang relatif santai dan terbuka, Prabowo membahas berbagai isu strategis seperti RUU TNI, hubungan luar negeri, dinamika politik dalam negeri, hingga isu Trump Tariff --menunjukkan sisi lain dari dirinya sebagai presiden terpilih yang tengah bersiap memasuki kekuasaan secara resmi.
Di balik kesan keterbukaan itu, wawancara ini menyimpan banyak lapisan makna, baik dari sisi politik komunikasi maupun dari konstruksi citra populis yang melekat pada diri Prabowo. Edward Aspinall (2015) telah menjelaskan karakteristik Prabowo sebagai populis oligarkis—figur yang menyerukan anti-elitisme dan nasionalisme sembari menjadi bagian dari elite itu sendiri.
Pertemuan dengan jurnalis ini dapat dilihat sebagai bagian dari strategi Prabowo untuk mengelola persepsi publik dan menjembatani kesan "keras" yang selama ini melekat padanya. Dengan menyambut jurnalis senior dan memberikan ruang untuk bertanya tanpa sensor, Prabowo seolah mengisyaratkan bahwa ia bukan figur otoriter yang tertutup terhadap kritik atau media, tetapi seorang pemimpin baru yang mengedepankan transparansi dan kedekatan dengan publik.
Namun, jika mengikuti analisis Aspinall, pendekatan ini bisa juga dibaca sebagai bagian dari taktik populisme personalistik, di mana pemimpin memanfaatkan media untuk membentuk citra autentik yang "langsung dari sumbernya" dan memotong perantara institusional yang biasa seperti konferensi pers formal.
Dilihat dari kacamata jurnalisme politik, peristiwa ini mencerminkan elemen-elemen dari apa yang disebut Todd Schaefer (1999) sebagai praktik rhetorical presidency yang berupaya mengelola pesan melalui media dengan mempertimbangkan dinamika bias media dan logika pemberitaan politik sebagai ajang pertarungan wacana.
Ketika Prabowo menyampaikan pandangan-pandangannya secara terbuka dan personal kepada para jurnalis yang kredibel, ia tidak hanya sedang "memberikan wawancara", tetapi sedang mengelola framing yang akan muncul di media pasca wawancara. Strategi ini relevan dengan penemuan dalam studi Banning dan Billingsley (2007), yang menunjukkan bahwa dalam setting informal atau solo press conference, seperti yang dilakukan Prabowo, jurnalis cenderung lebih agresif, tetapi juga berpotensi memberikan ruang yang lebih besar untuk eksplorasi naratif dari sisi politisi.
Di sisi lain, dari sudut pandang hubungan jurnalisme dan ilmu politik sebagaimana dikemukakan Nyhan dan Sides (2011), momen seperti ini menjadi contoh bagaimana narasi politik yang dibangun secara episodik—misalnya tentang rencana Prabowo terhadap RUU TNI dan RUU Polri atau tentang hubungannya dengan Presiden Jokowi—sering mengaburkan konteks struktural yang lebih luas, seperti bagaimana distribusi kekuasaan di lingkaran pemerintahan akan membentuk efektivitas kebijakan.
Dalam wawancara itu, Prabowo tampil percaya diri dan artikulatif, tetapi tidak semua pernyataannya dijabarkan dengan latar kebijakan yang konkret. Dalam kerangka ini, penting bagi jurnalis untuk tidak hanya memberitakan "apa yang dikatakan" tetapi juga mengaitkannya dengan konteks struktural politik yang lebih luas, seperti relasi civil-military dan dinamika partai dalam pemerintahan koalisi besar.
Mengontrol Narasi
Perspektif Martha Joynt Kumar (2020) terasa relevan untuk membaca praktik komunikasi Prabowo dalam wawancara tersebut. Kumar mencatat bahwa dalam era komunikasi politik kontemporer, presiden cenderung memilih format komunikasi yang membuat mereka merasa nyaman dan tetap mengontrol narasi.
Dalam hal ini, wawancara dengan tujuh jurnalis senior yang dilakukan secara tertutup dan tidak live di media sosial menjadi bentuk komunikasi yang aman, terkontrol, dan bisa diedit dari segi impresi publik. Prabowo, seperti yang juga dilakukan oleh presiden-presiden AS, tampaknya mulai mengadopsi format semi-formal yang memberikan ruang untuk narasi personal tetapi tetap menghindari risiko pertanyaan spontan dalam forum publik luas.
Kehadiran tujuh jurnalis senior dalam satu forum eksklusif juga menarik dilihat dari dinamika kolektivitas jurnalis dalam memaknai wawancara politik. Dalam studi Journalist Aggressiveness in Joint Versus Solo Presidential Press Conferences, Banning dan Billingsley (2007) menunjukkan bahwa konferensi pers solo lebih memungkinkan terjadinya tekanan lebih besar terhadap presiden.
Namun dalam kasus ini, meskipun secara teknis solo interview, keberadaan tujuh jurnalis dari media berbeda justru menghadirkan format diskusi yang lebih cair daripada formal. Hal ini memungkinkan Prabowo menyampaikan narasi-narasi pentingnya dengan sedikit gangguan, serta sekaligus memecah potensi tekanan karena tiap jurnalis hanya mendapat sedikit waktu untuk mengeksplorasi topik.
Namun, strategi ini juga menunjukkan bagaimana media dijadikan kanal untuk membangun konsensus simbolik tentang arah pemerintahan ke depan. Jika dilihat dari optik populisme oligarkis, Prabowo tidak sedang membongkar struktur kekuasaan yang mapan, tetapi sedang menyesuaikan dirinya agar diterima oleh kekuasaan media dan elite politik yang kini berada di bawah bayang-bayang koalisi besar yang ia masuki.
Wawancara ini menjadi bagian dari proses "normalisasi" figur Prabowo sebagai presiden baru: dari seorang mantan jenderal dengan citra kontroversial menjadi seorang negarawan yang siap memimpin bangsa dengan tenang dan rasional.
Akhirnya, yang paling signifikan dari pertemuan ini adalah bagaimana ia mencerminkan transformasi strategi komunikasi Prabowo dari seorang "outsider populis" menjadi "insider teknokratis" dalam lanskap politik Indonesia yang tetap oligarkis. Dengan menghadirkan jurnalis-jurnalis senior dan membuka percakapan mengenai isu-isu strategis, ia mengirim sinyal bahwa kepemimpinannya tidak akan bersifat tertutup, tetapi tetap berada dalam kerangka yang ia kontrol.
Ini adalah bentuk komunikasi politik yang berakar pada tradisi populisme, tetapi beradaptasi dengan realitas pasca-kemenangan—di mana simbolisme, impresi personal, dan narasi keseimbangan memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi dan stabilitas politik yang telah diraihnya.
Shela Kusumaningtyas pemerhati komunikasi politik
(mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini