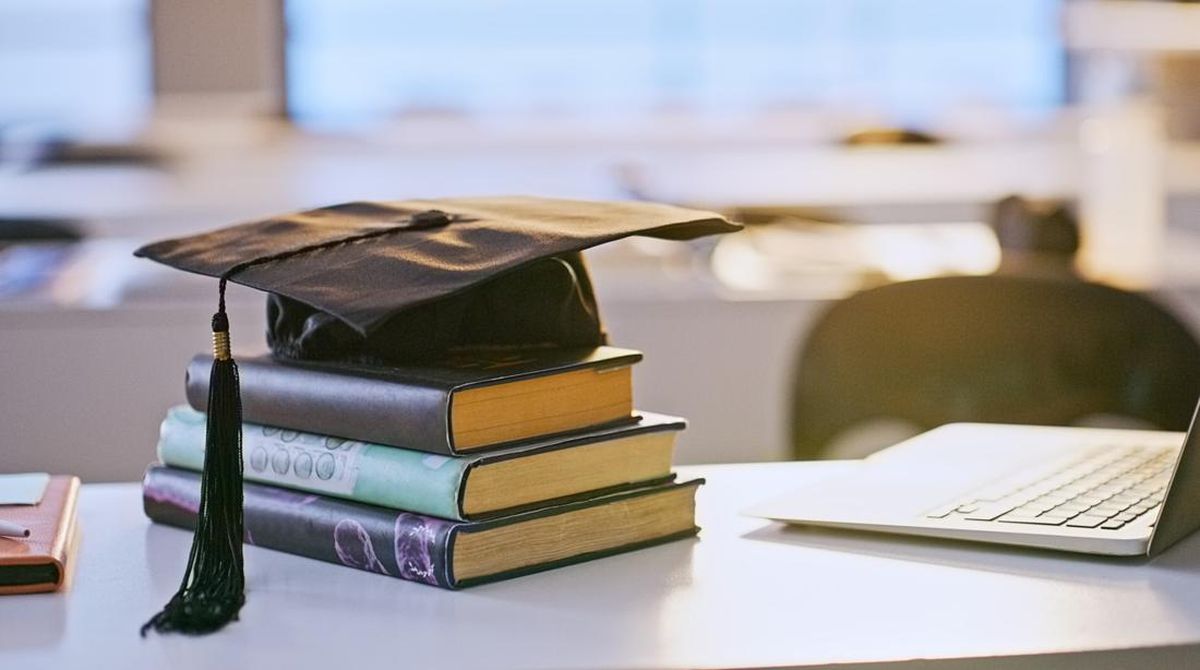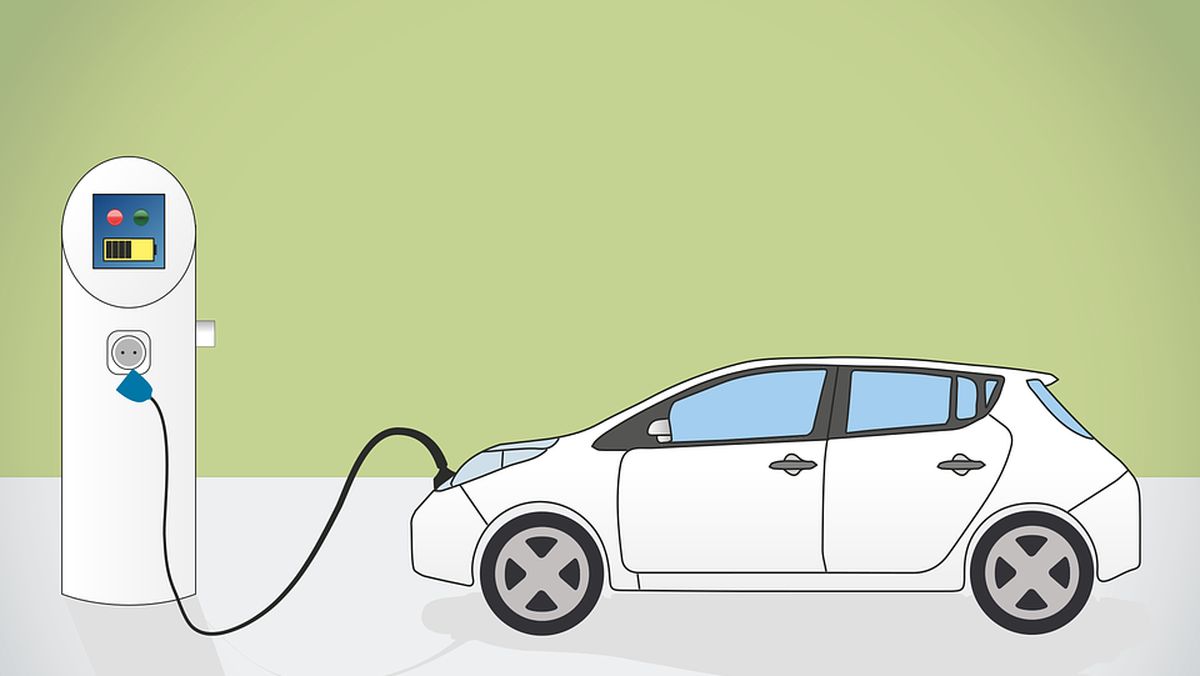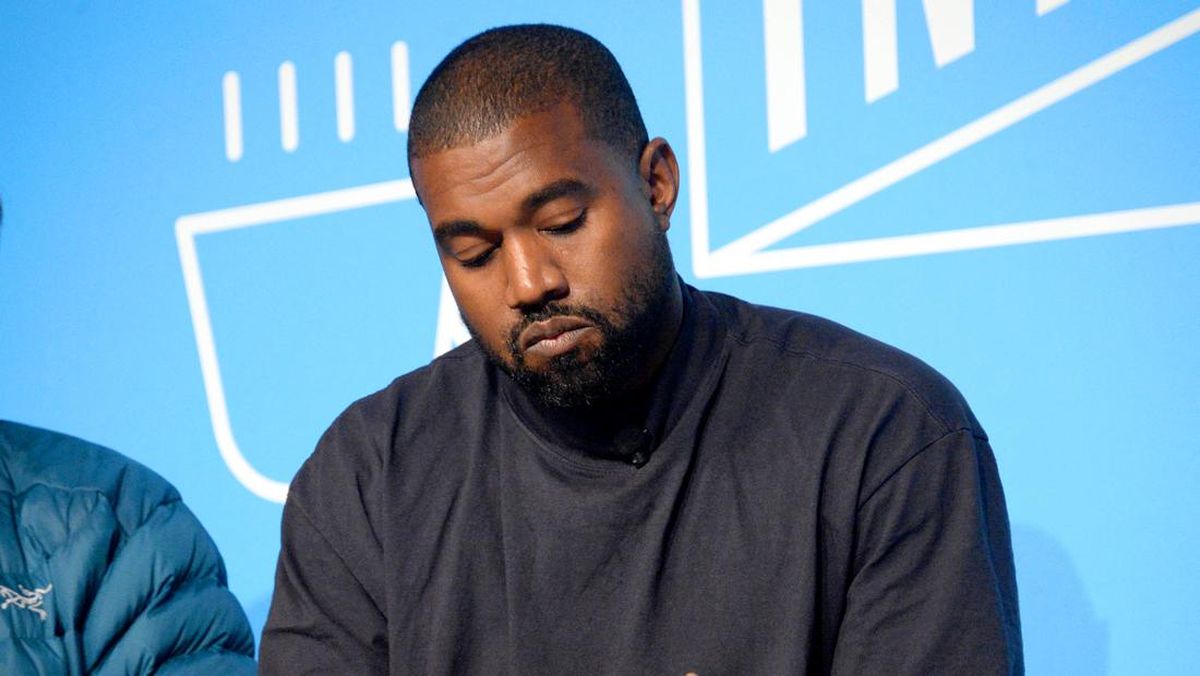Jakarta -
Awal tahun ini, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam Indonesia. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan, dalam dua bulan pertama 2025 saja, tercatat 18.610 orang kehilangan pekerjaan. Mayoritas berasal dari industri pengolahan, terutama tekstil dan garmen, dua sektor yang selama ini jadi tumpuan jutaan pekerja.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 berada di angka 4,76 persen, terendah sejak krisis 1998. Namun, secara absolut, jumlah pengangguran justru bertambah 83.000 orang dibandingkan tahun lalu. Artinya, ada masalah yang lebih mendalam: ekonomi memang tumbuh, tapi belum inklusif.
Tekanan Struktural
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fenomena PHK ini bukan sekadar ketidakberuntungan perusahaan atau siklus bisnis. Ia mencerminkan perubahan dalam struktur ekonomi. Tekanan biaya, disrupsi teknologi, hingga perubahan pola konsumsi membuat banyak sektor lama tergerus, sementara sektor baru belum cukup kuat jadi penyangga.
Teori transformasi struktural Simon Kuznets (1955) menjelaskan bahwa saat ekonomi tumbuh, tenaga kerja bergeser dari pertanian ke industri, lalu ke jasa. Namun jika transisi ini berlangsung tanpa kesiapan sistem dan kebijakan, hasilnya bukan kemajuan, tapi dislokasi sosial. Sektor industri kehilangan napas, sementara sektor baru masih menyempurnakan paru-parunya.
Gejala pengangguran terselubung juga mulai tampak: jutaan orang bekerja di sektor informal dengan penghasilan tak menentu. Menurut BPS, per Februari 2025, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 86,58 juta orang, atau 59,40 persen dari total penduduk bekerja; naik dari 59,17 persen tahun lalu. Mayoritas tenaga kerja masih hidup tanpa perlindungan sosial dan kepastian pendapatan.
Sektor Penyelamat
Tak semua sektor kehilangan daya. Sektor perdagangan menyerap hampir satu juta tenaga kerja baru, disusul pertanian dan industri pengolahan. Tapi sebagian besar dari penyerapan itu terjadi di sektor informal. Ada pekerjaan, tapi belum tentu perlindungan. Ada penghasilan, tapi belum tentu masa depan.
Kita perlu memetakan sektor-sektor yang jadi tumpuan: ekonomi digital berbasis UMKM, pertanian modern, energi terbarukan, logistik, dan layanan kesehatan. Sektor-sektor ini tak hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga memberi ruang mobilitas sosial. Peran UMKM sangat penting karena berada di titik temu antara inovasi dan akses.
Namun, potensi itu tak akan maksimal jika negara hanya berdiri di pinggir lapangan. Kita butuh kebijakan afirmatif: insentif fiskal, kemudahan regulasi, dan keberpihakan nyata pada pelaku kecil. UMKM tidak butuh janji, tapi butuh keberpihakan yang konkret: kemudahan modal, insentif pajak, dan proteksi pasar domestik.
Peta Ulang Kebijakan
Negara tidak bisa hanya responsif. Kita perlu memikirkan ulang seluruh ekosistem ketenagakerjaan: dari pendidikan, pelatihan, hingga skema perlindungan sosial. Program re-skilling dan up-skilling harus dikembangkan berbasis kebutuhan nyata industri. Balai Latihan Kerja (BLK) harus jadi pusat inovasi vokasi yang relevan.
Salah satu terobosan yang patut dipertimbangkan adalah Skills Development Fund (SDF). Skema pendanaan ini, jika dirancang baik, bisa membiayai pelatihan adaptif yang menjangkau kelompok rentan. Singapura sudah membuktikan efektivitasnya dalam memperkuat tenaga kerja.
Kita juga perlu memperluas perlindungan sosial. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tak boleh berhenti pada santunan. Ia harus jadi jembatan aktif menuju peluang kerja baru. Kebijakan industri pun harus bergeser dari ekspor murah ke inovasi dan penciptaan kerja berkelanjutan.
Kita bisa belajar dari Jerman pasca krisis 2008: menekan pengangguran lewat pelatihan vokasi, insentif perekrutan, dan kebijakan industri berbasis tenaga kerja terampil. Indonesia bisa, dan harus, menyesuaikan pendekatan ini dengan konteks lokal, melibatkan dunia usaha, dan menjadikannya agenda lintas kementerian.
Karena yang kita butuhkan bukan sekadar pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang memanusiakan. Masa depan kerja bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal martabat.
M. Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI; Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019; Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia.
(sls/M. Hanif Dhakiri)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini