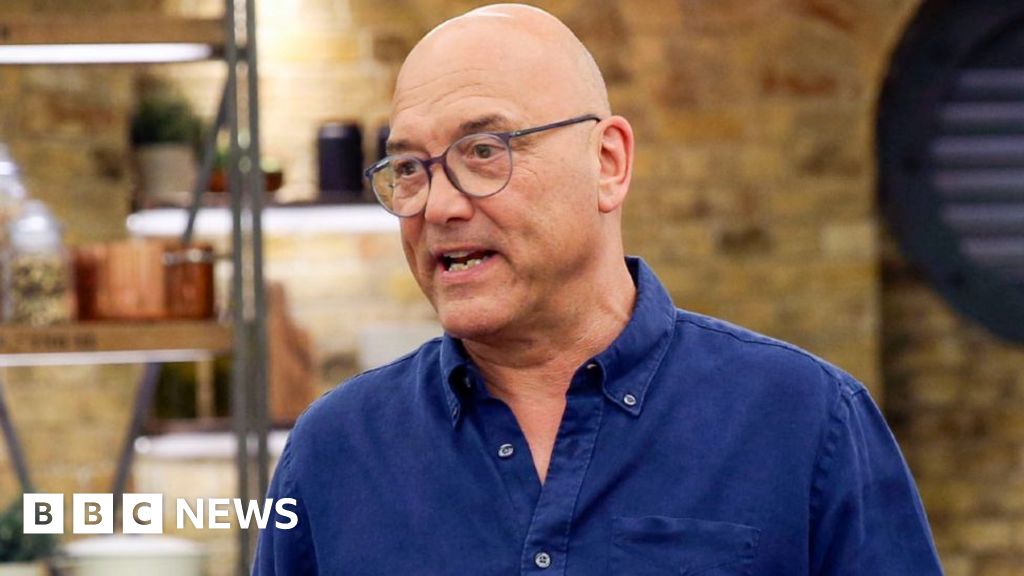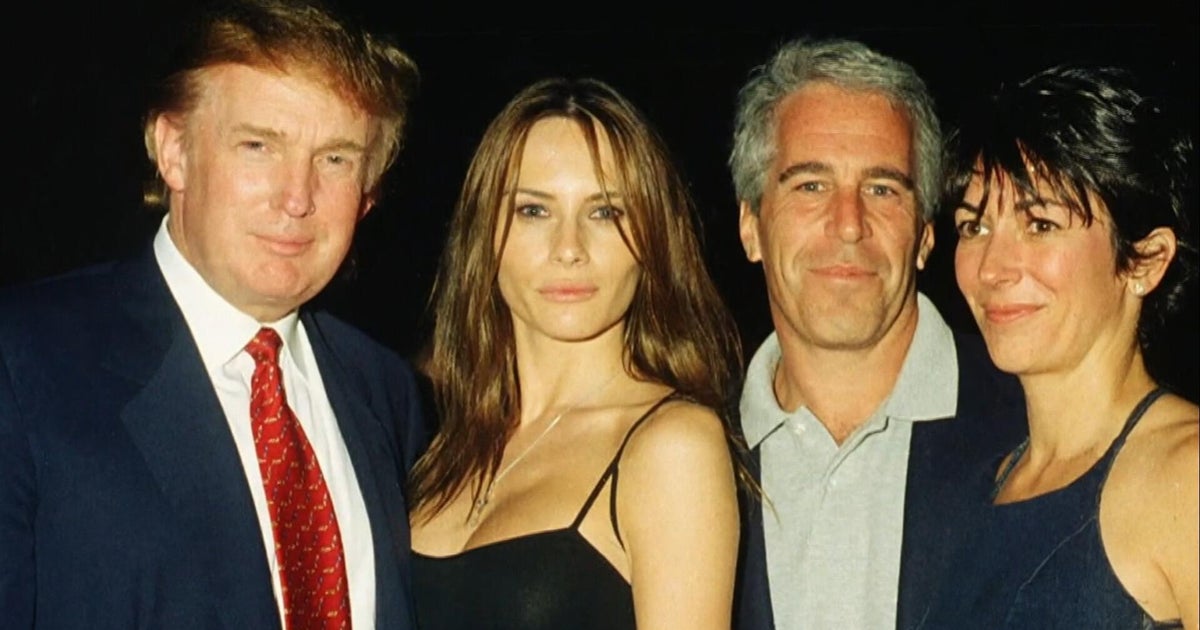Jakarta - Perempuan hari ini tak hanya diburu di jalanan. Ia diburu lewat likes, diserang lewat komentar, dan dipermalukan melalui layar. Pernyataan ini bukan sekadar metafora, tapi cerminan nyata dari kehidupan digital yang semakin brutal terhadap perempuan.
Kekerasan berbasis gender telah mengalami transformasi bentuk dalam era digital. Jika dahulu korban dibungkam melalui dominasi fisik atau kontrol sosial di ruang nyata, kini kekerasan menjelma lebih sunyi, tetapi jauh lebih luas dan cepat: di layar gawai, kolom komentar, pesan pribadi, hingga dalam konten deepfake yang diproduksi dan disebarkan tanpa izin.
Fenomena ini menandai tantangan baru dalam upaya perlindungan terhadap perempuan. Dunia digital, yang semula diharapkan menjadi ruang demokratis dan setara, justru berbalik menjadi arena baru bagi suburnya kekerasan berbasis gender (gender-based violence/GBV).
Kekerasan dalam Lintasan Teknologi
Laporan UN Women (2024) menyebut bahwa 85% perempuan korban kekerasan digital tidak melaporkan kasusnya. Mengapa? Karena mereka tidak percaya bahwa negara mampu melindungi mereka. Ketika seorang perempuan melaporkan akun pelaku pelecehan, atau bahkan revenge porn, yang terjadi bukan perlindungan, tapi sering perendahan—baik secara hukum maupun sosial.
Kasus revenge porn, doxing, dan pelecehan seksual via media sosial bukan lagi hal langka. Bahkan pada Pemilu 2024 lalu, 82% kandidat perempuan di Indonesia mengalami bentuk kekerasan berbasis gender, banyak di antaranya terjadi di ranah digital.
Belum lama ini, Korea Selatan diguncang oleh maraknya konten deepfake pornografi yang menggunakan wajah perempuan tanpa izin ke dalam video seksual. Fenomena ini tidak hanya merendahkan korban, tetapi menciptakan atmosfer ketakutan kolektif: bahwa tubuh dan identitas perempuan bisa dimanipulasi kapan saja, oleh siapa saja.
UU Tak Bergerak Secepat Internet
Indonesia memang sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU ITE. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan betapa hukum masih tertinggal jauh dari teknologi.
Aparat penegak hukum kerap gagap memahami terminologi dan konteks kekerasan digital. Tak jarang korban yang datang justru diintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan menyudutkan: "Kenapa kamu posting foto seperti itu?" atau "Kenapa tidak langsung blokir saja?"
Ini bukan hanya kegagalan hukum, tapi kegagalan empati.
Perempuan yang Dipaksa Diam
Ruang digital, dalam berbagai bentuknya, sejatinya menawarkan peluang besar untuk partisipasi perempuan dalam diskusi publik. Namun, gelombang kekerasan digital yang tak tertangani justru mendorong banyak perempuan untuk menarik diri dari ruang sosial. Tidak sedikit yang memilih berhenti berkarya, menyensor diri, atau bahkan mengalami gangguan psikologis serius akibat tekanan daring yang terus-menerus.
Fenomena ini mengancam keberlangsungan demokrasi yang sehat dan inklusif. Ketika perempuan takut bersuara, yang hilang bukan hanya satu opini, tetapi juga keberagaman perspektif yang esensial dalam kehidupan publik.
Merespons dengan Serius, Melindungi Secara Nyata
Agar kekerasan berbasis gender di ranah digital tidak semakin meluas dan normal, saya menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat segera dilakukan. Pertama, penguatan penegakan hukum berbasis korban. Kepolisian perlu memiliki unit khusus dengan kapasitas teknologi untuk menangani kekerasan digital, dengan pendekatan yang tidak menyalahkan korban dan memahami konteks GBV.
Kedua, standarisasi pelatihan aparat penegak hukum. Pelatihan nasional berbasis gender dan teknologi digital harus menjadi wajib bagi aparat hukum agar mereka memahami dinamika kekerasan di ruang maya.
Ketiga, literasi digital inklusif di lembaga pendidikan. Sekolah dan universitas perlu memasukkan materi literasi digital berbasis kesetaraan gender ke dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang sadar dan bertanggung jawab secara digital.
Keempat, kerja sama proaktif dengan platform digital. Pemerintah harus menjalin kemitraan aktif dengan platform seperti Meta, X, dan TikTok untuk menciptakan sistem moderasi dan pelaporan yang efektif serta transparan bagi pengguna yang menjadi korban kekerasan.
Lima, layanan pemulihan psikososial yang aksesibel. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperluas layanan konseling, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis bagi korban kekerasan digital, terutama di daerah yang selama ini terpinggirkan dari akses layanan.
Yang tak kalah penting: negara dan masyarakat harus berhenti menyalahkan korban. Karena kekerasan berbasis gender, di dunia nyata maupun digital, bukan tentang "mengapa ia tidak berhati-hati", tapi tentang mengapa pelaku merasa ia bisa lolos.
Kekerasan digital bukan sekadar efek samping dari perkembangan zaman. Ia adalah wajah baru dari patriarki yang memanfaatkan teknologi untuk menindas. Kita bisa memilih: menjadi penonton pasif dari luka yang viral ini, atau menjadi bagian dari perjuangan menciptakan ruang digital yang lebih adil, aman, dan manusiawi—terutama bagi mereka yang selama ini paling rentan disakiti.
Noralia Ulfa mahasiswi Pascasarjana Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pemerhati isu kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender, aktif di KOHATI
(mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini