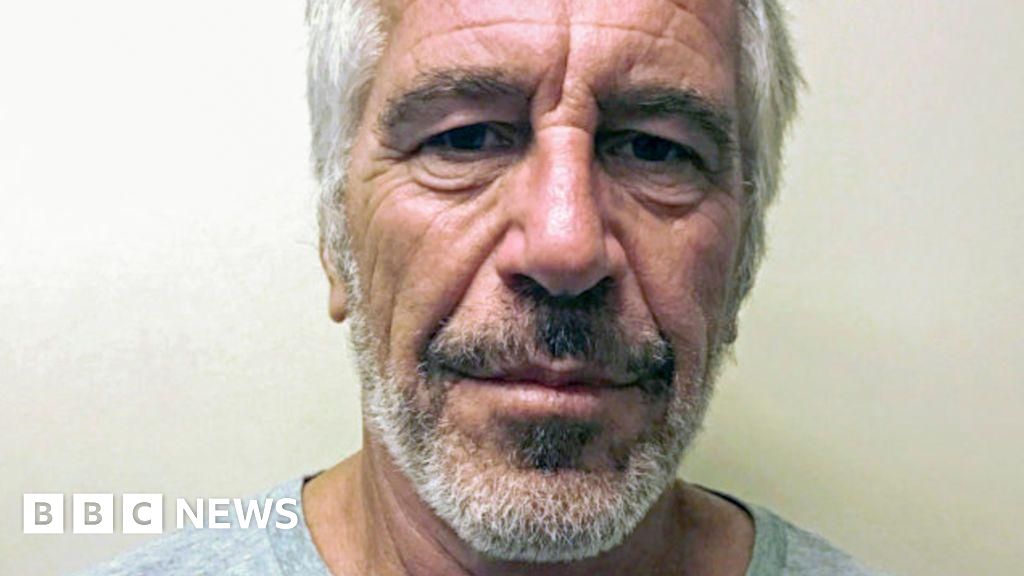Jakarta -
Lebaran. Kata yang begitu akrab di telinga, tapi pernahkah kita bertanya dari mana asalnya? Secara etimologis, ada beberapa teori menarik tentang asal-usul kata lebaran. Sebagian pakar bahasa mengaitkannya dengan kata dalam bahasa Jawa, lebar, yang berarti selesai atau usai—menunjukkan berakhirnya puasa Ramadan. Ada juga yang menghubungkannya dengan kata dalam bahasa Sunda, lebar, yang berarti luas atau lapang, selaras dengan suasana hati yang seharusnya kita rasakan saat Idulfitri: lapang dada, luas hati, dan penuh keikhlasan.
Namun, ada teori lain yang lebih unik. Beberapa filolog berpendapat bahwa lebaran berasal dari bahasa Tamil, lebar, yang berarti 'melimpah'—seperti halnya keberkahan yang melimpah di hari raya ini. Apapun asalnya, satu hal yang pasti: lebaran bukan hanya soal mudik, ketupat, atau THR. Ia adalah momentum untuk menguji seberapa lebar hati kita dalam memaafkan, menerima, dan melanjutkan hidup dengan lebih ringan.
Idulfitri: Kembali ke Fitrah atau Kembali ke Kebiasaan Lama?
Setiap kali Lebaran tiba, ada ungkapan yang selalu kita dengar: minal aidin wal faizin, yang sering diartikan sebagai "mohon maaf lahir dan batin." Padahal, makna aslinya lebih dalam—kembali menjadi orang yang menang. Tapi menang dari apa? Menang dari ego, dari hawa nafsu, dari dendam dan amarah yang menggerogoti hati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ramadan seharusnya mengajarkan kita untuk menahan diri, bukan hanya dari lapar dan dahaga, tapi juga dari amarah dan dendam. Namun, begitu bedug terakhir bertalu dan takbir berkumandang, apakah hati kita benar-benar menjadi lebih luas? Ataukah kita hanya kembali ke pola lama—mudik, makan enak, kumpul keluarga, lalu melanjutkan kehidupan seperti biasa tanpa ada perubahan hakiki?
Di sinilah letak tantangan terbesar Lebaran: menjadikannya bukan sekadar perayaan, tetapi transformasi diri.
Memaafkan: Semudah Ucapan atau Seluas Samudera?
Salah satu tradisi Lebaran yang paling sakral adalah saling memaafkan. Tapi mari kita jujur, apakah maaf yang kita ucapkan benar-benar datang dari hati? Atau sekadar basa-basi agar silaturahmi tetap lancar?
Memaafkan bukan hal mudah. Ada luka yang begitu dalam, ada pengkhianatan yang menyakitkan, ada janji-janji yang diingkari. Kadang kita berpikir, "Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan." Padahal, sejatinya memaafkan tidak berarti melupakan, tetapi menerima bahwa masa lalu tak bisa diubah dan memilih untuk tidak membiarkannya meracuni masa depan.
Memaafkan juga bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Ada batas antara memaafkan dan membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Namun, jika kita terus menggendong beban dendam, siapa yang sesungguhnya tersiksa? Kita sendiri.
Ibarat kapal yang hendak berlayar, semakin banyak beban yang dibawa, semakin sulit bergerak maju. Maka, melepaskan beban itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri—agar kita bisa berlayar lebih jauh, lebih bebas, lebih ringan.
Menerima Hidup: Antara Syukur dan Takdir
Selain memaafkan sesama, ada satu hal lagi yang sering terlupa dalam momen Lebaran: menerima keadaan hidup. Tak semua orang merayakan Lebaran dengan penuh kebahagiaan. Ada yang kehilangan orang terkasih, ada yang masih berjuang dalam ekonomi, ada yang merayakan di tanah rantau jauh dari keluarga.
Di sinilah ujian terbesar: bisakah kita menerima hidup sebagaimana adanya?
Menerima bukan berarti pasrah. Menerima adalah memahami bahwa hidup selalu datang dengan paket lengkap—kebahagiaan dan kesedihan, kemenangan dan kegagalan. Kita tak selalu bisa memilih jalan hidup yang kita inginkan, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalaninya.
Sebagaimana laut menerima gelombang tanpa mengeluh, begitulah seharusnya hati kita: luas, dalam, dan tenang.
Lebaran, Sebuah Refleksi
Jadi, apakah hati kita sudah seluas samudera?
Lebaran bukan hanya tentang baju baru dan ketupat. Ia adalah cermin bagi hati kita. Jika setelah sebulan penuh menahan diri kita masih enggan memaafkan, masih sulit menerima keadaan, dan masih menyimpan dendam, maka mungkin kita hanya menjalankan Ramadan sebatas ritual, bukan spiritual.
Mari jadikan Lebaran lebih dari sekadar perayaan tahunan. Jadikan ia titik balik, tempat kita benar-benar kembali ke fitrah—bukan hanya di bibir, tapi di hati.
Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang hatinya paling lapang.
Choirul Anam penulis tinggal di Bojonegoro
(mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini