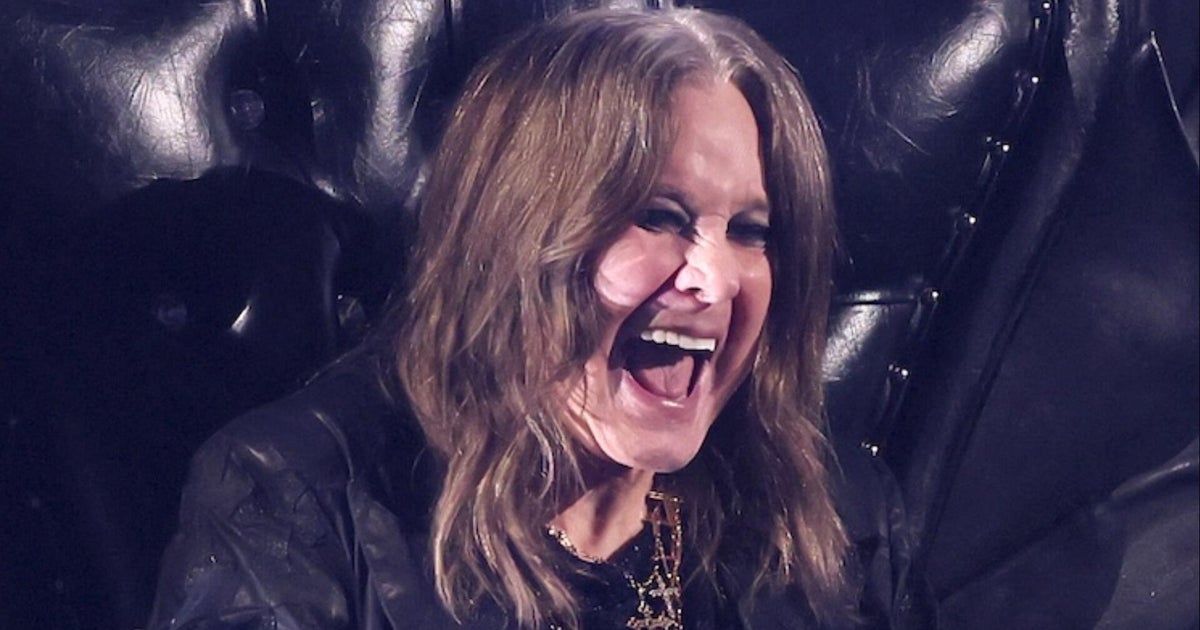Jakarta -
Saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan detail tarif impornya di Taman Mawar Gedung Putih pada 2 April, ia menjelaskan arti kata "resiprokal".
"Tarif resiprokal untuk negara-negara di seluruh dunia," katanya. "Resiprokal. Artinya: kalau mereka lakukan itu ke kita, kita lakukan hal yang sama ke mereka. Sangat sederhana. Tidak bisa lebih sederhana dari itu."
Pada hari itu, Trump mengumumkan dua set utama tarif — pajak 10% atas hampir semua impor AS dari semua negara, dan tambahan tarif "resiprokal" untuk berbagai negara, dengan tingkat yang berbeda-beda berdasarkan rumus pemerintah yang banyak dikritik, karena hampir hanya fokus pada defisit perdagangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump dan tim ekonominya berulang kali menyatakan bahwa tarif tersebut hanyalah pembalasan atas hambatan perdagangan yang dihadapi eksportir AS di negara-negara tersebut.
Rumus yang cacat
Namun, banyak ekonom, bank, dan lembaga keuangan menyebut bahwa tarif tersebut tidak benar-benar resiprokal, dan rumus yang digunakan tim Trump tidak masuk akal secara ekonomi.
"Rumus yang dia pakai itu omong kosong," kata Bill Reinsch, penasihat ekonomi senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), kepada DW.
"Semua orang tahu itu tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan klaim mereka, bahwa tarif tersebut akan bersifat resiprokal dan mempertimbangkan hambatan perdagangan nyata, termasuk tarif dan hambatan non-tarif. Tidak ada bukti bahwa mereka melakukan itu."
Doug Irwin, peneliti senior di Peterson Institute for International Economics dan pakar perdagangan global, juga menyatakan tarif tersebut jelas tidak resiprokal karena beberapa alasan.
Ia menjelaskan bahwa rumus dari Gedung Putih bahkan tidak mempertimbangkan tingkat tarif negara lain. Rumus itu hanya membagi defisit perdagangan barang AS dengan masing-masing negara terhadap total barang impor dari negara tersebut.
Tarif "resiprokal" bahkan diterapkan kepada negara-negara yang sudah punya perjanjian perdagangan bebas dengan AS seperti Chili, Australia, Peru, dan Korea Selatan.
"Padahal, hubungan dengan mereka sudah resiprokal. Kita tidak memungut tarif, mereka juga tidak," ujarnya. "Yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak memfokuskan pada hambatan perdagangan luar negeri, tapi pada defisit perdagangan. Itulah metrik yang mereka gunakan."
Jauh dari resiprokal
Data dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendukung pandangan para ekonom bahwa tarif "resiprokal" Trump justru jauh lebih tinggi daripada tarif negara lain terhadap AS.
Contoh paling mencolok adalah Cina. Beijing memang sering mengenakan tarif tinggi terhadap barang AS, tetapi tarif baru dari Washington kini membuat beban pada barang China jauh lebih berat dibanding sebaliknya.
Beberapa perkiraan menyebut tarif AS atas barang Cina kini mencapai 75%, dibandingkan 56% dari Cina terhadap AS. Bahkan, Trump mengancam akan menaikkan tarif tersebut sebesar 50% lagi, setelah Cina membalas dengan kenaikan 34%.
Contoh lain adalah Vietnam. AS kini akan mengenakan tarif sebesar 46% terhadap barang dari Vietnam, padahal menurut data WTO, Vietnam hanya mengenakan tarif rata-rata sederhana sebesar 9,4% dan tarif rata-rata tertimbang (berdasarkan porsi produk) sebesar 5,1% terhadap AS.
Contoh Vietnam jelas menunjukkan bahwa ini bukan soal resiprokal.
Hanoi langsung menawarkan untuk menghapus seluruh tarif atas impor AS, tapi penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro, menolak dengan mengatakan tawaran itu tidak cukup "karena yang penting adalah kecurangan non-tarif." Ia menuduh adanya barang Cina yang masuk melalui Vietnam dan penggunaan PPN sebagai bentuk "kecurangan."
Menurut Bill Reinsch, fakta bahwa Gedung Putih bahkan tidak mengukur hambatan tarif, apalagi hambatan non-tarif seperti yang dituduhkan Navarro, menunjukkan bahwa mereka "tidak benar-benar peduli dengan prinsip resiprokal."
"Itu cuma permainan. Jadi nanti akan ada negosiasi," ujar Reinsch.
Negosiasi dengan negara seperti Vietnam kemungkinan besar akan fokus pada neraca perdagangan, tetapi Irwin menyebut tujuan tersebut tidak masuk akal. "Sangat tidak mungkin AS bisa punya perdagangan seimbang atau surplus dengan Vietnam, mengingat struktur ekonomi masing-masing."
"Vietnam mendapat banyak investasi asing. Kita mengekspor komponen ke sana, lalu mereka mengekspor barang jadi ke kita," katanya. "Itu secara alami menciptakan defisit perdagangan."
Apa yang sebenarnya diinginkan Trump?
Bill Reinsch berpendapat bahwa selama lebih dari 40 tahun, Trump meyakini bahwa AS dirugikan dalam perdagangan global. Ia benar-benar ingin merombak sistem perdagangan dunia, namun kini berubah menjadi semacam "aksi balas dendam."
"Masalahnya adalah Trump hanya punya satu metrik, yaitu defisit perdagangan bilateral, dan satu alat, yaitu tarif," ujar Reinsch.
Menurut ekonom CSIS ini, pemerintahan Trump percaya bahwa defisit perdagangan itu tidak adil, dan hanya akan puas jika defisit tersebut hilang — meski tujuan itu tidak realistis dan bertentangan dengan logika ekonomi.
"Kalau kamu dengarkan Navarro, dan kadang Trump juga, nada dasarnya adalah: kalau kita punya defisit dengan negara A, pasti karena mereka curang, dan perdagangan harus seimbang," katanya. "Padahal itu tidak masuk akal."
Irwin setuju. Menurutnya, defisit perdagangan adalah perhatian utama Trump. "Bukan soal pendapatan, bukan soal keadilan atau resiprokal. Dia tidak suka defisit perdagangan. Dan sikap itu konsisten selama 40 tahun."
Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.
(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini