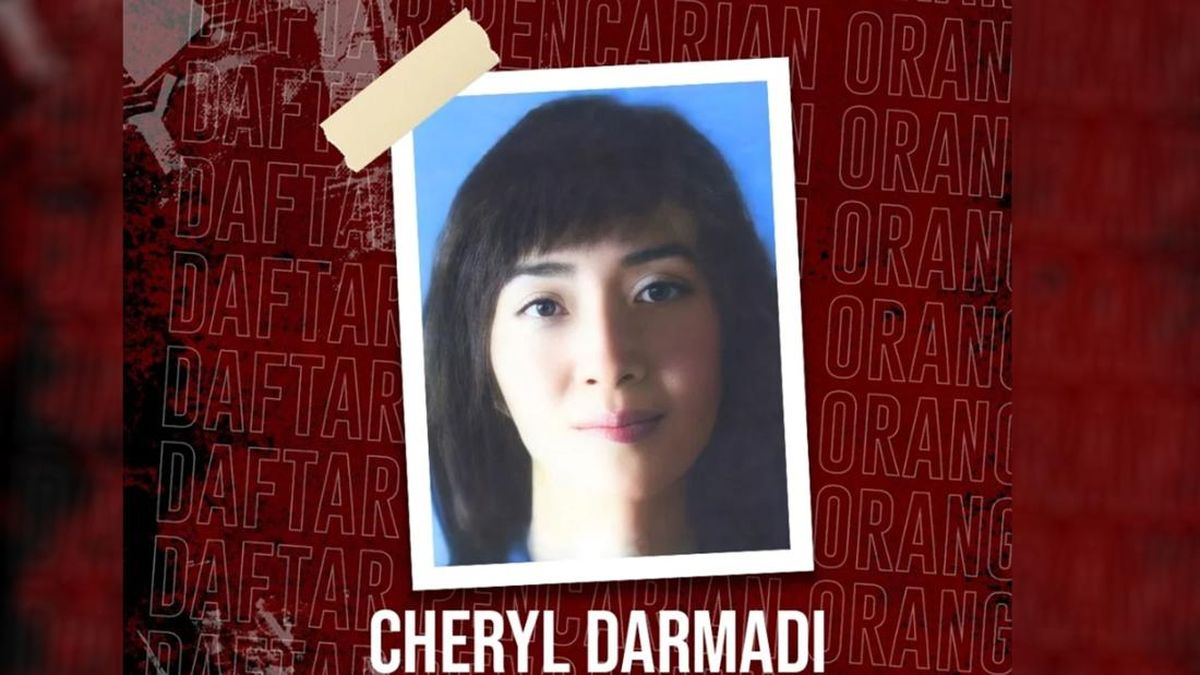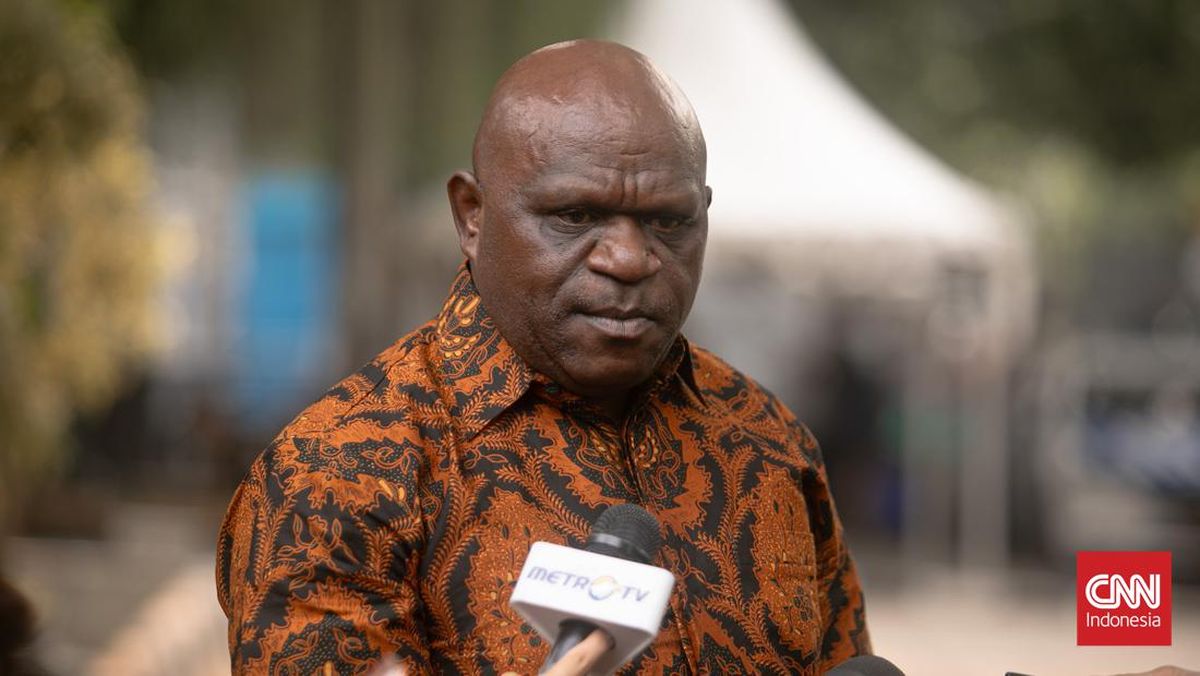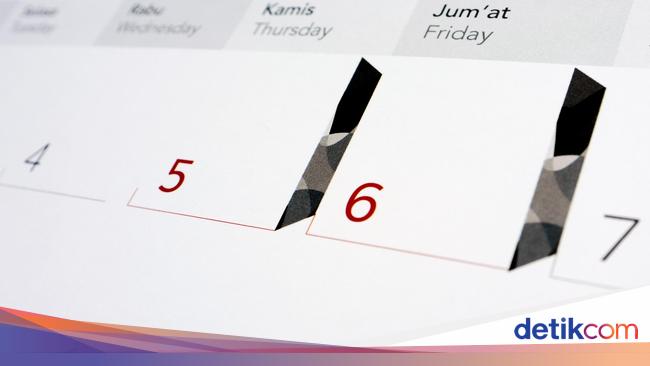Jakarta -
Sebuah video merekam amuk massa di tengah keteduhan alam Sukabumi, pada Jumat 27 Juni 2025. Dalam video yang tersebar di media sosial, tampak sekelompok warga menurunkan simbol salib, merusak kaca rumah, serta membalikkan meja dan kursi. Aksi tersebut sontak menuai kecaman luas dari berbagai kalangan. Peristiwa ini dengan cepat menyebar, menjadi potret buram intoleransi yang sekali lagi mencoreng wajah kebinekaan Indonesia. Namun, di balik rekaman yang memilukan itu, tersimpan sebuah narasi yang jauh lebih kompleks, sebuah benturan antara hak asasi yang paling fundamental dan keresahan komunal yang terakumulasi.
Insiden di Sukabumi bukan sekadar letupan amarah sesaat. Ia adalah puncak dari gunung es persoalan yang sering kali kita hindari untuk diskusikan secara mendalam: paradoks antara "kebebasan beragama" yang bersifat individual dan "kerukunan beragama" yang berorientasi komunal. Untuk membedahnya secara jernih, kita perlu menarik diri sejenak dari keberpihakan emosional dan menelusuri duduk perkaranya secara kronologis, memahami setiap perspektif, dan merefleksikannya dalam kerangka konstitusi serta realitas sosial kita.
Kronologi Sebuah Keresahan
Peristiwa yang terjadi tepatnya di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, bukanlah insiden yang terjadi tiba-tiba. Menurut berbagai sumber, termasuk Kepala Desa dan Ketua RT setempat, riak-riak di masyarakat sudah muncul sejak beberapa bulan sebelumnya. Vila milik Maria Veronica Nina, yang semula dikenal sebagai bekas pabrik pengolahan jagung dan jarang dihuni, mulai digunakan untuk kegiatan keagamaan sejak Februari 2025.
Bagi umat Kristen, kegiatan seperti ini dikenal sebagai retret. Berasal dari kata retreat yang berarti "menarik diri", retret spiritual adalah sebuah praktik menyisihkan waktu khusus untuk menjauh dari rutinitas duniawi dan memfokuskan diri pada hubungan dengan Tuhan. Ini adalah momen pendalaman iman yang esensial, sebuah ibadah yang khusyuk dan personal.
Namun, bagi sebagian warga Tangkil, kegiatan ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Keresahan mulai mengemuka ketika pada 30 April 2025, sebuah salib berukuran besar dipasang di area taman vila. Simbol keagamaan yang terlihat jelas ini menjadi titik awal protes warga. Laporan dan keluhan pun disampaikan secara berjenjang, mulai dari RT, hingga pemerintah desa. Mediasi tampaknya telah diupayakan.
Ketegangan memuncak pada 7 Juni 2025, saat sekitar 130 jemaat menggelar ibadah yang menurut laporan warga menggunakan pengeras suara pada waktu subuh. Bagi masyarakat yang mayoritas Muslim, suara nyanyian rohani yang bersamaan dengan waktu subuh itu asing dan mengusik ketenangan komunalnya. Peringatan dan mediasi yang telah dilakukan dirasa tidak membuahkan hasil, sepertinya masyarakat merasa diabaikan dalam ruang sosial yang mereka jaga. Hingga akhirnya kesabaran kolektif itu habis pada 27 Juni, yang berujung pada aksi pembubaran paksa dan perusakan.
Beragam pandangan pun mengemuka. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dengan tegas mengutuk peristiwa ini sebagai "bentuk nyata intoleransi" dan pelanggaran hak konstitusional. Bagi mereka, dan juga Center for Inter-Religious Studies and Traditions (CFIRST), beribadah adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat (non-derogable rights). Negara, dalam hal ini, dianggap gagal melindungi warganya.
Di sisi lain, MUI Sukabumi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukabumi meluruskan bahwa lokasi tersebut adalah vila, bukan gereja yang memiliki izin resmi sebagai rumah ibadah. Mereka menyoroti bahwa tindakan warga adalah akumulasi dari keresahan akibat kegiatan yang tidak mengindahkan teguran. Bahkan, Kesbangpol menyebut kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan, dengan kesediaan warga mengganti kerugian.
Hak Individual vs. Hak Komunal
Insiden Sukabumi secara telanjang mempertontonkan perdebatan fundamental dalam kehidupan berbangsa kita. Ada dua kerangka besar yang seolah saling berhadapan: kebebasan beragama sebagai hak individual dan kerukunan sebagai kepentingan komunal. Dalam praktiknya, dua nilai ini sering berbenturan.
Dalam perspektif Konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 28E dan 29, setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjaminan ini bersifat mutlak dan melekat pada setiap individu. Beribadah, sebagai esensi dari kebebasan beragama, adalah hak asasi manusia. Sehingga, secara normatif, setiap warga negara berhak menjalankan ibadahnya di mana pun di kolong langit wilayah Republik Indonesia. Melaksanakan ibadah, apalagi bersifat internal seperti retret, tidak semestinya memerlukan izin dari warga, terlebih jika tidak ada pelanggaran hukum positif. Izin mungkin diperlukan untuk mendirikan bangunan rumah ibadah (IMB), tapi bukan untuk aktivitas peribadatan itu sendiri.
Dari sudut pandang ini, apa yang terjadi di Tangkil adalah pelanggaran hukum dan wujud nyata intoleransi. Apapun alasannya, baik ketiadaan pemberitahuan, pemasangan salib, maupun penggunaan pengeras suara tindakan main hakim sendiri dengan merusak properti dan mengintimidasi para pelajar yang sedang retret tidak dapat dibenarkan. Kekerasan adalah jawaban yang keliru atas masalah sosial. Negara, melalui aparaturnya yang menurut laporan berada di lokasi, semestinya hadir untuk melindungi hak konstitusional para peserta retret, bukan membiarkan mereka menjadi korban persekusi.
Namun, dalam praktiknya, ekspresi hak individu sering kali berbenturan dengan nilai-nilai sosial masyarakat komunal. Kerukunan umat beragama yang dinarasikan pemerintah selama ini bukanlah sekadar konsep legalistik, melainkan nilai budaya yang berakar dari konsensus sosial. Ia menekankan pentingnya menjaga harmoni, menghindari gesekan, dan hidup berdampingan secara damai. Masyarakat perdesaan seperti di Tangkil umumnya memiliki karakter komunal yang kuat. Ikatan sosial, tradisi, dan norma-norma tak tertulis menjadi perekat utama keharmonisan. Dalam struktur masyarakat seperti ini, kemunculan "hal baru" atau "kelompok luar" yang membawa praktik berbeda sering kali dipersepsi sebagai potensi ancaman terhadap tatanan yang sudah mapan.
Sehingga yang penting dipahami, keresahan warga bukanlah bentuk kebencian apriori terhadap agama Kristen, tetapi karena mengalami disrupsi terhadap tatanan yang mereka pahami dan jaga. Faktanya, protes baru muncul setelah ada serangkaian tindakan yang dianggap mengabaikan eksistensi mereka sebagai komunitas. Pemasangan salib besar secara permanen di ruang yang semi-publik, kegiatan ibadah oleh "orang luar" tanpa komunikasi atau "kulonuwun" kepada tetua adat atau lingkungan, dan penggunaan pengeras suara pada waktu sensitif, semua ini secara akumulatif membangun persepsi adanya "invasi" simbolik ke dalam ruang hidup mereka. Ini adalah mekanisme "benteng diri" sebuah komunitas yang merasa keharmonisan dan ketenangan komunalnya terusik.
Perspektif antropologi sosial, masyarakat komunal cenderung mempertahankan stabilitas dan keharmonisan yang telah terbangun. Gangguan terhadap norma dan struktur yang mapan seringkali memicu resistensi, bukan semata karena kebencian, melainkan karena kegelisahan terhadap perubahan yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Kehadiran simbol agama besar dan aktivitas asing yang dilakukan oleh kelompok luar tanpa komunikasi dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap identitas lokal. Dalam narasi ini, sebenarnya yang diprotes bukanlah ibadahnya, melainkan cara dan etika dalam berinteraksi di ruang sosial bersama.
Mencari Jalan Tengah
Menyalahkan salah satu pihak secara mutlak hanya akan melanggengkan konflik. Menyatakan bahwa peserta retret 100% benar dan warga 100% salah (atau sebaliknya) adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya. Kasus seperti Sukabumi akan terus berulang di negeri yang majemuk ini jika kita gagal menemukan jalan tengah.
Di sinilah kita butuh menemukan jalan tengah dalam memandang setiap konflik yang melibatkan agama. Kita butuh lebih dari sekadar konsep kebebasan, kerukunan, bahkan moderasi beragama, kalaupun kini hadir konsep baru "beragama maslahat", sudah seharusnya hadir dalam tataran praksis sebagai sebuah praktik keagamaan yang tidak hanya damai, tetapi juga secara aktif mendatangkan kebaikan (maslahat) bagi lingkungan sekitarnya.
Penyelesaian yang adil harus mengakui validitas kedua kutub. Hak individual para pelajar untuk beribadah dalam retret harus dibela dan dijamin oleh negara. Tindakan perusakan adalah kriminal dan harus diproses secara hukum untuk memberikan efek jera. Namun, pada saat yang sama, hak komunal masyarakat Cidahu untuk merasa aman dan tidak terganggu di ruang hidupnya juga harus diakui dan dihormati.
Solusinya bersifat dua arah. Bagi kelompok yang hendak mengadakan kegiatan keagamaan di suatu wilayah, terutama jika mereka adalah pendatang, membangun komunikasi dan menunjukkan sensitivitas sosial adalah kunci. Ini bukan soal meminta izin untuk beribadah, melainkan soal etika bertetangga dan mengamalkan ajaran agama yang sejatinya mengajarkan kasih dan penghormatan kepada sesama. Menghindari penggunaan simbol yang provokatif di ruang bersama atau mengatur volume pengeras suara adalah wujud dari kearifan, bukan kekalahan.
Bagi masyarakat setempat, menyalurkan keresahan melalui dialog, mediasi, dan jalur hukum adalah jalan kedewasaan. Kekerasan dan main hakim sendiri hanya akan merusak citra komunitas itu sendiri dan mencederai tenun kebangsaan. Pemerintah, dari tingkat desa hingga pusat, harus bertindak sebagai fasilitator proaktif, bukan pemadam kebakaran yang reaktif.
Membumikan Toleransi
Artikel ini tidak hendak mencari siapa yang salah dan benar. Tetapi ingin mengajak kita semua untuk merenung bahwa merawat Indonesia tidak cukup hanya dengan mengagungkan slogan "kebebasan" dari menara gading konstitusi, tetapi juga harus turun membumi, mempraktikkan "kerukunan" dalam sapa dan interaksi sehari-hari. Menemukan harmoni antara hak individu dan hak komunal adalah pekerjaan rumah abadi bangsa ini, sebuah seni mengelola perbedaan yang menuntut kearifan, empati, dan kebesaran hati dari kita semua.
Insiden Sukabumi adalah cermin bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa ketika satu kelompok mengekspresikan hak konstitusionalnya secara penuh, tanpa koordinasi dan komunikasi yang memadai dengan lingkungan sosial, potensi konflik membesar. Sebaliknya, ketika komunitas mayoritas menuntut kontrol terhadap ekspresi keyakinan minoritas dengan alasan kerukunan, maka hak konstitusional minoritas terancam.
Menjaga kerukunan bukan berarti membatasi hak beragama. Sebaliknya, menegakkan kebebasan beragama tidak berarti mengabaikan sensitivitas sosial. Diperlukan ruang mediasi yang adil, edukasi lintas komunitas, serta peran aktif pemerintah yang tidak sekadar administratif. Jika tidak, intoleransi seperti di Tangkil akan terus berulang dalam rupa yang berbeda, menjadi luka diam yang menggerogoti fondasi persatuan bangsa.
Donald Qomaidiasyah Tungkagi. Dosen IAIN Gorontalo dan Wasekjen Bidang Kajian Stratejik Pimpinan Pusat GP Ansor
(imk/imk)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini