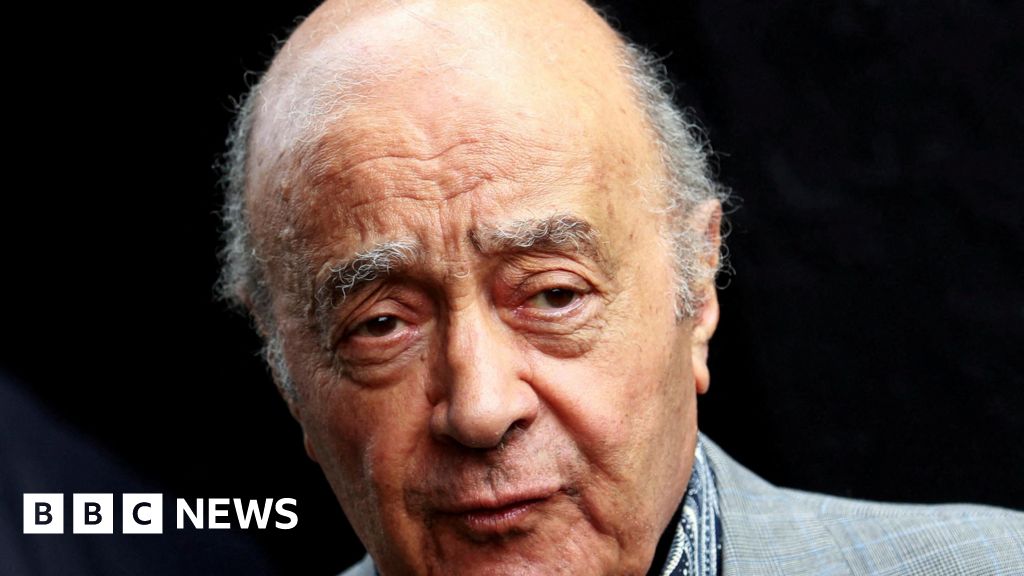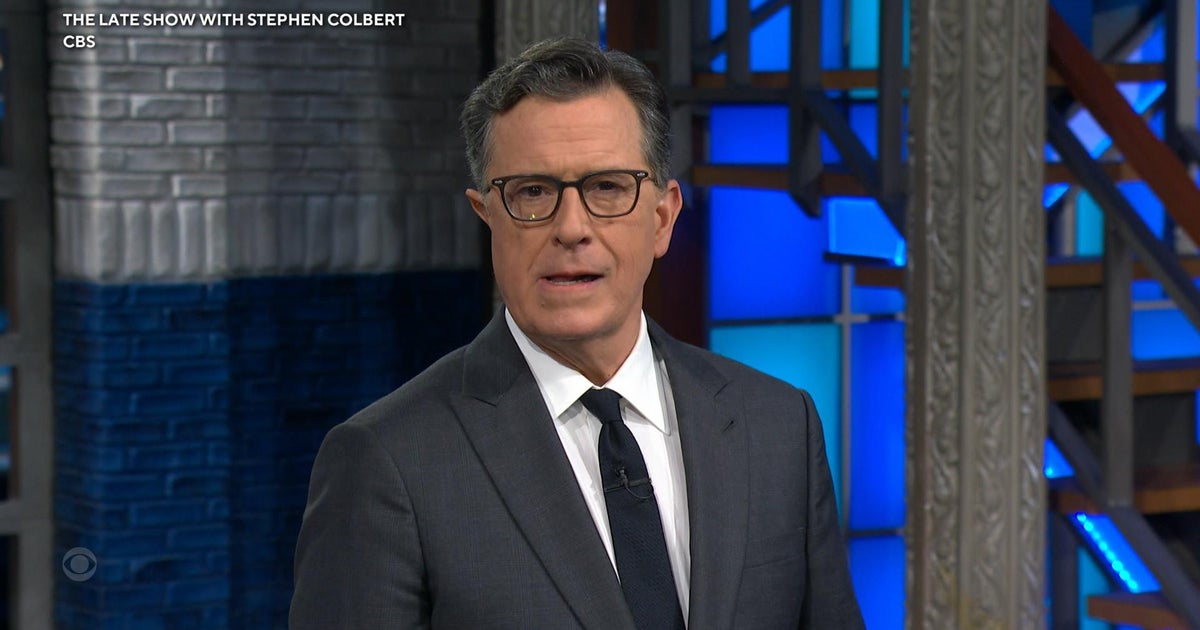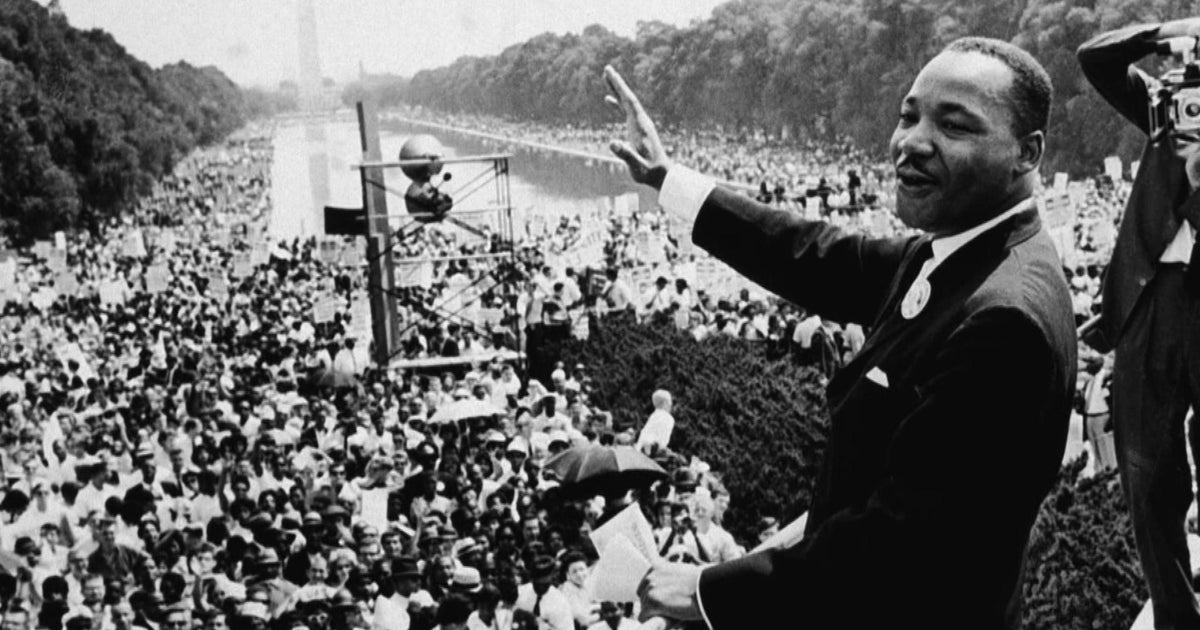Jakarta -
Di tengah lorong dingin sebuah swalayan di pinggiran kota di salah satu negara bagian Amerika Serikat (AS), seorang ibu berhenti di depan rak susu formula impor menatap label harga yang kini melonjak hampir dua kali lipat. Dengan ragu, ia menggenggam kaleng susu berlogo asing itu, berharap isinya cukup untuk menjaga tumbuh kembang anaknya yang sedang memasuki usia emas. Barangkali, ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan apa yang akan dialami oleh warga di negara Paman Sam jika pemerintahan Donald Trump resmi memberlakukan tarif resiprokal yang sebelumnya telah diumumkan pada 2 April 2025 yang lalu.
Sebagian dari kita mungkin mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan terjadinya perang dagang antarnegara, yang mana bukan merupakan istilah asing, karena juga pernah terjadi pada era pemerintah Donald Trump sebelumnya. Namun, siapa sebenarnya pihak yang harus membayar harga dari perang dagang itu sendiri? Apakah negara mitra dagang yang dihukum tarif? Produsen? Importir? Atau, justru konsumen akhir?
Tarif: Retorika vs Realitas
Kita tahu, tarif adalah semacam pajak yang dikenakan pada barang impor. Dalam konteks AS, kebijakan tarif resiprokal diberlakukan sebagai bentuk "balasan" terhadap negara-negara yang dianggap memberlakukan tarif tak adil terhadap produk AS. Dalam retorika politik, ini tampak seperti langkah heroik—seolah pemerintah AS tengah membela industri dalam negeri.
Namun di balik retorika itu, ada kenyataan yang lebih sunyi dan menyakitkan: beban tarif tidak ditanggung oleh negara asing yang menjadi mitra dagang, melainkan oleh pelaku usaha lokal, dan pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir.
Efek Domino: Kenaikan Harga, Ancaman Daya Beli, dan Inflasi
Ketika barang impor dikenai tarif tambahan, maka bukan tidak mungkin biaya bahan baku yang berasal dari luar negeri akan meningkat. Produsen di AS yang menggunakan bahan baku dari negara lain mungkin terpaksa menaikkan harga produk jadi.
Di sisi lain, distributor akan menerima barang dengan harga lebih mahal, yang kemudian akan membuat pengecer ikut menyesuaikan harga di rak-rak toko mereka. Pada akhirnya, konsumenlah yang harus terbebani untuk membayar lebih pada barang yang sama yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Tentu, hal ini bukan soal teori ekonomi yang abstrak. Ini adalah hal yang nyata!. Ini tentang harga gawai, obat-obatan, atau bahkan makanan dan minuman dalam kemasan yang mendadak meningkat signifikan.
Teori Cost Pass-Through menjelaskan bagaimana perusahaan menyesuaikan harga produknya ketika terjadi perubahan biaya (termasuk peningkatan tarif). Menurut teori ini, proses penyesuaian harga produk melibatkan "penerusan" kenaikan biaya ke pihak berikutnya dalam rantai pasokan, hingga akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir.
Sebagai ilustrasi, jika pemerintah AS mengenakan tarif yang lebih tinggi pada komoditas pertanian yang berasal dari sebuah negara di Asia, maka harga akhir dari makanan olahan buatan lokal yang menggunakannya sebagai bahan baku, dapat mengalami kenaikan yang signifikan pula. Bahkan kenaikan harga yang terjadi bukan hanya karena kenaikan tarif itu sendiri, tapi juga karena entitas-entitas di rantai pasokan yang berpotensi ikut menambahkan margin.
Dalam kondisi ini, tarif yang sejatinya ditujukan untuk "mendisiplinkan" negara-negara lain selaku mitra dagang, bukan tidak mungkin justru menjadi beban bagi daya beli warga AS sendiri. Efek lanjutan yang mungkin mengiringi kondisi ini adalah inflasi. Hal ini relevan karena ketika harga barang naik akibat pemberlakuan tarif resiprokal, maka harga-harga lain akan ikut terdorong.
Dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, warga kelas menengah ke bawah tentu yang akan paling merasakan dampaknya. Mereka dihadapkan pada pilihan yang tak mudah: tetap membeli barang yang sama dengan harga yang lebih mahal, atau beralih ke produk lain yang belum tentu setara kualitasnya.
Apa Imbasnya Jika Indonesia Membalas?
Menjadi hal yang semakin rumit jika kebijakan tarif resiprokal AS memicu respons serupa dari para mitra dagangnya. Tentu, hal ini akan memicu gejolak perdagangan internasional yang meluas menjadi konflik dagang global. Terlepas dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak merespons tarif resiprokal AS dengan strategi retaliasi (pembalasan), bisa saja Indonesia membalas AS dengan mengenakan tarif tambahan terhadap produk atau komponen asal AS.
Jika itu terjadi, maka hasilnya sama saja, pada akhirnya, konsumen di Indonesia yang akan menanggung akibatnya. Misalnya, produk pertanian AS yang biasa diimpor akan menjadi lebih mahal, dan produk lokal yang menggunakannya sebagai bahan mentah, akan mengalami lonjakan harga pula.
Contoh lain, obat-obatan dari perusahaan farmasi AS yang biasa dilanggan oleh konsumen di Indonesia mungkin akan jadi lebih terbatas ketersediaannya (karena permintaan berkurang akibat kenaikan tarif), sementara it, produsen lokal belum tentu siap mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan produk yang setara kualitasnya dalam waktu singkat.
Ketidakpastian dan Efisiensi Global yang Terancam
Dalam jangka panjang, tarif resiprokal menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan global. Dalam konteks ini, produsen enggan melakukan ekspansi atau investasi baru karena takut tarif bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung dari kebijakan politik. Akibatnya, dunia usaha menjadi gamang, dan konsumen lagi-lagi menanggung dampaknya. Harga jadi fluktuatif, pasokan dapat terganggu, dan inovasi pun melambat.
Ironi Patriotisme: Harga yang Dibayar di Lorong Sunyi
Kembali ke kisah ilustrasi seorang ibu di sebuah swalayan. Setelah beberapa saat berpikir, ibu itu akhirnya melangkah ke kasir dengan sekaleng susu untuk anaknya di tangan dan keraguan di wajahnya. Ia tahu, harga yang dibayarnya hari itu bukan sekadar angka di struk belanja—melainkan konsekuensi dari kebijakan yang dibuat jauh dari tempatnya berdiri, oleh orang-orang yang tak pernah mengantre di lorong kasir swalayan.
Ya, hal yang paling ironis dari semua ini adalah bagaimana tarif dibungkus dalam narasi patriotik "demi melindungi industri nasional," begitu kata mereka. Tapi mari kita berpikir kembali, ketika tarif membuat harga barang naik dan membatasi pilihan, apakah itu merupakan bentuk perlindungan? Atau, justru bentuk pengabaian terhadap kebutuhan rakyat sendiri?
Maka, jika kembali kepada pertanyaan "siapa sebenarnya yang membayar tarif itu?" maka jawabannya bukan diplomat di ruang perundingan, bukan negosiator dagang, dan bukan pula birokrat yang menyusun pasal demi pasal. Tapi dia, si ibu di lorong dingin itu. Dan, jangan lupa ia tidak sendiri; ia bersama jutaan konsumen kelas menengah ke bawah lainnya, yang setiap harinya hanya ingin memenuhi kebutuhan paling dasar: merawat, memberi makan, dan menjaga masa depan keluarganya.
Perang dagang mungkin diputuskan dari atas, tapi dampaknya paling dulu dirasakan dari bawah. Tepat di tempat paling sunyi: rak-rak swalayan dan dompet rakyat biasa.
Baziedy Aditya Darmawan Asisten Profesor di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia
(mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini