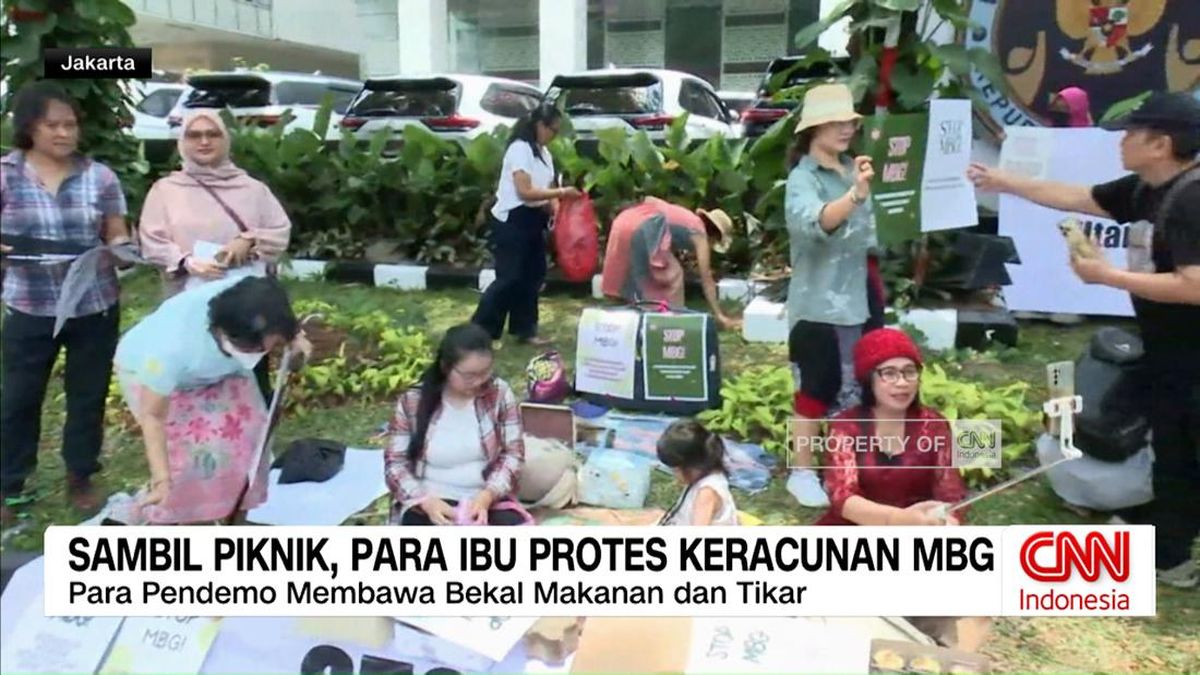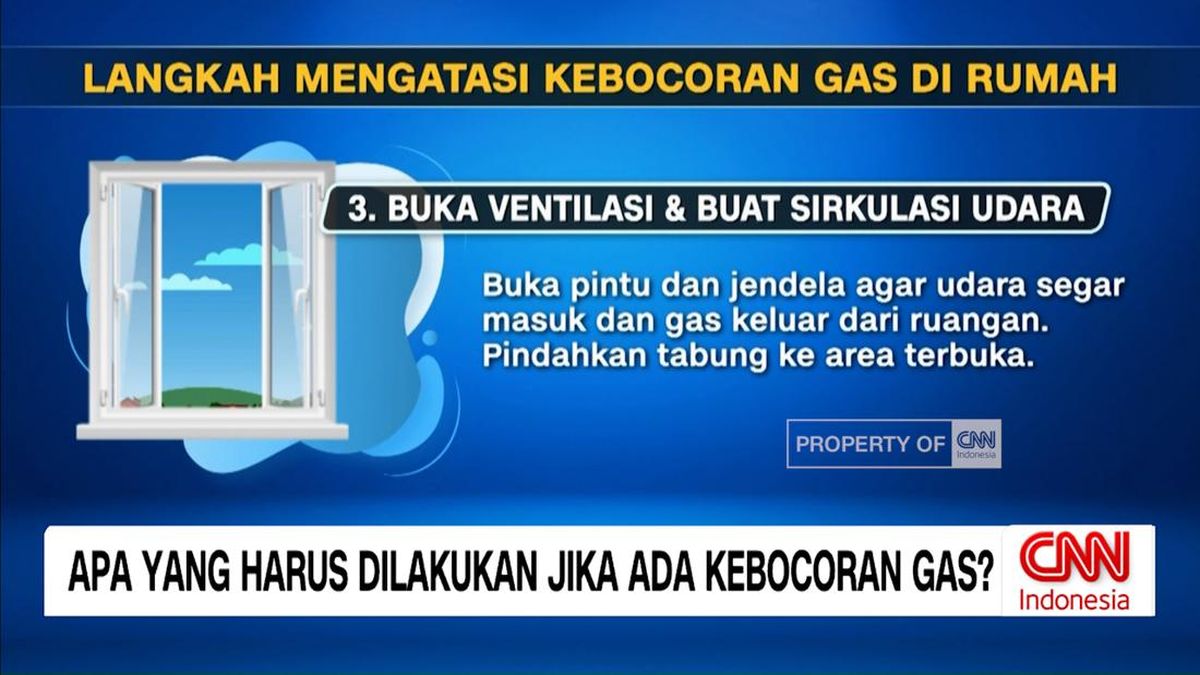Ikhtiar Anugrah Hidayat adalah profesional berpengalaman di bidang Manajemen Informasi dan Rekod, saat ini bekerja di PT Hutama Karya Infrastruktur. Lulusan Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Gadjah Mada, ia memiliki minat khusus pada corporate governance, risk management, dan ESG (Environmental, Social, and Governance). Dengan pengalaman mendalam dalam informasi dan dokumentasi serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data, Ikhtiar fokus pada penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan berbasis proyek.
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi
CNNIndonesia.comJakarta, CNN Indonesia --
Dalam beberapa waktu terakhir, perekonomian global tengah menghadapi tekanan yang tak terhindarkan. Termasuk ke Indonesia.
Ancaman resesi global terus membayangi dan kian diperparah dengan konflik geopolitik, inflasi berkepanjangan, serta perlambatan ekonomi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang.
World Bank dalam laporannya menyebutkan bahwa "Risiko resesi global meningkat akibat suku bunga yang tinggi, investasi yang lemah, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang." (World Bank Global Economic Prospects, Juni 2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan hasil survei 26 ekonom (Saputra, D, 2025) ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih lambat pada kuartal II/2025 yaitu sebesar 4,8 persen, dibandingkan kuartal I/2025 yang mencapai 4,87%. Perlambatan ini dipengaruhi tren pelemahan daya beli, tekanan inflasi pangan, serta turunnya ekspektasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Meski Indonesia secara teknis belum masuk ke resesi (dua kuartal pertumbuhan negatif), tekanan ekonomi yang terjadi belakangan ini membuat banyak keluarga kelas menengah harus "mundur" dan kembali fokus pada kebutuhan dasar.
Pergeseran konsumsi ini tidak berjalan linier, melainkan fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi mikro-ekonomi (kebutuhan rumah tangga).
In this Economy Era: Reflasi & Realita
Merespons kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa terlihat lebih fokus untuk meningkatkan ekonomi lewat belanja masyarakat.
Hal ini diperkuat dengan keputusan menyebarkan Rp200 triliun dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia kepada Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Rakyat).
Melalui rencana ini, masyarakat Indonesia khususnya kelas menengah dan bawah yang tergolong paling rentan terhadap guncangan ekonomi, perlu mengatur keuangan. Terutama karena kondisi ekonomi "reflasi" ini condong bisa mendorong inflasi karena belanja masyarakat meningkat.
Kelas menengah ini dianalogikan oleh pakar ekonomi Dr. Anisa Dwi Utami dari Institut Pertanian Bogor memiliki "duck syndrome", yaitu tampak tenang di permukaan, tapi berjuang keras di bawah tekanan finansial dan sosial, seperti inflasi, kesulitan ekonomi, dan ekspektasi tinggi dari media sosial.
Fenomena ini menunjukkan ada kesenjangan antara penampilan luar dan kondisi internal yang penuh tekanan bagi masyarakat, utamanya kelas menengah.
Dalam konteks ini, mulai muncul perilaku baru di kalangan masyarakat khususnya generasi milenial dan Gen Z, yaitu pengeluaran yang lebih bijak dan terencana (conscious spending). Bukan sekadar menahan konsumsi, tetapi mengalokasikan uang atau finansial sesuai nilai dan prioritas hidup.
Survei Jakpat (2023) menunjukkan bahwa 68% milenial Indonesia lebih memiliki pengeluaran yang bermakna, seperti kesehatan dan pengalaman dibanding barang mewah.
Tren ini dipicu oleh berbagai faktor: ketidakpastian ekonomi global, kenaikan biaya hidup, dan meningkatkan literasi keuangan.
Melek Finansial, Belanja Rasional
Kondisi ini tidak hanya mencerminkan tanggapan terhadap tekanan ekonomi, tapi juga menunjukkan kesadaran finansial yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat.
Conscious spending tidak identik dengan mengurangi pengeluaran secara drastis, melainkan menyesuaikan pola belanja dengan nilai dan tujuan finansial pribadi. Artinya, masyarakat terutama generasi saat ini semakin sadar bahwa uang yang mereka keluarkan harus sejalan dengan hal yang benar-benar menjadi prioritas bagi hidup mereka.
Peningkatan literasi keuangan, atau pengetahuan dan keterampilan yang esensial untuk mengelola keuangan pribadi secara efektif, juga menjadi faktor penting. Semakin seseorang memahami cara mengelola keuangan, semakin besar kemungkinannya untuk menerapkan pola belanja yang bijak dan terencana.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan ada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang turut mendorong munculnya perilaku belanja yang lebih bijak.
Riset OJK Tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional meningkat signifikan dari 38,03% pada 2019 menjadi 49,68% pada 2022. Kenaikan ini berkorelasi dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam merencanakan keuangan secara lebih bijak.
Dari Budgeting ke Wealth Building
Pengetahuan literasi dasar seperti pada penerapan konsep budgeting 50/30/20 (50% kebutuhan pokok, 30% keinginan, 20% tabungan/investasi) sangat membantu penerapan conscious spending.
Artinya, masyarakat tidak berarti menghapus total pengeluaran non-primer, namun tetap mengalokasikan dana hiburan secara terencana sebagai bagian dari pola hidup (life style). Salah satu prinsip yang dapat dijadikan referensi untuk mengatur keuangan sehari-hari:
Setelah memahami prinsip dasar metode 50/30/20 dan pengelolaan anggaran bulanan, terdapat pendekatan lanjutan membangun ketahanan finansial jangka panjang. Salah satu pendekatan yang semakin populer adalah Spending Cap & Wealth Ladder.
Konsep ini mengacu pada gaya hidup hemat (frugal living) dan investasi bertahap. Dalam framework ini, individu menetapkan spending cap, batas pengeluaran hidup yang tetap meski pendapatan meningkat.
Tujuannya untuk mencegah inflasi gaya hidup (lifestyle inflation). Selisih dari penghasilan yang tidak digunakan untuk konsumsi, kemudian dialokasikan mengikuti tangga prioritas keuangan (wealth ladder), yaitu:
- Dana darurat minimal 3-6 bulan biaya hidup,
- Pelunasan utang konsumtif, dan
- Investasi dengan barbell strategy: alokasi aset rendah risiko dengan high upside secara seimbang untuk menciptakan ketahanan finansial jangka panjang (Taleb, Antifragile, 2012).
Contoh penerapan konsep oleh seorang individu dengan penghasilan Rp10 juta per bulan:
Konsep spending cap and wealth ladder memperkenalkan pendekatan jangka panjang yang menekankan gaya hidup hemat dan alokasi strategis.
Dalam konteks ini, literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan, tapi alat yang dapat membentuk perilaku finansial seseorang, mulai dari perencanaan keuangan harian hingga strategi investasi jangka panjang.
Literasi keuangan menjadi penghubung antara penghasilan saat ini dengan ketahanan finansial masa depan.
Dengan pemahaman literasi keuangan yang baik, seseorang menjadi lebih sadar terhadap prioritas jangka pendek hingga panjang, risiko konsumtif dan pentingnya dana darurat, dan strategi investasi sesuai dengan risiko.
Tiga poin penting dari literasi keuangan terhadap pengambilan keputusan: Pertama keputusan pengeluaran dan investasi dibuat berdasarkan alokasi yang jelas dan terencana. Kedua, individu siap menghadapi kondisi darurat tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Ketiga, pendapatan tidak hanya sebagai konsumsi, tetapi juga membangun aset dan ketahanan finansial.
Antara Konsumsi dengan Kesadaran Finansial
Perlambatan ekonomi global dan nasional telah menekan daya beli masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi.
Pemerintah Indonesia menanggapi reflasi melalui stimulus fiskal untuk mendorong minat belanja masyarakat. Namun, kebijakan ini akan efektif apabila disertai dengan kesiapan psikologis dan finansial masyarakat secara bijak.
Di sinilah konsep conscious spending muncul sebagai respons adaptif kelas menengah, yakni pola belanja yang selaras dengan nilai dan prioritas hidup, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sosial.
Tanpa pemahaman atau literasi keuangan tentang budgeting, dana darurat, dan strategi investasi masyarakat rentan terjebak dalam lifestyle inflation ketika gaya hidup tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan.
Dengan demikian, stimulus ekonomi harus sejalan dengan intervensi keuangan yang lebih realistis. Tujuannya bukan hanya meningkatkan konsumsi, tetapi membentuk masyarakat yang dapat mengelola keuangan secara bijak, membangun aset produktif, dan menciptakan gaya hidup dengan realitas ekonomi.
Melalui cara ini, kelas menengah dapat bertahan di tengah tekanan global, tetapi juga berpeluang naik kelas secara struktural dan berkelanjutan.
Artikel opini ini dituliskan bersama Danish F. Adinata (Supply Chain Transformation - L'Oréal) dan M. Akmal Daffari (Customer Business Development - Paragon Corp).(vws/vws)

 4 hours ago
5
4 hours ago
5