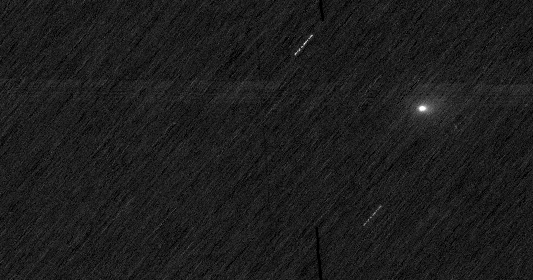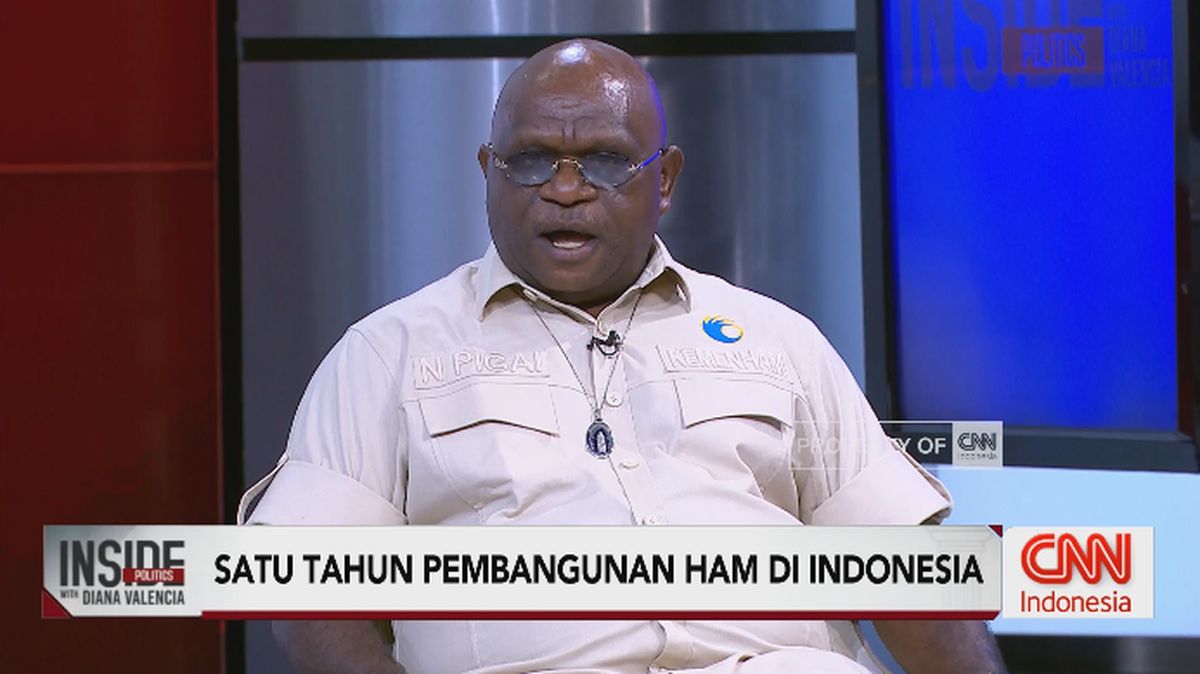Jakarta -
"Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen kekuasaan yang mengatur horizon makna." — Michel Foucault
Dalam dunia yang semakin kompleks, bahasa tak lagi dapat dibaca sebagai jendela transparan menuju realitas. Ia adalah arena pertarungan, tempat di mana makna dibentuk, direkayasa, dan diperebutkan. Dalam lanskap ini, munculnya istilah seperti "Wahabi lingkungan"—sebuah frasa kontroversial yang sempat dilontarkan oleh Gus Ulil Abshar Abdalla—menjadi sangat menarik untuk dianalisis. Istilah ini bukan sekadar permainan kata, melainkan penanda dari dinamika wacana yang menempatkan gerakan lingkungan dalam posisi ambivalen: antara perjuangan moral dan tuduhan ekstremisme.
Istilah "Wahabi lingkungan" menandai sekelompok orang yang dianggap terlalu ketat, terlalu dogmatis, atau terlalu tidak kompromistis dalam memperjuangkan agenda ekologis. Namun, alih-alih sekadar menyebut pendekatan yang tidak fleksibel, frasa ini menyelipkan ironi: ia menggunakan kerangka religius untuk menilai perjuangan lingkungan, seolah menyamakan kepedulian ekologis dengan semangat keagamaan yang keras. Inilah cara kerja bahasa yang penuh jebakan: ia menormalisasi bias, menutupi struktur kekuasaan di baliknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekologi Bahasa dan Delegitimasi Simbolik
Dalam kerangka Foucaultian, kita memahami bahwa ujaran adalah bentuk kekuasaan. Bahasa tidak hanya mencerminkan dunia, melainkan menyusunnya. Bahasa mengatur siapa yang berhak berbicara, dari posisi mana, dan dengan legitimasi apa. Maka, penyematan istilah "Wahabi lingkungan" adalah taktik diskursif yang tak sekadar mendeskripsikan, tetapi sekaligus menegasikan dan menaklukkan.
Di sinilah berlaku apa yang dapat kita sebut sebagai "ekologi bahasa"—relasi antara tanda-tanda yang saling mempengaruhi dalam ekosistem makna sosial. Dalam ekosistem ini, istilah seperti "Wahabi lingkungan" berfungsi seperti spesies invasif: ia mendominasi, menekan spesies makna lain, dan menggantikan keragaman tafsir dengan satu citra yang simplistik dan problematik. Gerakan lingkungan yang bersifat kritis dan mendalam pun terancam disederhanakan menjadi semata gaya hidup puritan yang tak toleran.
Jean Baudrillard pernah memperingatkan bahwa dalam masyarakat simulasi, tanda menjadi lebih penting dari kenyataan. Aktivisme lingkungan dalam kerangka ini tidak lagi dinilai berdasarkan efek nyatanya terhadap perubahan struktural, tetapi berdasarkan estetika perilaku: siapa yang "terlalu keras", siapa yang cukup moderat, siapa yang tampak ramah di media sosial. Dalam dunia semacam ini, militansi ekologi mudah dicitrakan sebagai fanatisme, bukan sebagai bentuk kesadaran kritis.
Dengan kata lain, "Wahabi lingkungan" adalah penanda kosong—ia tidak menunjuk pada entitas konkret, melainkan menciptakan konstruksi imajiner yang berfungsi memarjinalkan suara-suara yang terlalu menuntut, terlalu jujur, atau terlalu radikal untuk diterima dalam politik konsensus.
Militansi Ekologis dan Kritik terhadap Normalitas
Tuduhan terhadap militansi lingkungan sering kali berangkat dari standar moralitas yang dibentuk oleh sistem dominan: sistem yang masih menganggap konsumsi berlebih sebagai hak, pembangunan tak terbatas sebagai tujuan, dan kenyamanan individual sebagai ukuran rasionalitas. Dalam situasi ekologis global yang kian genting, di mana krisis iklim melanda, ekosistem runtuh, dan sumber daya semakin langka, suara-suara yang menyerukan perubahan radikal bukan hanya dibutuhkan—ia mendesak.
Gerakan lingkungan yang keras bukanlah ekspresi kekerasan, melainkan bentuk pertahanan terhadap kekerasan sistemik yang telah berlangsung lama: eksploitasi alam, perusakan habitat, ketimpangan distribusi sumber daya. Dalam konteks ini, militansi bukan lawan dari rasionalitas, melainkan wujud etika tanggung jawab yang sadar bahwa kompromi terhadap krisis hanya akan memperpanjang penderitaan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Félix Guattari, perjuangan ekologis tidak dapat dipisahkan dari perjuangan sosial dan mental. Ia menyebut konsep "ekosofi" sebagai cara pandang lintas dimensi: lingkungan, relasi sosial, dan kehidupan psikis. Dalam perspektif ini, militansi ekologis adalah upaya membangun harmoni baru antara manusia dan dunia—harmoni yang tidak bisa dibangun dengan bahasa yang memusuhi komitmen total.
Ironisnya, justru bahasa lembut dan narasi kompromistis yang sering kali melanggengkan status quo. Bahasa yang menenangkan tetapi kosong secara politis; bahasa yang menyarankan kesabaran di tengah kehancuran. Sementara itu, suara yang nyaring, yang tidak kompromistis terhadap plastik, batu bara, atau industri ekstraktif, dituduh tidak inklusif. Ini adalah bentuk kekerasan simbolik yang bekerja secara halus, tetapi efektif.
Ketika seseorang memilih untuk hidup tanpa plastik, menolak fast fashion, atau mengkritik konsumerisme budaya urban, pilihan itu sering kali dianggap "berlebihan". Namun sesungguhnya, tindakan tersebut adalah bentuk protes diam terhadap sistem yang menjadikan bumi sebagai komoditas. Mereka bukan sekadar bertindak demi citra diri, tetapi karena memahami bahwa waktu bagi bumi semakin menipis.
Membangun Ruang Diskursif yang Adil
Kita membutuhkan cara baru untuk berbicara tentang aktivisme lingkungan—cara yang lebih adil, lebih reflektif, dan lebih terbuka terhadap keberagaman ekspresi. Alih-alih terjebak dalam dikotomi "moderat vs radikal", kita perlu mengakui bahwa dalam perjuangan ekologis, berbagai pendekatan bisa berjalan berdampingan. Yang konsiliatif, yang konfrontatif, yang simbolik, dan yang praktikal.
Bahasa memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan baru, tetapi juga bisa membatasi. Ketika istilah "Wahabi lingkungan" dipakai secara sembrono, ia mengerdilkan medan perjuangan menjadi masalah gaya bicara. Kita lupa bahwa di balik kebisingan wacana, ada hutan yang terbakar, sungai yang tercemar, dan masyarakat adat yang digusur.
Sudah saatnya kita berhenti menilai gerakan berdasarkan narasi popularitas atau kenyamanan semantik. Saat dunia menghadapi krisis eksistensial, kita tidak membutuhkan aktivisme yang ramah kamera. Kita membutuhkan keberanian moral yang tidak malu untuk tampil tegas, bahkan jika harus dituduh ekstrem.
Karena sejatinya, bumi tidak membutuhkan aktivis yang populer. Ia membutuhkan mereka yang bersetia, yang berani membela tanpa syarat, yang tak gentar dicap fanatik demi menyelamatkan kehidupan itu sendiri.
Muhammad Ghufron. Alumnus Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(imk/imk)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini