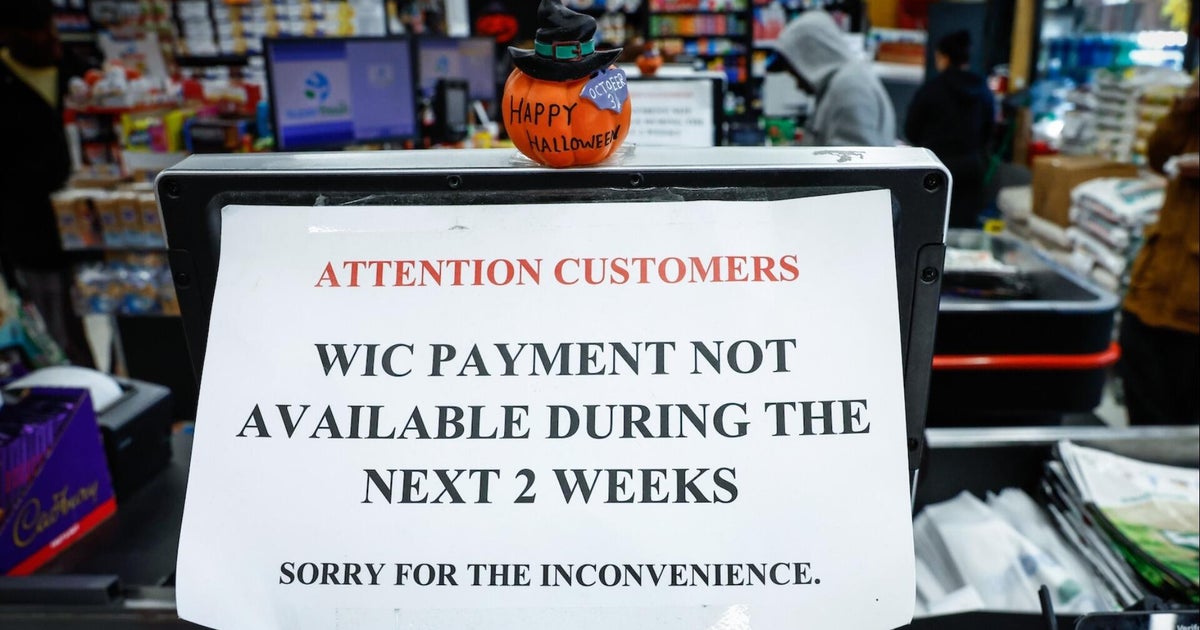Jakarta -
Tragedi yang menimpa seorang wisatawan asal Brasil di Gunung Rinjani baru-baru ini telah mengguncang publik dan mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Wisatawan asing tersebut ditemukan meninggal dunia setelah mengalami kelelahan dan tidak mendapatkan pertolongan darurat secara cepat di jalur pendakian. Kejadian ini tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga menjadi pengingat keras bahwa sistem keselamatan di kawasan konservasi kita masih jauh dari kata siap. Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, kegagalan negara menjamin keselamatan satu nyawa saja dapat berdampak besar terhadap kepercayaan global terhadap destinasi wisata kita.
Gunung Rinjani tidak hanya menjulang megah sebagai ikon pariwisata dan konservasi di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga sebagai salah satu penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dari sektor taman nasional di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp22,5 miliar dari aktivitas pendakian dan non-pendakian. Angka ini mengindikasikan lonjakan minat masyarakat terhadap wisata alam berbasis petualangan dan spiritualitas ekologis.
Berdasarkan data resmi Balai TNGR, jumlah pendaki Rinjani sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 189.091 orang. Dari jumlah tersebut, pengunjung domestik mendominasi dengan 141.302 orang atau sekitar 74,73%, sementara pendaki mancanegara mencapai 47.789 orang atau 25,27%. Ini menunjukkan bahwa Rinjani tidak hanya menjadi magnet bagi wisatawan lokal yang ingin mendaki gunung tertinggi kedua di Indonesia ini, tetapi juga telah menembus pasar internasional sebagai destinasi unggulan eco-adventure.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, pencapaian angka tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan para pendaki dan menjaga kelestarian kawasan. Rinjani bukan sekadar tujuan wisata, tetapi juga kawasan konservasi yang memiliki ekosistem unik, rentan, dan membutuhkan pengelolaan yang profesional serta berkelanjutan. Sayangnya, pengalaman lapangan menunjukkan masih adanya kekosongan sistem penyelamatan dan perlindungan yang memadai. Dalam konteks ini, tulisan ini hadir untuk menyerukan bahwa momentum penerimaan PNBP yang tinggi harus dibarengi dengan prioritas pada aspek keselamatan dan konservasi.
Investasi Keselamatan, Bukan Beban
Dalam dunia konservasi modern, keselamatan pengunjung bukanlah beban, melainkan bentuk investasi. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi setiap individu yang beraktivitas di kawasan konservasi. Dengan perolehan Rp22,5 miliar dari aktivitas wisata di Rinjani, seharusnya tidak sulit bagi TNGR dan mitra kementeriannya untuk mengalokasikan sebagian anggaran demi pembentukan dua titik penyelamatan utama: gudang rescue di Pelawangan Sembalun dan pusat rescue di Rinjani Trekking Centre (RTC) Sembalun.
Gudang rescue di Pelawangan Sembalun setidaknya harus dilengkapi alat evakuasi vertikal sejauh 500 meter untuk menanggulangi insiden jatuh atau kelelahan ekstrem di jalur puncak. Selain itu, diperlukan charging station berbasis solar panel sebagai sumber daya mandiri untuk mengisi ulang baterai perangkat komunikasi atau drone pencari. Di sisi lain, RTC sebagai titik awal pendakian dapat difungsikan sebagai pusat kontrol keselamatan dengan dukungan teknologi seperti cargo delivery drone dan thermal drone yang dapat beroperasi pada malam hari atau kondisi minim visibilitas.
Kesiapsiagaan selama 24 jam mutlak dibutuhkan, terutama pada musim ramai pendakian. Banyak insiden ringan hingga berat yang tidak tertangani secara cepat akibat keterbatasan akses dan ketiadaan tim rescue permanen. Negara tidak boleh menunggu korban jatuh terlebih dahulu untuk bertindak. Investasi pada keselamatan adalah prasyarat mutlak dari pariwisata yang berkelanjutan.
Rambu, Edukasi, dan Disiplin Pengelolaan
Salah satu titik kritis pendakian Gunung Rinjani adalah jalur menuju puncak, terutama di atas Pelawangan Sembalun. Medan yang terjal, berdebu, dan licin menjadikan jalur ini rentan terhadap kecelakaan, baik karena faktor kelelahan, misorientasi, maupun cuaca ekstrem. Ironisnya, di titik-titik tersebut, rambu keselamatan nyaris tidak ditemukan. Padahal, keberadaan rambu visual, peringatan arah angin, dan zona rawan longsor dapat menyelamatkan nyawa.
Lebih jauh lagi, edukasi kepada pendaki sejak titik awal pendakian merupakan kebutuhan yang mendesak. Tidak semua pendaki memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang survival di gunung, terlebih lagi Rinjani bukan gunung yang dapat dipandang remeh. Dengan pendaki domestik mencapai lebih dari 74% dari total kunjungan, penyediaan pos edukasi dan video briefing di shelter utama menjadi sangat penting.
Penegakan aturan terhadap operator trekking juga perlu diperketat. Saat ini masih banyak operator yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan konservasi. Sertifikasi pemandu, batas maksimal pendaki per hari, dan kepatuhan terhadap jalur resmi harus ditegakkan tanpa kompromi. Di sinilah peran pengelola TNGR perlu ditingkatkan, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator keselamatan dan pembina komunitas trekking.
PNBP untuk Siapa?
Gunung Rinjani merupakan salah satu penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dari sektor taman nasional. Pada tahun 2024, PNBP yang dihasilkan dari aktivitas pendakian Gunung Rinjani mencapai Rp 22,5 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar hampir 80% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp14,7 miliar. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh pemberlakuan tarif baru yang naik hingga 100% sejak 30 Oktober 2024, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024.
Selain PNBP, aktivitas pendakian di kawasan Rinjani juga memberikan dampak ekonomi berganda (multiplier effect) yang besar bagi masyarakat lokal. Total pendapatan yang berputar di masyarakat dari seluruh aktivitas pendakian diperkirakan mencapai Rp109 miliar pada tahun 2024. Kontribusi ekonomi ini tersebar di berbagai sektor, termasuk pendapatan operator wisata (Rp21,8 miliar), jasa pemandu (Rp13,3 miliar), jasa porter (Rp30,9 miliar), serta penyedia jasa makanan dan minuman (Rp8,94 juta), transportasi (Rp2,56 juta), penginapan (Rp3,84 juta), persewaan peralatan pendakian (Rp3,84 juta), dan asuransi (Rp1,62 juta).
Aktivitas pariwisata Rinjani juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar, dengan total 50.621 orang terlibat. Porter menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar dengan 36.425 orang, diikuti oleh pemandu sebanyak 13.060 orang, dan operator wisata sebanyak 1.136 orang.
Kesenjangan yang mencolok antara PNBP sebesar Rp22,5 miliar dan total nilai ekonomi yang berputar di masyarakat sebesar Rp109 miliar menunjukkan bahwa PNBP hanya sebagian kecil dari nilai ekonomi Rinjani secara keseluruhan. Ini memperkuat argumen bahwa PNBP harus dialokasikan secara transparan dan berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan keselamatan. Jika PNBP sebagian besar digunakan untuk keperluan administratif dan operasional dasar tanpa investasi yang memadai dalam infrastruktur keselamatan dan konservasi, hal ini menimbulkan dilema moral dan ekonomi. Penurunan reputasi Rinjani akibat insiden keselamatan atau degradasi lingkungan, seperti penumpukan 31 ton sampah yang dilaporkan , akan secara langsung mengancam daya tarik taman nasional. Pada gilirannya, hal ini akan berdampak parah pada ekonomi lokal senilai Rp109 miliar dan mata pencarian lebih dari 50.000 pekerja lokal. Oleh karena itu, alokasi PNBP yang transparan dan efektif untuk keselamatan dan konservasi bukan hanya kewajiban hukum atau etika, tetapi juga investasi ekonomi yang krusial untuk menjaga keberlanjutan seluruh ekosistem pariwisata dan melindungi kesejahteraan masyarakat lokal.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab oleh para pemangku kepentingan adalah: "Untuk siapa sebenarnya PNBP sebesar Rp22,5 miliar itu?" Jika jawabannya adalah negara, maka negara wajib bertanggung jawab atas keberlangsungan ekosistem dan keselamatan pengunjung. Jika jawabannya adalah masyarakat, maka mereka berhak atas jaminan pelayanan publik yang setara dengan kontribusi mereka.
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam dengan fungsi utama konservasi, pendidikan, dan pemanfaatan terbatas secara lestari. Maka dari itu, penggunaan dana PNBP harus mengikuti tiga koridor besar: (1) konservasi kawasan dan spesies endemik, (2) edukasi dan pelibatan publik, serta (3) penguatan sistem mitigasi risiko.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar dana PNBP lebih banyak digunakan untuk kebutuhan administratif dan operasional dasar. Transparansi penggunaan dana menjadi sorotan, terutama ketika masyarakat tidak melihat dampak langsung dari kontribusi yang telah mereka berikan. Sudah saatnya negara menerapkan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana PNBP taman nasional.
Lebih lanjut, masyarakat lokal sebagai pihak yang paling terdampak dari kebijakan pengelolaan kawasan, juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan alokasi PNBP. Apakah desa-desa penyangga merasakan manfaat? Apakah ada program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi yang konsisten berjalan? Jika tidak, maka dana sebesar itu hanya berputar dalam lingkaran birokrasi.
Kita juga perlu mendesak dibentuknya mekanisme evaluasi tahunan atas penggunaan dana PNBP taman nasional, dengan pelibatan unsur independen seperti akademisi, komunitas pendaki, dan LSM lingkungan. Evaluasi ini penting agar ada umpan balik konstruktif serta penguatan kelembagaan dalam menjamin tata kelola yang sehat.
Dengan pengelolaan yang transparan dan partisipatif, PNBP tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga instrumen pembangunan berkelanjutan di sekitar kawasan konservasi. Sebaliknya, jika terus dikelola tertutup, maka akan timbul ketidakpercayaan publik dan resistensi dari pemangku kepentingan lokal.
Identifikasi Titik Kritis dan Bahaya di Jalur Pendakian
Gunung Rinjani, meskipun menawarkan keindahan alam yang luar biasa, juga menyimpan tantangan dan risiko yang signifikan bagi para pendaki. Jalur pendakian menuju puncak, khususnya di atas Pelawangan Sembalun, diidentifikasi sebagai titik kritis yang sangat rentan terhadap kecelakaan. Medan di area ini digambarkan sangat terjal, berdebu, dan licin, meningkatkan potensi terpeleset dan jatuh. Tragedi terbaru yang menimpa Juliana Marins terjadi di sekitar titik Cemara Nunggal, sebuah area jurang dengan medan yang sangat ekstrem dan menantang. Kondisi berbahaya ini diperparah oleh keberadaan bebatuan yang mudah longsor, tikungan sempit di sisi jurang, serta cuaca ekstrem yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat.
Salah satu klaim yang mengkhawatirkan adalah hampir tidak adanya rambu keselamatan di titik-titik kritis pada jalur Rinjani. Kondisi ini diperkuat oleh rekomendasi langsung dari Menteri Kehutanan untuk segera memasang rambu-rambu yang memadai. Kurangnya penandaan yang jelas dapat membahayakan pendaki, terutama di area yang sulit dan berbahaya.
Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak akan fasilitas penyelamatan yang lebih baik. Asosiasi Trekking Gunung Rinjani Lombok Timur secara eksplisit menyatakan perlunya pusat penyelamatan (rescue center) khusus yang dapat menangani keadaan darurat dengan cepat dan efektif di Gunung Rinjani. Keluhan juga datang dari operator trekking (TO) yang meminta pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani untuk menyediakan peralatan penyelamatan dan P3K yang memadai. Permintaan ini mencakup ketersediaan tali panjang, jaket penahan dingin, dan makanan khusus untuk korban yang dievakuasi di Plawangan, menunjukkan bahwa fasilitas dasar seperti P3K, meskipun penting, seringkali terlupakan atau tidak memadai di lapangan.
Meskipun Balai TNGR memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi (P2E) yang rinci, yang meliputi mekanisme respons cepat, tim terlatih, dan persiapan sumber daya , terdapat kesenjangan yang mencolok dalam implementasi di lapangan. Kurangnya rambu keselamatan dan fasilitas P3K serta pusat penyelamatan yang memadai menunjukkan adanya masalah mendasar dalam alokasi sumber daya dan pengawasan yang efektif. Jika SOP yang ada mengamanatkan "persiapan sumber daya," namun infrastruktur keselamatan dasar seperti rambu dan pusat penyelamatan masih kurang atau tidak efektif, ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam eksekusi. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh anggaran yang tidak mencukupi untuk infrastruktur keselamatan spesifik, atau kurangnya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa SOP yang didokumentasikan benar-benar diterapkan di lapangan. Akibatnya, sistem keselamatan, meskipun memiliki kerangka kerja yang terperinci, tetap "sangat kurang" dalam aspek-aspek praktis yang krusial.
Peran Pemandu dan Porter: Kualifikasi, Pelatihan, dan Kondisi Kerja
Pemandu dan porter adalah tulang punggung operasional pendakian di Rinjani. Pada tahun 2024, tercatat 13.060 pemandu dan 36.425 porter terlibat dalam aktivitas ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas logistik perjalanan dan memastikan pendaki tidak tersesat, tetapi juga berperan krusial dalam menjaga keselamatan dan bahkan menjadi pahlawan tak terduga dalam situasi darurat, seperti yang ditunjukkan oleh aksi heroik porter Agam dalam evakuasi Juliana Marins.
Meskipun peran mereka sangat penting, Forum Wisata Lingkar Rinjani secara tegas menyarankan agar pemandu dan porter dibekali keterampilan pertolongan pertama dan memiliki sertifikat penyelamatan. Keluhan juga muncul bahwa porter dan pemandu jarang mendapatkan pelatihan yang memadai. Forum tersebut juga mendesak penerapan rasio pemandu-pendaki yang lebih ketat, misalnya satu pemandu untuk empat pendaki, dan menuntut gaji yang layak bagi porter dan pemandu agar Rinjani dapat mencapai standar keamanan kelas dunia.
Ketergantungan yang tinggi pada porter dan pemandu lokal sebagai garda terdepan dalam keselamatan, tanpa dukungan pelatihan dan kompensasi yang memadai, menciptakan risiko keselamatan yang signifikan dan potensi eksploitasi tenaga kerja informal. Jika personel di garis depan yang paling krusial ini kurang terlatih, kurang dilengkapi dengan keterampilan penyelamatan, dan kurang dihargai secara finansial, hal ini secara langsung membahayakan sistem keselamatan secara keseluruhan. Keberanian dan kepahlawanan informal mereka, meskipun patut diacungi jempol, tidak dapat menjadi pengganti bagi tenaga kerja penyelamat dan keselamatan yang profesional dan didukung penuh. Situasi ini juga menyoroti masalah yang lebih luas terkait hak-hak buruh dan perlakuan yang adil dalam sektor pariwisata, di mana manfaat ekonomi yang besar dari Rinjani (Rp109 miliar) tidak selalu terdistribusi secara merata kepada mereka yang melakukan pekerjaan paling berat dan berisiko.
Kolaborasi Antar-Kementerian
Upaya penguatan keselamatan dan konservasi tidak dapat dibebankan kepada Kementerian Kehutanan semata sebagai induk dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Diperlukan keterlibatan aktif dari Kementerian Pariwisata dalam menstandarkan sistem keselamatan wisata alam di seluruh taman nasional yang telah dibuka sebagai destinasi wisata massal. Begitu juga dengan Basarnas, yang harus membangun protokol kerja sama terpadu dengan pengelola taman nasional.
Kementerian Pariwisata memiliki sumber daya dan jaringan yang luas dalam mengembangkan destinasi wisata unggulan. Namun, belum banyak terlihat keterlibatan aktif mereka dalam merumuskan standar keselamatan wisata petualangan seperti pendakian gunung. Rinjani dapat menjadi pilot project dalam menyusun kebijakan bersama antara kementerian agar terjadi sinergi yang nyata di lapangan.
Peran Basarnas juga sangat vital, bukan hanya dalam evakuasi, tetapi dalam edukasi, pelatihan, dan pengembangan tim penyelamat lokal. Basarnas dapat melatih warga sekitar sebagai bagian dari tim tanggap darurat berbasis komunitas, yang dalam praktiknya jauh lebih cepat menjangkau lokasi kecelakaan dibandingkan tim pusat.
Selain itu, teknologi juga perlu diarusutamakan. Kolaborasi dengan BRIN atau lembaga riset lainnya dapat mempercepat adopsi teknologi seperti drone pemantau cuaca, pemetaan digital jalur evakuasi, dan sistem peringatan dini. Teknologi lokal tidak kalah mumpuni, hanya butuh keberanian untuk diimplementasikan.
Kolaborasi ini juga harus dituangkan dalam regulasi bersama-bukan hanya MoU seremonial-agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Termasuk pula penguatan anggaran lintas sektor yang memungkinkan kegiatan penyelamatan dan edukasi dilakukan secara konsisten sepanjang tahun.
Pada akhirnya, keberhasilan kolaborasi antar-kementerian akan menentukan arah masa depan wisata alam Indonesia. Jika keselamatan dan konservasi menjadi prioritas bersama, maka sektor ini bukan hanya akan berkelanjutan, tetapi juga bermartabat dan adil bagi semua pihak.
Gunung Rinjani telah menjadi sumber inspirasi, penghidupan, sekaligus kebanggaan bagi masyarakat NTB dan Indonesia. Tapi rasa bangga itu akan timpang jika tidak diiringi dengan rasa tanggung jawab untuk melindunginya. Negara, dalam hal ini kementerian terkait, harus menjawab tantangan zaman: dari sekadar menarik wisatawan menjadi penyedia perlindungan sejati.
Sebagai penikmat Rinjani dan wakil rakyat yang sering mendapat aspirasi dari komunitas pendaki, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan bahwa dana yang dihasilkan dari aktivitas wisata di Rinjani benar-benar kembali pada fungsi konservasi, edukasi, dan keselamatan. Jangan biarkan Rinjani menjadi tempat di mana pendaki membayar mahal, tetapi keselamatan mereka dibiarkan murah. Karena sejatinya, gunung bukan tempat berbisnis semata, melainkan ruang suci yang wajib kita jaga bersama.
Tragedi yang menimpa wisatawan Brasil harus menjadi alarm kolektif kita. Ke depan, tidak boleh lagi ada korban jiwa yang terjadi karena kelalaian sistem, minimnya fasilitas, atau tumpang tindih kewenangan. Indonesia harus membuktikan bahwa menjadi destinasi wisata kelas dunia juga berarti menjadi negara yang bertanggung jawab dalam keselamatan dan perlindungan nyawa setiap tamu yang datang. Inilah saatnya kita berubah, sebelum korban berikutnya jatuh sia-sia.
Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR-RI, Dapil NTB 1 FPKS, penikmat dan pencinta Rinjani
(gbr/gbr)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini