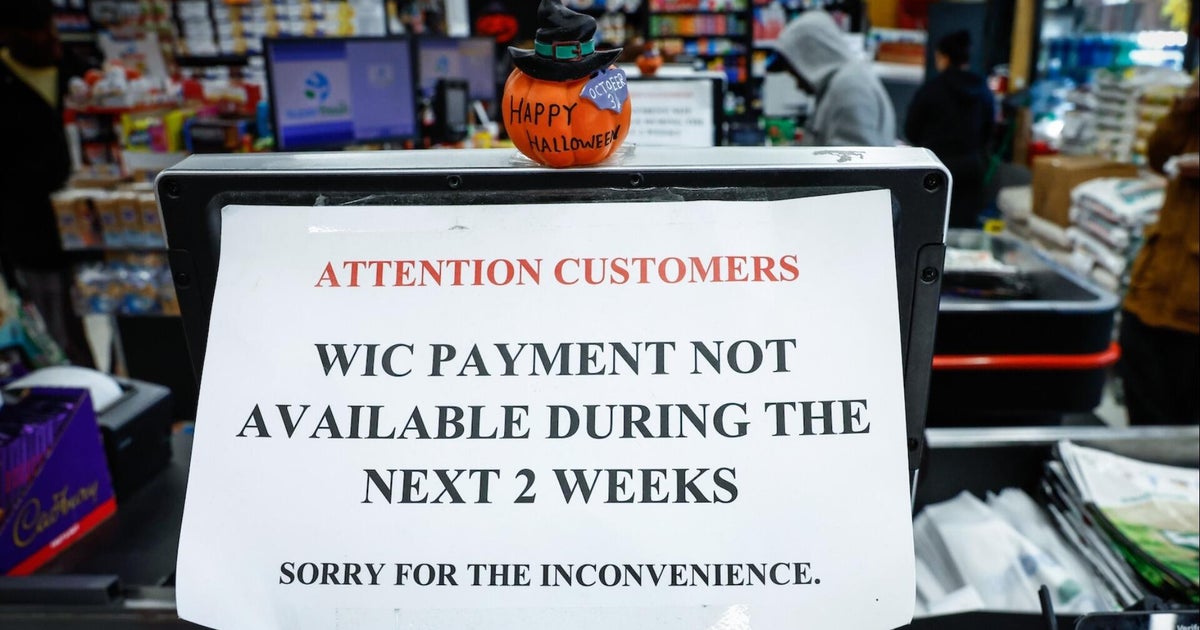Ilustrasi : Edi Wahyono
Selasa, 1 Juli 2025
Mahmudin lahir dan besar di pesisir Marunda. Sejak dulu ia menggantungkan hidup dari menangkap udang di tepi muara laut, menggunakan bubu. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan delapan jam di muara dan tepian laut. Biasanya ia mampu membawa pulang 4 hingga 5 kilogram udang segar. Itu cukup untuk menghidupi lima anggota keluarga—tiga anak dan seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga. Namun, dalam empat bulan terakhir, Mahmudin tidak lagi bisa menangkap udang.
“Kami (pasang) bubu di tepi ya kena (limbah) busa itu, udang hilang,” ucap laki-laki berusia 45 tahun itu saat ditemui detikX pada Rabu, 25 Juni 2025.
Limbah busa muncul hampir setiap kali hujan. Mahmudin menyaksikan sendiri bagaimana busa itu mengalir di sepanjang muara Banjir Kanal Timur hingga ke laut.
“Banyak sampai ke laut,” tuturnya.
Busa itu memengaruhi ekosistem pesisir, memaksa udang menjauh dari garis pantai. Sejak kesulitan mendapatkan udang, Mahmudin beralih menjadi nelayan rawe—penangkap ikan di laut tengah. Sayangnya, perahu kecilnya tidak dirancang untuk menghadapi gelombang tinggi.
“Bahaya juga kalau ke tengah, kan perahunya kecil,” katanya.
Waktu kerja pun jadi lebih lama, hingga 24 jam. Sementara itu, biaya tenaga bahan bakar membengkak. “Pakai solar Rp 150 ribu sampai 200 ribu, jadi kepotong banyak,” ungkapnya.
Dulu, dari hasil tangkapan udang, Mahmudin bisa memperoleh Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per hari. Dalam sebulan, pendapatannya bisa mencapai Rp 3-4 juta, tapi kini penghasilan itu anjlok drastis.
Selain polutan dari arah hulu kali yang menghasilkan busa, warga juga dihantui limbah-limbah berbau menyengat yang berasal dari kawasan industri di sekitar Marunda.
“Bau, ikan sampai mati, sebulan baru hilang,” ujarnya.

Suasana limbah busa di kawasan Pintu Air Banjir Kanal Timur (BKT) Marunda, Jakarta Utara, Senin (23/6/2025).
Foto : Pradita Utama/detikcom
Menurutnya, jika ada limbah yang dibuang ke muara dan pesisir laut, nelayan tidak bisa bekerja seperti biasa. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan, mereka harus beralih pekerjaan sementara menjadi kuli.
Meski para nelayan pernah menyampaikan keluhan, hasilnya nihil. “Ya nelayan sini sudah pernah ngeluh semua, ngeluh ke dinas percuma kayaknya,” keluhnya.
Di tengah kesulitan itu, Mahmudin hanya berharap, jika tidak mampu sepenuhnya menghilangkan paparan limbah, setidaknya pemerintah mampu mengurangi keberadaan limbah yang terbukti merugikan warga.
Hal serupa dialami oleh Adul, seorang nelayan yang tinggal di kawasan pesisir Marunda sejak 2002. Pada usianya yang menginjak 62 tahun, ia masih rutin ke laut saban pagi pukul enam. Dengan bagan serok, ia mengandalkan hasil tangkapan udang untuk hidup. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kondisi perairan berubah drastis.
Ia menyebut satu penyebab yang paling menyulitkan, yakni limbah. Limbah mengalir dari arah hulu sungai dan menghasilkan busa-busa putih di muara. Selain itu, ada limbah kimia yang, menurutnya, berasal dari pabrik-pabrik di kawasan industri sekitar Marunda.
Limbah tersebut, menurutnya, dibuang secara diam-diam saat hujan, seminggu sekali. Modusnya pembuangan limbah dilakukan berbarengan dengan turunnya hujan. Ini untuk menyamarkan tindakan.
"Pabrik gula, pabrik oli, minyak tuh. Nah itu. Tapi kan kita mau bagaimana memangnya? Kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain dah," sambungnya.
Adul dan rekan-rekannya sudah beberapa kali mengadu dan melakukan demonstrasi sebanyak tiga kali ke pelaku industri. Namun tidak ada tanggapan serius dari pihak berwenang maupun pelaku industri. Justru warga yang protes, menurut Adul, dianggap sebagai perusuh.
Padahal paparan buruk berdampak langsung terhadap penghasilan orang dewasa. Dulu ia bisa memperoleh Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu sehari, kini ia hanya bisa mengumpulkan puluhan ribu rupiah. Akibat paparan limbah, ikan-ikan yang biasanya mudah ditangkap juga sudah sulit ditemui.
“Saya saja ini sudah hampir sebulan, Pak. Penghasilannya paling Rp 30 ribu, Rp 40 ribu,” ucapnya.

Busa putih yang mengambang di permukaan air sungai Jakarta bukan sekadar gangguan visual. Menurut Manajer Divisi Advokasi Ecoton Alex Rahmatullah, busa adalah gejala dari krisis lingkungan yang lebih dalam. Busa-busa itu berasal dari akumulasi limbah industri dan domestik yang mencemari aliran sungai hingga ke laut.
“Kami sebenarnya dari dua hari yang lalu, habis dari sana, habis dari yang di Pintu Air Marunda,” ujar Alex kepada detikX pada Jumat lalu.
Ia mengatakan kasus di Jakarta mirip dengan yang terjadi di Tambak Wedi, Surabaya, dan daerah pesisir utara Jawa lainnya. Sumber utama busa itu, kata Alex, adalah fosfat dan surfaktan—zat kimia dari detergen rumah tangga maupun limbah industri. Keduanya sangat tinggi kadarnya, bahkan melebihi lima kali lipat dari baku mutu.
“Kalau sungai berbusa, otomatis ikan-ikan yang sangat sensitif, dia akan pindah, bermigrasi. Bahkan tidak jarang bisa sampai mati,” paparnya.
Paparan limbah tersebut turut memicu mekarnya alga. Pertumbuhan alga yang berlebihan akibat tingginya fosfat menyebabkan kadar oksigen dalam air menurun.
“Ketika (kadar oksigen) menurun, akan berpengaruh terhadap biota, terutama ikan,” jelasnya.
Hanya sedikit jenis ikan yang toleran terhadap kondisi tersebut, seperti lele atau mujair. Sisanya, terutama ikan sensitif: mati atau bermigrasi. Dampaknya juga tidak berhenti pada air dan ikan saja.
“Ikannya dimakan manusia, otomatis akan terjadi yang namanya biomagnifikasi. Polutannya akan tersalurkan ke manusia, dan itu bisa berdampak pada kesehatan,” ujar Alex.
Ecoton juga menemukan partikel mikroplastik dalam jumlah besar saat pengambilan sampel udara di muara Banjir Kanal Timur, Jakarta. Dalam 1 liter sampel udara ditemukan 103 partikel plastik. Kondisinya jauh di atas rata-rata temuan di daerah hulu, yang hanya 20-30 partikel per liter. Partikel itu berasal dari fiber tekstil dan plastik tipis.
"Artinya benar. Ketika orang-orang mencuci baju, limbahnya dibuang ke sungai. Kemudian yang kedua ada film atau filamen. Itu berasal dari plastik-plastik tipis seperti kresek ataupun kemasan jajanan makanan," ucapnya.

Pedayung nomor kayak DKI Jakarta Muhammad Fajar Maulana berlatih di antara busa-busa limbah di Sungai Banjir Kanal Timur, Marunda, Jakarta, Rabu (17/8/2022).
Foto : Aditya Pradana Putra/Antarafoto
Kondisi ini, menurut Alex, diperparah oleh lemahnya pengawasan dan lambannya pemerintah bertindak.
“DLH juga seharusnya punya data ini ya, inventarisasi industri yang berdiri di sepanjang bantaran ataupun yang membuang limbahnya ke sungai. Harapannya, harus menginspeksi itu,” tegas Alex.
Dari pengalaman Ecoton di Sungai Brantas, Jawa Timur, Alex mengingatkan paparan limbah tertentu bahkan menyebabkan interseks pada ikan (satu individu ikan memiliki dua jenis kelamin).
“Hampir 30 persen ikan di Sungai Brantas itu mengalami yang namanya interseks. Jadi ikannya ini tidak akan bisa bertelur, tidak akan bisa berkembang biak, sehingga terancam kepunahan.”
Untuk mengatasi dan mencegah dampak lebih buruk di Jakarta, Alex menekankan pentingnya pemerintah membangun IPAL komunal, yaitu sistem pengolahan air limbah domestik yang dilakukan dengan cara terjangkau. Selain itu, pemerintah diminta tegas menindak pelaku industri nakal yang membuang limbah tanpa pengolahan yang mampu sebelumnya.
“Kalau sungai terus dibiarkan seperti ini, bukan hanya ikan yang akan punah, tapi air bersih juga akan semakin langka bagi manusia,” ucapnya.
Limbah busa yang muncul di Kali BKT (Banjir Kanal Timur), terutama di sekitar Pintu Air Marunda, bukanlah fenomena baru bagi Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Kepala Seksi Pengawasan dan Penaatan Hukum DLH Jakarta Abdur Rochman, mengungkap pengaduan serupa sudah masuk sejak 2016.
“Pengaduan ini sudah berlangsung sejak 9 tahun yang lalu ya, pada 2016 itu di data kami ada beberapa pengaduan sejenis yang berhubungan dengan busa yang timbul di BKT,” kata Abdur.
Ia menjelaskan, berdasarkan pemantauan rutin di 13 sungai besar di Jakarta, termasuk BKT, hasil pemantauan 2024-2025 menunjukkan kualitas udara di BKT bagian hilir berada dalam kategori cemar sedang hingga cemar berat. Abdur menyebut kategori cemar berat terjadi sebanyak empat kali (22 persen) dari 18 kali pengambilan sampel.
DLH mengklaim telah berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA), untuk membangun sistem IPAL komunal. Selain itu, pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) diklaim sedang berlangsung di wilayah Penjaringan.
Reporter: Ahmad Thovan Sugandi, Ani Mardatila, Fajar Yusuf Rasdianto
Penulis: Ahmad Thovan Sugandi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Fuad Hasim