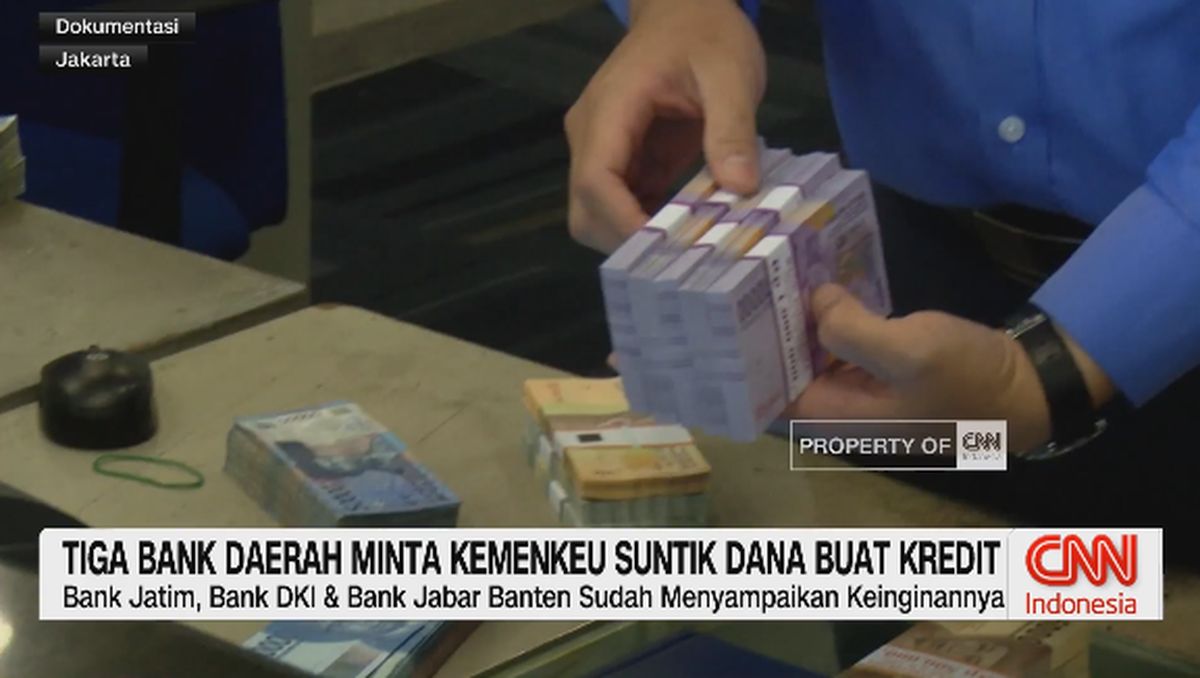Setiap pagi, sebelum membuka mata sepenuhnya, Salma Putri Ramadhani sudah mengulurkan tangan ke meja samping tempat tidurnya. Bukan untuk segelas air, bukan pula untuk menyentuh wajah suaminya yang masih lelap, melainkan untuk sebuah smartphone yang kini seperti perpanjangan dari tubuhnya. Jari-jarinya sudah hafal gerakan membuka layar, masuk ke TikTok, dan mulai menggulir tanpa berpikir. Kadang video lucu, kadang resep simpel, kadang berita politik, semua mengalir tanpa urutan, tanpa waktu yang jelas.
"Aku cuma mau lihat sebentar, lima menit, lah. Tapi tahu-tahu sudah satu jam. Bahkan bisa lebih," kata Salma, perempuan berusia 35 tahun, seorang freelancer asal Depok.
Awalnya, TikTok adalah pengusir sepi. Tapi kini, aplikasi itu menjadi habitat harian. Bahkan untuk sekadar mencari definisi atau informasi ringan, Salma tak lagi membuka Google. “Lebih cepat lihat TikTok aja, banyak yang jelasin singkat pakai suara lucu, jadi gampang ngerti,” jelasnya.
Namun belakangan, Salma mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia makin sering lupa hal-hal sederhana, kata-kata dalam percakapan, ide konten yang baru terpikirkan sejam lalu, bahkan lupa letak barang. Yang paling terasa, ia kesulitan untuk duduk diam dan membaca sesuatu yang panjang. “Buka dokumen kerjaan lebih dari dua halaman aja langsung pusing. Rasanya mau cepat selesai, tapi otak nolak,” katanya.
Fenomena yang dialami Salma dikenal dengan istilah brain rot atau pembusukan otak. Istilah ini mendadak populer dan bahkan dinobatkan sebagai Word of The Year 2024 oleh Oxford University. Menurut catatan mereka, istilah ini mencerminkan realitas budaya digital saat ini, masa ketika banyak orang merasakan penurunan kapasitas kognitif, seperti sulit fokus, rentang perhatian menyusut, dan kelelahan mental akibat konsumsi konten instan.
Dr. Andreana Benitez, dosen di departemen neurologi Medical University of South Carolina, menyebutnya sebagai ‘junk food untuk otak’. Sama seperti makan keripik yang membuat kenyang tapi tidak menyehatkan, konten instan yang dikonsumsi berjam-jam dapat membuat otak kehilangan kemampuan berpikir dalam dan reflektif.
Ardi Wijaya, 21 tahun, mahasiswa desain komunikasi visual di salah satu kampus swasta di Jakarta Barat, menyebut dirinya sebagai korban ‘otak keropos digital’. Ia sadar betul bahwa sejak pandemi, dunianya beralih ke layar, kelas online, tugas, hiburan, semuanya dari satu gawai yang sama. Tapi sejak TikTok menjadi bagian dari rutinitasnya, ia merasa kemampuannya menyerap informasi mulai berubah.
“Gara-gara TikTok, fokus saya nggak bisa lama. Nonton video panjang jadi capek, baca artikel lebih dari tiga paragraf rasanya berat,” ujarnya.
Dalam wawancara dengan TODAY, Marci Cottingham, profesor sosiologi di Kenyon College, menggambarkan pengalaman pribadi yang serupa. “Saya mengalami perasaan ini setelah berjam-jam menonton TikTok,” katanya. Cottingham menyebut brain rot sebagai respons sosial atas situasi budaya saat ini, ketika orang merasa kehilangan arah untuk bertindak secara individu atau kolektif.
Laporan We Are Social dan Meltwater 2024 menyebut Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar kedua di dunia, sebanyak 107 juta orang berusia di atas 18 tahun, hanya kalah dari Amerika Serikat. Dan tak tanggung-tanggung, pengguna aktif di Indonesia menghabiskan rata-rata 44 jam 54 menit per bulan hanya untuk menonton di TikTok lewat Android.
Tak heran, platform ini menjadi medan utama brain rot menyebar. Dalam studi yang dipublikasikan oleh jurnal Brain Sciences awal 2025, ditemukan bahwa konsumsi media sosial secara berlebihan, ditambah waktu layar (screen time) yang ekstrem, bisa memicu gejala-gejala seperti kabut otak, kehilangan memori jangka pendek, ketidakmampuan fokus, dan kecenderungan untuk mencari kepuasan instan.
“Rasanya seperti otak saya dilatih untuk berpikir cepat tapi dangkal,” ujar Ardi. Ia bahkan pernah mencoba puasa gadget selama satu hari. Tapi alih-alih merasa segar, ia justru gelisah dan tak tahu harus mengisi waktu dengan apa. "Buku kuliah dibuka, langsung menguap. Kalau buka TikTok, walau enggak ngapa-ngapain, otak kayak terhibur."
Sayangnya, dampak brain rot bukan cuma soal malas membaca atau gampang lupa. Di dunia pendidikan, fenomena ini mulai terasa mengikis motivasi belajar siswa. Nur Islamiah, PhD, psikolog dari IPB University, menjelaskan bahwa siswa yang terbiasa mengonsumsi konten instan mengalami penurunan motivasi dalam tugas akademik yang menuntut proses berpikir mendalam.
“Ketika otak terus-menerus menerima rangsangan dari media sosial atau konten hiburan, aktivitas belajar yang lebih statis terasa membosankan dan kurang menarik,” katanya dikutip dari laman IPB. Ia menambahkan, siswa jadi lebih menyukai aktivitas yang memberikan kepuasan instan, daripada proses belajar yang membutuhkan ketekunan.
Fenomena brain rot juga menghantui anak-anak yang masih dalam masa perkembangan otak. Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq bahkan menyebut tsunami digital sebagai ancaman nyata untuk generasi usia dini. Ia menyebut bahwa 33,4% anak usia 0-6 tahun sudah terbiasa menggunakan gawai, dan angka ini melonjak pada anak usia 5-6 tahun hingga 52%.
“Kita sedang menghadapi tantangan besar. Brain rot ini bisa mengikis stimulasi intelektual, emosional, dan sosial anak sejak dini,” ujar Fajar dalam sebuah kegiatan PAUD Holistik Integratif.
Peneliti dari IPB, Melly Latifah, juga menambahkan bahwa anak-anak yang kecanduan gawai menunjukkan perilaku seperti sulit melepaskan diri dari layar, mudah marah saat dibatasi, dan mengabaikan kegiatan bermanfaat lain seperti bermain atau membaca buku.
Namun, apakah semua konten digital harus dihindari? Tidak juga. Menurut Dr. Constantino Iadecola dari Weill Cornell Medical Centre, konten digital tidak semuanya buruk, selama digunakan dengan seimbang dan diarahkan ke aktivitas kreatif dan edukatif. Tapi ia menegaskan bahwa otak manusia, terutama yang masih berkembang, membutuhkan pengalaman nyata. Sentuhan, emosi, gerak fisik, dan interaksi langsung. Tanpa itu, otak bisa kehilangan sebagian fungsi pentingnya.
Seperti junk food, kata Andreana Benitez, konsumsi layar boleh saja sesekali. Tapi jika terlalu sering, maka kita bukan hanya membuang waktu, melainkan juga daya pikir. Dan seperti Ardi yang kini sedang berusaha kembali membaca buku lebih dari sepuluh halaman, atau Salma yang mencoba membatasi waktu TikTok hanya di malam hari, mungkin kita semua memang harus mengingat bahwa otak juga butuh istirahat. Bukan hanya dari lelah, tapi dari keterpakuan pada hal-hal instan yang seolah membuat kita sibuk, padahal otak kita tidak benar-benar bekerja.